Semacam pengantar: Dalam rangka menyambut diterbitkannya kembali Seikat Kisah Tentang yang Bohong, kumpulan cerpen saya, di sini saya menurunkan ulasan dari Kak Jenni Anggita atas buku tersebut. Seikat Kisah Tentang yang Bohong awalnya diterbitkan oleh Penerbit Alpha Centauri (Yogyakarta) pada 2016. Pada awal 2020, buku ini diterbitkan ulang oleh Penerbit Buku Mojok (Yogyakarta).
Mengenai tulisan Kak Jenni Anggita ini, awalnya merupakan tulisan pengantar untuk diskusi atas buku Seikat Kisah tentang Yang Bohong pada terbitan pertamanya, 2016 silam. Diskusi tersebut diadakan oleh Komunitas Agenda 18 bertempat di Yayasan Obor Indonesia, Jakarta pada Sabtu, 4 Maret 2017. Lantas, tulisan Jenni ini dipublikasikan pertama kali di website Agenda 18. Di dalam diskusi yang dimaksud, Kak Jenni bersama Bung Heru adalah pembedahnya.

Fiksi dapat membuat kita tenggelam pada suatu dunia antah-berantah. Dunia rekaan itu kadang bagai labirin yang sulit sekali untuk dicari jalan keluarnya. Kendati demikian, fiksi selalu menawarkan kita pada sebuah kemungkinan ber-refleksi. Baik itu bercermin untuk diri sendiri atau cerminan masyarakat.
Seikat Kisah yang Bohong karya Berto Tukan membawa saya masuk ke dalam perjalanan sebuah dunia rekaan yang bagai labirin itu, yang membuat saya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh sang pengarang. Kendati beberapa cerita sulit dipahami, saya justru semakin berhasrat untuk mencari tahu di mana letak jalan keluarnya.
Saya ingat sebuah pernyataan Melani Budianta bahwa sebuah fiksi yang bagus adalah yang dapat menyentuh ke dalaman hati pembacanya. Bertolak dari pendapat itu, saya tertarik pada hal-hal remeh-temeh, yang banal dalam cerita.
Tema yang tertuang dalam cerita merupakan realita kehidupan manusia dalam persoalan sehari-hari berupa percintaan, rindu, kenangan, kehilangan, kesepian, kehampaan, kekhawatiran yang berjalin berkelindan antara imajinasi dan realita dalam dunia rekaan. Di beberapa cerpen, tokoh-tokoh dapat begitu saja hadir, hilang, lalu hadir kembali. Sudut pandang dapat berganti-ganti. Alur tak linear. Adanya interteks yang memungkinkan ditelusuri lebih dalam sekaligus menggambarkan kekayaan pengarang dalam membaca berbagai buku. Maka, kumpulan cerpen ini seperti kepingan puzzle yang mengajak pembaca untuk menyusunnya dan berusaha menyatukannya kembali menjadi sebuah kepingan yang utuh. Barangkali kutipan berikut dalam “Semper Reformanda” berikut ini menegaskan pemikiran atau suara si penulis:

“Gawat. Aku bercerita tentang sesuatu yang tak kuketahi sama sekali… Bolehlah Umberto Eco mengiyakan seorang penulis sebagai pembohong, tetapi menuliskan sesuatu yang sebenarnya tak kita ketahui memang sungguh menggelisahkan dan mengecewakan. Ah, mereka-reka. Seperti merekayasa. Berimajinasi. Mungkin sebuah kemampuan yang dimiliki binatang. Namun Descartes menyebutnya dengan berpikir. Kurasa mungkin lebih tepat disebut berimajinasi atau mereka-reka” (hlm 100).
Hal berikut inilah yang kemudian menarik perhatian saya dalam cerita, yakni perihal bagaimana melalui hal-hal kecil, berupa latar, yang barangkali sambil lalu ditulis, justru merepresentasikan kota dan kampung[1], serta tarik-menarik realitas masyarakat perkotaan dengan kepercayaan atau mitos-mitos masyarakat kampung.
Ruang Kota, Problematika Masyarakat Urban
Modernitas kota dalam cerita tampil berupa simbol-simbol yang remeh-temeh atau sekadar menjadi penghias latar atau penghias tokoh seperti kedai kopi dan kopinya, rokok serta mereknya, sejumlah kendaraan umum seperti mobil dan mereknya (BMW, APV, Pajero)[2], laju sepeda motor, bus kota, kereta, iklan, Facebook, Yahoo Messenger, atau pembicaraan selingan antartokoh seperti korupsi. Dari merek-merek barang yang ada di cerita, menunjukkan tokoh-tokohnya hidup dalam ruang perkotaan yang seperti kita juga di dunia nyata: menjadi konsumen atas berbagai barang-barang.
Eksplorasi ruang kota melalui kedai kopi menjadi pembuka cerita dalam “Kedai Kopi Oriental”. Gaya hidup khas perkotaan kelas menengah berupa ngopi dan nongkrong bersama kawan di kedai kopi yang tengah menjamur. Cerita dibagi menjadi tiga fragmen: percintaan dua sejoli di kedai, laki-laki hitam yang bicara pada sosok perempuan keturunan di iklan, dan perempuan penjaga toko yang khawatir sebentar lagi pekerjaannya hilang karena usianya akan menginjak 30. Demikianlah, bagaimana problematika masyarakat urban yang beragam.
Jika perempuan penjaga toko—yang menjadi salah satu tokoh “Kedai Kopi Oriental” sudah bekerja, tetapi cemas kehilangan pekerjaan, dalam “Seikat Kisah Tentang yang Bohong” menampilkan persoalan mahasiswa baru lulus yang terjebak pada paradoks kehidupan. Di satu sisi merasa kelulusan berarti menjadi manusia seutuhnya dan dapat membanggakan orangtua, namun di sisi lain berbenturan dengan kenyataan bahwa selama enam bulan menjadi pengangguran. Mengangkat percintaan sesama jenis, cerpen itu menjadi cerita menarik yang dibuka dengan seorang perempuan keturunan (Tionghoa) yang tertabrak kereta. Kemudian, persoalan dililit utang hadir di dua cerpen: dilema penagih utang yang menagih perempuan cantik dalam “Debt Collector”, dan dalam “Anak Lelaki dan Langit Sewarna Darah”:
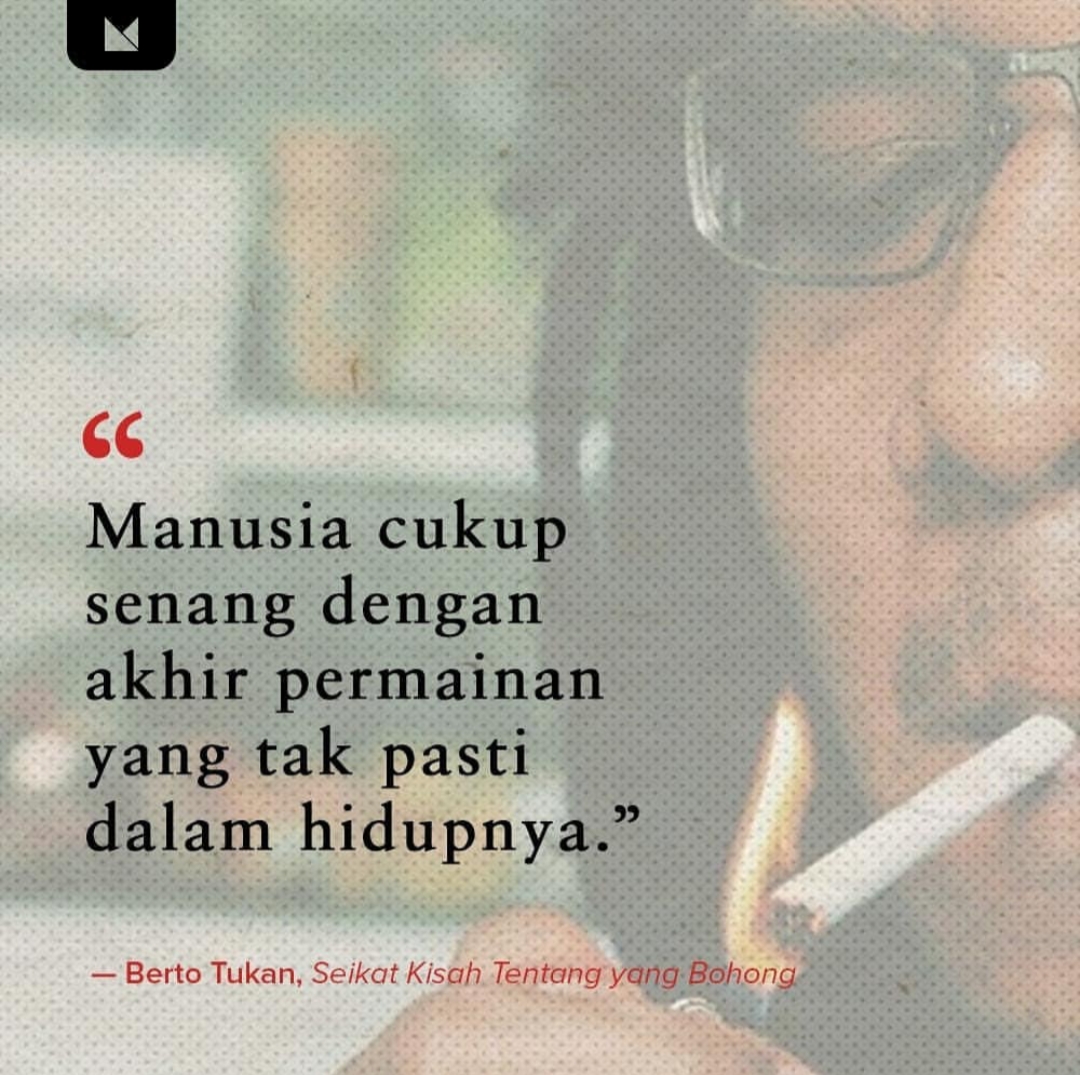
“Di dekat pesawat televisi baru keluaran Tiongkok yang belum lunas kreditnya…” (hlm.12).
“Banyak utang, sebentar lagi harus bayar dokter. Dengan apa?” (hlm. 36).
Tema kesepian tampak dalam “Titian” yang bercerita tentang tokoh “aku” yang menyembuhkan kesepiannya dengan menemukan sahabat lewat telepon. Selanjutnya, cerita percakapan Rich dan Eve soal kemajuan teknologi berupa telepon yang mempermudah komunikasi antarmanusia di masa kini, meski terbentang jarak yang jauh.
Ruang kota digambarkan tidak manusiawi sebagaimana realitanya. Persoalan keterbatasan ruang di pemukiman padat penduduk di Jakarta berupa rumah yang sempit; kendaraan umum dan motor berseliweran tidak karuan di jalan-jalan; infrastruktur yang tidak “ramah” bagi pengguna jalan; kemacetan yang mendera setiap hari. Penggambaran tersebut diulang dalam beberapa cerita. Disertai dengan pertanyaan seolah mengajak pembaca ber-refleksi atau sekadar satir kepada pihak penguasa:
“…ditambah lagi dengan kamar sebuah rumah di kawasan padat Jakarta yang sirkulasi udaranya jauh dari menyehatkan” (hlm. 110-111).
“Jalanan telah menunjukkan dampak keegoisan manusia atasnya; macet yang seakan niscaya bagaikan siang dan malam itu telah berlaku lagi. Kapankah jalanan menjadi ramah di kota ini? Kapankah jalanan menjadi semulis kulit Miss Universe asal Rusia?” (hlm. 119).
Dalam “Kedai Kopi Oriental” kota menjadi tempat yang tidak bersahabat bagi pendatang. Selanjutnya, tokoh “aku” justru dengan sangat halus menyindir penghuni kota yang telah terbiasa dengan lalu-lintas kota:
“Ah, lalu lintas kota ini memang bangsat. Mungkin nanti aku akan sampai pada kesimpulan bahwa lalu-lintasnya bisa membuat semangatmu berkobar-kobar padam seketika. Tapi entahlah. Banyak penghuni kota ini biasa-biasa saja dengan lalu lintas yang demikian. Mungkin karena aku orang baru aku butuh penyesuaian sejenak” (hlm. 8).
Inilah gambaran masyarakat urban yang selalu terburu-buru dan tidak menikmati perjalanannya di kota, entah itu supaya tepat waktu, menghindari macet, atau mengejar kereta dalam “Sebuah Perempatan Pukul Lima Petang”. Tokoh-tokoh tersebut hadir merepresentasikan realitas kehidupan penduduk kota bak robot karena hanyut pada rutinitas sehari-hari dan habis dimangsa penatnya jalan Ibukota sehingga tidak punya lagi waktu bersantai, memperhatikan sekitar, atau merefleksikan kehidupan:
“Orang berseliweran, berjalan bergegas. Bergegas mengejar jalanan, menghindari aksi dia bumi; membiarkan macet terjadi di mana-mana. Bergegas menjemput payung di rumah agar bisa bebas dari jejalan tubuh penuh keringat. Bergegas menyilih macet, bergegas mengejar kopi panas, bergegas mengejar… Begitu banyak orang bergegas di trotoar, di seperempat badan jalan” (hlm.123).
Tokoh-tokoh dalam cerita tidak hadir begitu saja hanya sebagai tambahan, melainkan diberi pula “pemanis” yang ikut membentuk dinamika masyarakat urban. Misalnya saja dalam “Malam Penuh Kecoak”, tokoh supir yang terinspirasi tokoh “Satir” memasang togel setelah mendengar “Satir” mimpi dikerumuti kecoak. Sementara rasionalitas yang merepresentasikan masyarakat urban tampak pada pikiran tokoh “Satir” usai bangun mimpi:
“Ah cuma mimpi, bunga tidur halusinasi. Aku orang rasional. Aku tak percaya hal-hal aneh, apalagi berbau mistik dan sebangsanya itu. Bagiku, semua kejadian pasti punya pertalian hubungan sebab akibat. Tak ada yang terberi begitu saja” (hlm. 161).
Sebagaimana kehidupan sehari-hari yang bisa saja ada kejutan, tak melulu begitu, atau tidak hanya menampilkan satu persoalan, begitu pun cerita-cerita Berto. Dalam satu cerita kita dapat menemukan dua realitas yang berjalin berkelindan antara tokohnya. Setiap tokoh punya suara dan cerita sendiri. Sulit memang untuk dipahami, namun sekaligus menarik. Maka usaha menampilkan realitas yang tidak tunggal memunculkan kemungkinan interpretasi atau pemaknaan ganda.
Cerpen “Manekin” bercerita tentang memori seorang istri dan ibu yang dengan sengaja dimusnahkan oleh si suami, sementara sang anak berusaha mencari memori itu melalui gaun usang yang dipakai manekin di sebuah toko. Manekin itu sendiri menjadi saksi perselingkuhan penjaga toko dan kakek pemilik toko. Karena gaun manekin itu dibeli dan manekin menyadari ketelanjangannya, yang berbeda dari tubuh perempuan penjaga toko yang dilihatnya ketika bercinta dengan kakek pemilik toko. Manekin itu kemudian berlari di jalan dan hancur karena menjatuhkan diri dari atas jembatan. Isu mengenai tubuh perempuan menjadi tema besar cerpen ini.
Pada beberapa cerpen, rasionalitas yang harusnya lekat pada masyarakat urban berusaha dibenturkan dengan yang irasional: imajinasi tokoh atau benda-benda mati yang menjadi hidup[3]. Maka rasionalitas yang dianggap dimiliki oleh masyarakat urban, tidak demikian adanya, karena mereka pun masih membutuhkan imajinasi sebagai penawar kehidupan atau realitas yang menjemukan. Misalnya pada cerpen “Henri Kecil, Sobat-sobitnya, dan Peta yang Tak Sempurna”.
Tokoh-tokoh dalam cerita yang merepresentasikan masyarakat perkotaan membuat saya teringat pada Herbert Marcuse[4] dalam bukunya One Dimensional Man. Gambaran tokoh-tokoh tersebut adalah gambaran masyarakat modern di era kapitalisme dan kecanggihan teknologi. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sakit, yang berpikir dan bertindak dalam satu dimensi, yaitu suatu masyarakat yang seluruh aspek kehidupannya diarahkan pada satu tujuan belaka[5]. Canggihnya teknologi membuat manusia kehilangan kesadaran kritisnya. Merasa memiliki kebebasan, namun kebebasan itu semu karena terbelenggu pada sistem kapitalisme yang menindas. Selayaknya kita di dunia nyata, tokoh-tokoh dalam cerita teralienasi dari dirinya sendiri dan kehidupannya—sesama dan lingkungan.

Memori, Representasi Kampung
Dalam “Sebuah Perempatan Pukul Lima Petang”, usai turun dari bus kota, Tarso mengingat memori tentang masa kanak-kanak yang mengasyikkan: bermain bola atau layang-layang. Kemudian pembaca akan masuk pada latar kampung berupa gang-gang sempit tempat bermain petak umpet. Namun, diakhiri dengan ironi bahwa tanah lapang tempatnya bermain telah berdiri gedung bertingkat.
Persoalan sebuah kampung yang membawa memori kolektif peristiwa penjagalan direpresentasikan melalui memori seorang lelaki tua yang bercerita kepada tokoh aku tentang penjagalan yang dilakukan beberapa warga yang melibatkan Uje terhadap mereka yang dicurigai pemberontak. Sementara Uje setelah peristiwa itu hilang entah di mana. Meski tidak secara tersurat latar kejadian ini ditulis, kita dapat langsung mengasosiakan pada peristiwa ’65.
Selain itu, persoalan kemiskinan yang erat pada masyarakat kampung tertuang dalam cerpen “Ina”. Seperti juga dalam “Vayu”, kampung digambarkan yang telah melek informasi ternyata tidak membantu apa-apa karena realita kehidupan membawa tokoh-tokoh kembali berpikir bagaimana mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup:
“Di kampung sekarang sudah mulai banyak tempan juga yang ngomongin korupsi, pemerintah yang tak adil, orang miskin yang harus berjuang sendiri dan jangan mengharap-harap bantuan, aku tak peduli semua itu. Toh mau bicara, pertemuan, demo, Lui tetap harus masuk TK sebentar lagi” (hlm. 53).
Di sisi lain, masih dalam “Vayu”, alam pikiran masyarakat kampung digambarkan sebagai sosok yang “nrimo”, pasrah pada keadaan, dan menjalani kehidupan dengan mengalir, serta percaya bahwa rezeki ada yang atur:
“Biarlah. Hidup memang tak perlu dipikirkan. Jalani saja. Kebanyakan orang pintar tak bisa buat apa-apa… Semua punya rezekinya masing-masing” (hlm.53).
Jika sebelumnya beberapa cerita berlatar kota diikuti dengan imajinasi benda-benda yang seolah hidup, cerita dengan latar kampung tak perlu pakai imajinasi macam itu. Misalnya cerpen “Naomi” yang diawali dengan misteriusnya kepergian Naomi dan ibunya di laut yang kemudian dikaitkan dengan dongeng serta mitos masyarakat setempat. Kemudian berlanjut persoalan dua sejoli yang tak dapat menyatu karena beda suku. Selain itu, secara sangat halus membisiki persoalan anak-anak muda pergi merantau dan tak kembali ke kampung halaman. “Naomi” juga sekaligus memberikan pernyataan perbedaan mendasar kota dan kampung karena masyarakatnya masih percaya pada dongeng dan mitos-mitos:
“Jangan kira cerita itu dongeng. Itu benar-benar terjadi” (hlm. 69).
Penutup
Apabila saya diminta memilih, cerpen yang mana yang paling saya sukai, justru belum sama sekali saya sebut di atas. Saya justru paling menyukai “Sekadar Cerita, Sekadar Kenangan”, kenapa? Karena itu cerita tentang kenangan yang terasa manis jika dibaca, namun, barangkali, getir jika dikenang oleh si pengarang.
Seikat Kisah Tentang yang Bohong menampilkan sejumlah problematika masyarakat urban yang teralienasi, persoalan perkotaan yang tak kunjung selesai, juga masyarakat kampung yang miskin dan irasional. Perbedaan antara kampung dan kota dalam cerpen justru pada akhirnya tidak seperti langit dan bumi. Baik masyarakat kota atau masyarakat kampung sama-sama manusia yang memiliki sisi-sisi kemanusiaan yang pada akhirnya ternyata menghadapi problematika kehidupan yang sama: berjuang demi mencari sesuap nasi.
“Kelak kita tak perlu ke kota. Kelak kita membuat kota…”[6]

[1] Pilihan penggunaan diksi kampung dan bukan desa merupakan pilihan pengarang dalam kumpulan cerita ini, saya hanya mengikuti saja supaya ada kesamaan diksi.
[2] Dalam penulisan fiksi, gaya bahasa atau majas semacam ini, yang menggunakan merek-merek, dikenal dengan istilah metonimia.
[3] Gaya bahasa atau majas ini dikenal dengan personifikasi, yaitu benda mati seolah hidup.
[4] Lahir di Berlin, Jerman 19 Juli 1898, Marcuse adalah seorang Fiilsuf Jerman-Yahudi. Salah satu pemikir yang tergolong dalam Frankfurt School dan berpengaruh besar pada gerakan New Left.
[5] Lihat Agus Darmaji, “Herbert Marcuse tentang Masyarakat Satu Dimensi”, dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin, Volume 1, Nomor 6, Juli 2013, hlm. 519-520.
[6] Petikan syair Lagu “Tetanggaku Pergi ke Kota” yang dinyanyikan oleh Tetangga Pak Gesang.
*Tulisan ini dibuat untuk acara Bincang Buku yang diselenggarakan oleh Agenda 18 dan Yayasan Pustaka Obor pada 4 Maret 2017.



