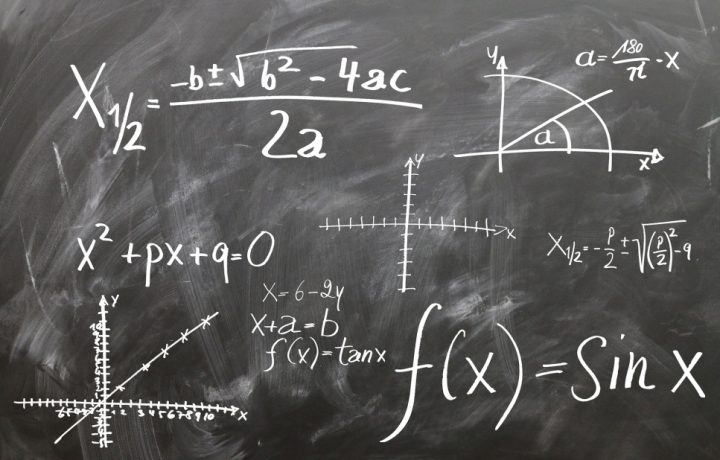I
Beberapa bulan lalu, film Bob Marley: One Love dirilis. Film ini, sebagaimana judulnya yang memang diangkat dari salah satu judul lagu Bob Marley, merupakan sebuah film biopik tentang Robert Nesta Marley. Kita juga bisa menemukan film dokumenter tentang sepenggal kisah dari Bob Marley berjudul Who Shoot The Sheriff di platform Netflix. Judul dokumenter ini juga merupakan plesetan dari sebuah judul lagu Bob Marle, “I Shoot The Sheriff”.
Kehadiran dua film ini pada hemat saya memang menegaskan peran penting Bob Marley; salah satu pewarta kedamaian di dunia. Meskipun, pesan perdamaian itu kini mengalami reduksi makna, lebih tepatnya, mengalami peyorasi makna. Hal ini berkaitan dengan stigmatisasi terhadap marijuana yang juga dekat dengan musik reggae. Kerap hari-hari ini ungkapan “peace aje, Bro” muncul dalam makna yang sedikit reduktif. Tentu saja tidak setiap orang yang mengungkapkan itu hendak memaknainya secara reduksionis seperti itu. Namun yang kerap kita temukan adalah demikian. Kira-kira, salah satu varian dari pemaknaan reduksionis atas ungkapan di atas adalah demikian; ungkapan itu kerap disematkan kepada seorang pencinta reggae, kerapnya seorang dreadlock, yang juga dianggap dekat dengan marijuana. Lantas, “peace aja, Bro”, seolah-olah bermakna; karena yang disapa itu orang yang sudah mabuk marijuana, maka dia akan sante aje karena efek dari hal yang disebut pertama tadi memang membuat orang sedikit lemes.

Tentu saja, hal demikian itu sedikit banyak ada benarnya juga. Marijuana merupakan salah satu hal penting dari Rastafari yang sangat lekat dengan musik reggae, meskipun tentu tidak semua musisi reggae atau pencinta musik reggae adalah penganut rastafari. Marijuana bisa kita anggap sebagai ‘alat bantu’ untuk lebih cepat mencapai trance. Dan trance, adalah salah satu metode mendekatkan diri pada sesuatu yang dipercayai berada di luar manusia. Semua kepercayaan dan agama, dengan metode yang beragam dan durasi yang juga realtif, punya salah satu segi dari trance ini. Maka, dalam konteks itu, sebetulnya bisalah kita mengkatagorikan hak menggunakan marijuana sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi[1].
II
Barangkali saya yang terlalu melankolis atau berlebihan memaknai. Kehadiran film biopik yang sudah disebutkan tadi terasa begitu tepat waktu lantaran ia hadir ketika dunia pun pula Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ekstrim kanan muncul di panggung sejarah hampir di seluruh penjuru dunia diikuti oleh sumbu-sumbu ledak perang di beberapa bagian dunia; Ukraina, Palestina, dan konflik yang makin mengemuka di Laut Cina Selatan. Rasisme menyeruak ke permukaan, bak hama mematikan di ladang tadah hujan yang muncul di musim kemarau. Masih kental di ingatan, beberapa minggu lalu, netijen yang terhormat dari negara +62 ini berbondong-bondong berkomentar di akun resmi Federasi Sepak Bola Guinea pasca kekalahan Tim Nasional U-23.
Rasisme jelas landasan utama munculnya perlawanan dalam genre musik reggae. Bahkan, bisa musik reggae bisa dikatagorikan sebagai musik yang muncul dari jalan ketidak-adilan, musik via negativa. Akar dari musik reggae adalah perbudakan. Karena adanya jual beli budak di masa lampau dari Afrika oleh kolonial Eropa untuk menjadi pekerja di tanah-tanah koloni mereka yang barulah maka muncul musik reggae. Di dalam konteks ini, reggae tidak sendirian. Ada juga musik jazz sebagai salah satu contohnya dan banyak lagi jenis musik lain yang mayoritas adalah musik rakyat. Sayangnya, sebagaimana produk-produk perlawanan yang muncul dari rahim kapitalisme, ia akan dimakan pula oleh kapitalisme itu sendiri.

Orang-orang Afrika yang dibawa ke Kepulauan Karibia, termasuk Jamaika, berabad-abad yang lalu membawa pula musik tradisi Afrika ini sendiri. Dalam perkembangannya dan persentuhannya dengan musik modern Eropa memunculkan, salah satunya, genre musik ini.[2] Maka jelaslah, ada perpaduan antara memorie volontaire dan memorie involontaire di dalam musik reggae menyangkut itu. Saya kira, tanpa sadar dan sadar, perlawanan terhadap rasisme dan perbudakan itu muncul di dalam nada dan lirik musik reggae, tidak hanya Bob Marley.
Ketika orang mendengar dan menikmati musik Bob Marley dan musik reggae secara umum di hari-hari ini, memori-memori yang berasal jauh dari masa lalu mengenai perbudakan, ketidaksetaraan, dan perlawanan atas rasisme, semoga perlahan-lahan hinggap di kepala dan batin mereka. Semacam sebuah, meminjam Walter Benjamin, kilatan cahaya di malam gelap dari masa lalu yang menuntut pelihatnya, para pendengar musik itu, untuk menangkapnya dan dijadikan bara api perjuangan hari ini.
III
Who Shoot The Sheriff dan Bob Marley: One Love bermula pada keinginan Bob Marley untuk menyelenggarakan konser perdamaian dan memuncak pula pada konser perdamaian tersebut. Sebagaimana banyak kita ketahui, Jamaika baru merdeka dari Inggris pada 1962. Konflik, perang saudara, dan juga ketidakstabilan lantaran banyak gangster mewarnai Jamaika di era Bob Marley hidup. Dua film yang disebutkan di atas tadi menggambarkan hal itu dengan baik. Kaum Rastafari termasuk kaum yang didiskriminasikan ketika itu. Kedua film di atas menggambarkan bagaimana hidup di Kingston Town, ibukota Jamaika, di era-era itu tidak lepas dari ketakutan demi ketakutan; hidup bagaikan telur di ujung tanduk. Tubuh tak bernyawa di pinggir jalan adalah hal lumrah bagi fajar Kongstown Town. Para gangster saling bertikai dan di baliknya partai politik menjadi pendukung dari para gangster ini.
Orang seperti Bob Marley adalah anak kampung yang datang ke Kingstown Town untuk mengadu nasib, mencari hidup yang lebih baik, karena di ibu kota negara dunia ketigalah gemerlap itu ada, mengundang laron-laron terbang menghampiri, seperti juga kondisi di Indonesia. Untung mereka punya musik yang sedikit banyak menjadi hiburan di tengah keadaan yang demikian. Bagi banyak anak muda berbakat kala itu di Kingstown Town bermusik adalah salah satu jalan untuk mencapai hidup yang lebih baik itu. Bob Marley, Jimmy Cliff dan beberapa lainnya tentu berhasil di sana tetapi banyak juga yang tak berhasil; ada yang lantas menjadi penjual ganja di dalam jejaring gangster, ada yang berada di waktu-tempat yang salah menjadi korban dari pertikaian para gangster.

Setelah dikenalkan Rita Marley dengan Rastafari, Bob Marley mulai memasukan unsur-unsur Rastafari di dalam lagu-lagu gubahanya. Di sini kondisi sosial yang memang sudah membentuk ciri musik Bob Marley sebagai suara kaum terpinggirkan, saksi kondisi sosial yang tak adil, dan jerit perlawanan dari kaum yang kalah mendapat unsur penyelamatan; Messiah. Orang seperti Bob Marley tidak perlu membaca dan belajar tentang segala macam teori sosial perihal ketimpangan; ketimpangan itu adalah bagian dari hidupnya. Itulah sebabnya, ketika ia perlahan-lahan mulai terkenal dan musiknya banyak digandrungi, Bob Marley merasa ia perlu melakukan sesuatu untuk masyarakatnya, rakyat Jamaika. Ia menaruh harapan besar pada musiknya dan musik pada umumnya sebagai obat di tengah kondisi demikian. Lebih jauh, ia mengupayakan musik menjadi alat penyelamatan dan alat pengubah keadaan.
Itulah sebabnya, ia merencanakan konser perdamaian dengan harapan untuk menghentikan konflik sosial politik di Jamaika. Tentu, ini mengganggu ‘kestabilan politik’ dari perspektif para politisi Jamaika kala itu beserta perangkatnya. Bob Marley and The Wailers. Mereka mendapatkan teror, penembakan, di rumah Bob Marley. Tak ada yang terbunuh. Namun, teror itu tak menyurutkan langkah Bob. Konser tetap dijalankan meskipun hasilnya jauh dari harapan. Kecewa, mereka pindah ke London. Dari sana, pesan perdamaian Bob Marley menjalar ke seluruh penjuru dunia yang kala itu pun tidak baik-baik saja.
Bob Marley and The Wailers lantas pulang ke Jamaika untuk kembali melakukan konser perdamaian. Ia bahkan berhasil membuat dua pemimpin politik besar dan berseberangan serta bermusuhan di Jamaika kala itu berada di satu panggung yang sama; sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Namun, seniman dan politisi puya maksud berbeda; seniman bermaksud mewujudkan tujuan Politik (dengan P besar) yakni kebahagiaan untuk hidup manusia dan politisi punya maksud mewujudkan tujuan politik (dengan p kecil) yakni kebahagiaan untuk diri dan golongannya. Dua politisi tadi di atas panggung bersama Bob Marley bertingkah seolah-olah konflik sudah selesai dan kedamaian akan ada di dalam suasana politik Jamaika. Seperti yang sudah ditebak, hal itu tidak terjadi. Kedua politisi itu, tentu saja, hadir di sana untuk mengambil simpati massa dengan mendompleng pada ketenaran dan polulartias Bob Marley.
Pada titik ini, kita kerap terjebak membaca sikap dan apa yang dilakukan seniman, dalam hal ini Bob Marley, sebagai sesuatu yang naif. Niat “baik” mereka dimanfaatkan oleh politisi untuk kepentingan-kepentingan politik (dengan p kecil) mereka. Pertanyaannya, apakah benar seorang seniman itu naif? Bob Marley tentu tidak begitu saja percaya bahwa para politisi di Jamaika sudah berubah ketika ia mengiakan ajakan untuk pulang dan mengadakan konser perdamaian di Kongston Town. Pengalaman pada upayanya membuat konser perdamaian yang pertama tentu memberikannya banyak pelajaran, hidup di London dan melihat banyak tempat di Eropa dan Amerika tentu memberikan banyak masukan berharga untuknya.
Sebelum pulang ke Jamaika, Bob Marley sudah mengetahui penyakit kanker yang dideritanya. Rupanya, kepercayaan Rastafari untuk tidak ‘memangkas’ apapun yang ada di tubuh manusia membuat tidak ada tindakan medis tertentu yang dilakukan terhadap penyakit tersebut. Dengan pemahaman akan kondisi diri seperti itu, Robert Nesta Marley memutuskan pulang ke Jamaika sebagai Bob Marley and The Wailers yang baru; simbol perdamaian untuk, tidak hanya Jamaika, tetapi dunia. Maka, barangkali ia ingin pulang dan memberikan kesan terakhir untuk masyarakat Jamaika yang dicintainya, masyarakat dengan pengalaman ketertindasan dan penderitaan yang darinyalah dirinya berasal dan terus berada. Konser yang ia adakan di Kongston Town dengan demikian adalah pesannya yang terakhir untuk masyarakat Jamaika bahwa di dalam musik reggae ada pesan dari upaya dan perjuangan menuju kesetaraan, perdamaian yang mana pesan-pesan itu bukan diciptakan semata olehnya, melainkan jejaknya jauh tercipta sejak masa lalu, sejak kaum kolonial menginjakan kaki di Afrika, bahkan lebih jauh dari itu. Semua itu jelas di dalam lagu-lagunya, salah satua “Buffalo Soldier”.
IV
Saya kira pesan dari Bob Marley itu terus bergema hingga hari ini, pun pula sampai ke tanah air. Lagu-lagu reggae tanah air banyak pula yang mewarisi semangat dan pesan yang sama dari apa yang diutarakan Bob Marley. Tentu saja tidak seluruhnya. Namun jika kita mencerna lirik-lirik dari musisi reggae Indonesia, berceceran di sana jejak-jejak tradisi perlawanan dan perjuangan untuk perdamaian, kesetaraan, dan keadilan. Ia juga mendapatkan konteks tanah air di mana banyak pula di sana rekaman dan potret kondisi sosial politik di tanah air yang timpang dan tak adil.
Akhirul kalam, bolehlah konser perdamaian kedua yang diadakan Bob Marley di Kongston Town tidaklah membuahkan hasil yang maksimal kala itu. Namun pesan yang ia wartakan kala itu terus bergema, bahkan gaungnya sampai pada kita, bertemu dengan konteks yang spesifik dari sejarah dan kondisi sosial politik tanah air. Perjuangan di jalan kebudayaan dengan demikian adalah perjuangan demi tujuan Politik dengan P besar yang buah hasilnya akan tampak dan terlihat jauh di kemudian hari, pada mereka-mereka yang mewarisinya.
[1] Kita tahu belaka bahwa hak menjalankan agama dan kepercayaan merupakan salah satu Hak yang Tidak Dapat Dikurangi. Jika, di dalam konteks Rastafaria, marijuana digunakan sebagai salah satu ritualnya, maka jelaslah, itu merupakan bagian dari hak yang disebutkan tadi.
[2] Di tanah air, kita punya musik sejenis ini di dalam diri dangdut misalnya. Saya pernah menulis itu dalam, “Dangdut – Reggae: Musik Kompromi dan Suara Minoritas”.
*Catatan: Tulisan ini dibuat sebagai bahan diskusi pada Senandung Warga Edisi Cengcet, Gimana Bang Bob Merebut Hak Kebebasan, yang diadakan oleh Lokataru Foundation, Sabtu, 25 Mei 2024.