I.
Modernisasi, sebagaimana perubahan-perubahan lainnya di muka bumi ini, menghilangkan hal-hal tertentu dan membawa ke depan hal-hal yang lainnya. Kita tahu cuaca pemikiran modern muncul ditandai dengan Rene Descartes memproklamirkan cogito ergo sum (aku berpikir maka aku ada). Saat itulah perlahan-lahan dunia pemikiran, dengan imbas sedikit banyak pada pengaturan hidup sehari-hari dan atau dunia pemikiran sebagai refleksi dari dunia kehidupan sehari-hari, bergerak perlahan-lahan meninggalkan ‘Deosentris’ menuju ‘antroposentris’. Manusia tidak lagi berpikir bahwa ia seumpama wayang yang digerakan oleh Sang Dalang yang maha kuasa, melainkan ia adalah penggerak bagi dirinya sendiri. Manusia pelan-pelan meninggalkan dunia yang kental dengan religiusitas dan lebih masuk kepada hal-hal yang profan. Di masa-masa itu pulalah muncul sekularisme yang berusaha memisahkan dengan tegas dunia keseharian dengan religiusitas.
Belakangan, kita perlahan melihat bahwa apa yang dicanangkan modernisme tidaklah berbuah sebagaimana yang diharapkan. Dunia yang antroposentris bukanlah surga yang didamba-dambakan. Perang Dunia I dan Perang Dunia II sedikit banyak meluluh-lantakan janji-janji manis modernisasi. Kerusakan lingkungan yang semakin parah akhir-akhir ini adalah dampak langsung dari pandangan bahwa manusialah pusat alam semesta; sebuah sumbangsih juga dari modernisme yang antroposentris. Usaha memisahkan secara tegas, bahkan menghilangkan sama sekali, peran yang religius dalam kehidupan manusia pun mulai dipertanyakan. Modernisasi tidak menghilangkan sama sekali dan membuang jauh-jauh yang religius. Sebaliknya, panorama dunia belakangan ini menunjukan kerinduan dan tetap ada serta dibutuhkannya yang religius oleh manusia itu. Selain di satu sisi muncul fundamentalisme agama, atau dengan kata lain kembalinya manusia pada agama-agama ‘tradisional’, di sisi lain manusiapun berusaha mencari bentuk-bentuk religiusitas yang baru. Modernisasi dengan demikian tak berhasil memberikan cukup alasan dan amunisi untuk manusia bisa percaya pada dirinya sendiri sehingga tak membutuhkan hal-hal lain di luar dirinya.
Sekularisme lantas diperiksa ulang. Dari penelitian Charles Taylor—misalnya di dalam buku Modern Social Imaginaries (2004)—tampaklah bahwa sekularisme tidak serta-merta menghilangkan yang religius dari imajinasi masyarakat. Masyarakat, demikian Taylor, justru menerima bahwa di dalam kehidupan publik bolehlah tak ada campur tangan yang religius. Namun di dalam pribadi masing-masing, bahkan di dalam kehidupan komunitas, religiusitas tetap memiliki tempat. Masyarakat bahkan terkadang menjalankan apa yang ada di dalam ruang publik—yang berarti tanpa campur tangan religiusitas—dengan niatan dan motifasi yang sangat religius. Inilah panorama kehidupan modern kita belakangan ini. Hal yang sama tampak pada humanisme terkhusus dalam karya Jens Zimmermann. Tulisan ini akan pertama memaparkan posisi Zimmermann. Selanjutnya, kedua, akan memberikan sedikit catatan singkat atas posisi Zimmermann tersebut.
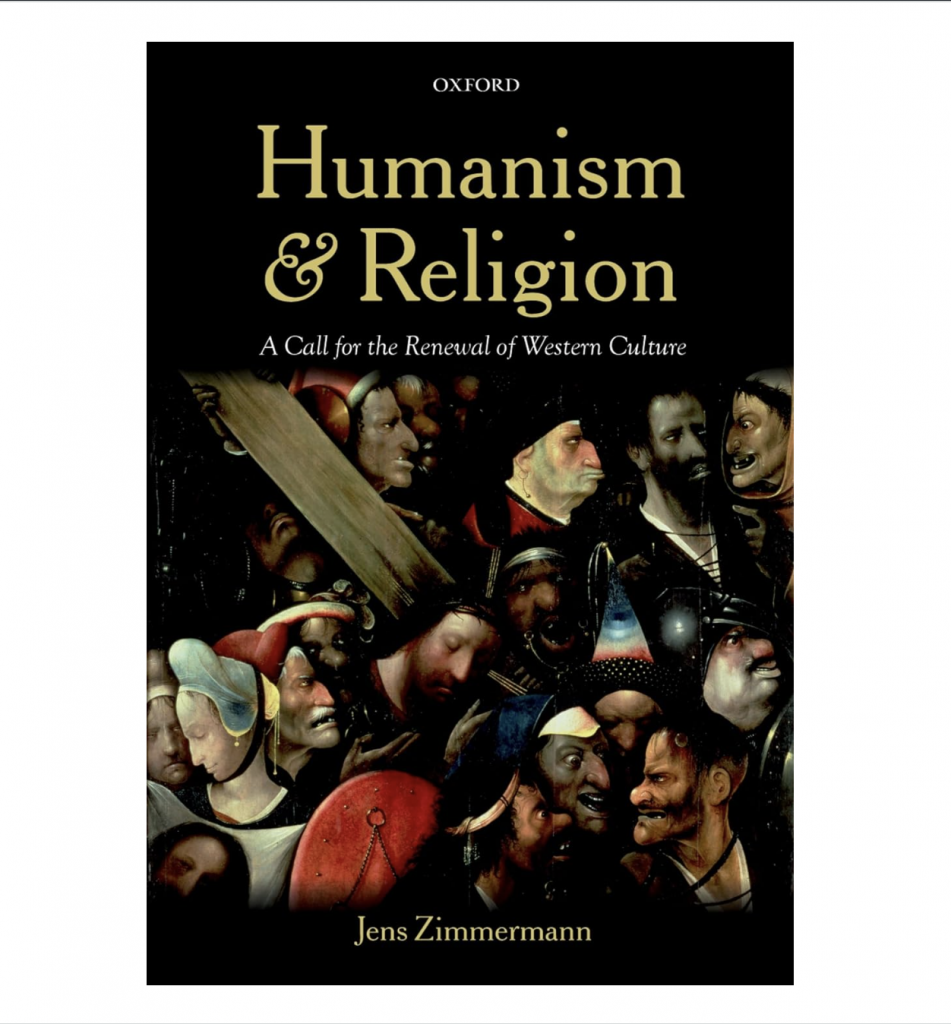
II
Humanisme barangkali menjadi sangat kuat dan tersebar begitu rupa setelah Perang Dunia II. Walau pun tentu saja akar-akarnya sudah ada jauh sebelum itu. Di awal modernisme dalam pemikiran, humanisme digerakan oleh studi-studi terhadap peninggalan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno[1]:
….in the early Renaissance, the disciplines of grammar, rhetoric, poetry, history, and philosophy were called studia humanitatis, that is, the humanities. A teacher of one of these disciplines was called a “humanist.” At that time the study of these disciplines was stimulated by the newly discovered literature of classical Greece and Rome. These teachers found a human ideal involving features such as a unity between humans and nature, a confidence in the power of human understanding, the ability to enjoy the pleasures of life.
Namun demikian, keluasan dari humanisme ini sendiri membuatnya tidak bisa didefinisikan secara ketat dalam satu atau dua kalimat. Keluasan humanisme ini lantaran sejarahnya yang memang bisa ditarik sejak pemikiran kaum Stoik hingga zaman kontemporer ini. Jens Zimmermann mencatat ada tiga hal yang membuat pendefinisian dari humanisme terasa sulit atau katakanlah menyederhanakan masalah, “… a) humanism cannot be reduced to one single discipline (is it literary, philosophical, theological?), b) humanism has become a synonym for atheism, and c) humanism is often equated with and hence dismissed as Platonism by anti-humanist philosophers and theologians”[2].
Zimmermann dalam karyanya Humanism and Religion: A Call for the Renewal of Western Culture berusaha melihat humanisme dalam kaitannya dengan religiusitas. Berbeda jauh dengan banyak pemikir yang melihat humanisme sebagai lawan dari religiusitas atau teologi, Zimmermann berpendapat bahwa justru religiusitas adalah sumber dari humanisme.[3] Hal ini menurut Zimmermann adalah sesuatu yang pasti terjadi lantaran kebudayaan barat sendiri adalah sebuah kebudayaan yang berlandaskan atau dibangun oleh religiositas.
Lebih jauh dari itu humanisme yang hendak dicari tahu dalam kara Zimmermann di atas adalah seperangkat nilai-nilai implisit tentang eksistensi manusia dan goal dari pengetahuan manusia yang meregulasi kebudayaan barat. Dengan begitu humanisme sebenarnya sesuatu yang cukup luas cakupannya. Mengikuti pandangan dari Albert Schweitzer, Zimmermann menekankan bahwa untuk menjadi benar-benar manusia, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan seperangkat teori semata. Ia perlu mengandalkan juga keyakinan yang dalam akan lingkaran spiritual yang berelasi dengan dunia.[4] Zimmermann menegaskan[5]:
True humanism, in other words, requires religion. For Schweitzer, a truly human ethos capable of transforming barbarism into humane culture demands transcendence none in some abstract sense, but in the sense of the personal participation one find in many world religions.
Untuk menjadi manusia yang benar-benar manusia atau dengan kata lain manusia yang humanis maka diperlukan juga kedalaman dari religiusitasnya atau setidak-tidaknya inspirasi dari religiusitas. Apa yang dikatakan Zimmermann seturut Schweitzer di atas menunjukkan bahwa peradaban, proses manusia menjadi semakin manusia, bukanlah sebuah perihal yang abstrak semata tetapi ia membutuhkan partisipasi personal. Artinya, jika boleh dibahasakan secara lain, peradaban bukan hanya ditentukan oleh ide-ide tetapi juga praktik-praktik yang nyata. Partisipasi nyata ini oleh Zimmermann dapat ditemukan dalam religiusitas. Partisipasi personal membutuhkan semacam iman yang menggerakannya untuk berpartisipasi.
Dengan demikian menjadi jelaslah bagi kita bahwa menurut Zimmermann humanisme itu berakar juga dari religiusitas. Hal ini lantaran humanisme tumbuh dari jantung peradaban Eropa sendiri yang mana peradaban Eropa tersebut pun dibentuk dari religiusitas tertentu pula. Dalam hal ini tentu saja yang paling jelas adalah religiusitas Kristen. Selain dari hal itu, dari sisi manusia secara personal, religiusitas berperan memberikan api semangat untuk berpartisipasi dalam pemberadaban manusia. Dengan kata lain, religiusitas menjadi semacam motor penggerak peradaban, dengan demikian motor penggerak manusia menjadi semakin manusia, motor penggerak humanisme itu sendiri.
III
Kebudayaan barat atau Eropa kita tahu dibangun oleh tiga kebudayaan besar yakni Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan juga Kristianisme dari Yahudi. Pemikiran Barat yang banyak bersifat teleologis misalnya bisa dilacak akarnya dari teologi dan kebudayaan Yahudi dan Kristianisme. Dalam sejarahnya, kebudayaan Yunani Kuno mempengaruhi Romawi Kuno. Lantas berkat campuran dengan Kristianisme, lahirlah Skolastikisme. Barulah setelah itu muncul modernisme dengan abad Pencerahannya. Humanisme mulai tumbuh berkembang, begitu juga dengan sekularisme, di periode modernisme pencerahan ini.
Tentu saja perjalanan sejarah yang demikian tidak bisa menafikan peran religiusitas. Para pemikir barat adalah para pemikir yang terkungkung pula di dalam kebudayaan yang demikian. Pierre Bourdieu mengingatkan dalam konsepnya tentang sosiologi yang reflektif di mana seorang pemerhati atau pemikir tentang masyarakat tidak bisa lepas dari bias kebudayaan tempat ia berada. Saya kira para pemikir barat yang memformulasikan humanisme juga bisa saja berada dalam keadaan yang demikian.
Permasalahannya, sebagaimana yang digambarkan dalam ihwal sekularisme, perubahan yang terjadi pada era modern hanyalah pada pengaturan dan administrasi publik dan bukan pada pribadi orang perorangan. Jadi, religiusitas tetap ada di dalam diri manusia yang mana terus berkembang dalam kemasyarakatannya. Praktek hidup masyarakat tidak bisa secara serta merta dibersihkan dari hal-hal religiusitas.
Membicarakan ihwal humanisme tentu saja kita membicarakan perihal manusia. Di sini, secara vulgar, kita bisa menempatkan humanisme pada katagori ilmu sosial. Perbedaannya dengan ilmu alam murni, ilmu sosial berurusan dengan manusia yang mana pikiran, mental, dan sebagainya ditentukan pula oleh kebudayaannya. Banyak pengalaman dan peristiwa di dalam sejarah menunjukkan bahwa sebuah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tidak serta merta mengubah masyarakat itu menjadi sama sekali baru. Selalu saja ada hal-hal dari tatanan lama yang terbawa di dalam tatanan baru. Hal ini terjadi juga di dalam perubahan masyarakat dari sebelum modern ke modern hingga saat ini. Sesuatu yang berasal dari tatanan lama terus dibawa hingga saat ini. Tentu banyak faktor penyebab hal itu terjadi tetapi bukan di sini tempat untuk membuat daftarnya.

Apa yang hendak ditegaskan adalah bahwa humanisme berakar dari religiusitas pada hemat saya adalah sesuatu yang wajar. Wajar karena perkembangan masyarakat dan peradaban selalu begitu dan memang begitu; bahwa ia dibangun di atas tatanan lama, demi tatanan lama hingga mencapai keadaannya yang sekarang. Tak bisa kita pungkiri peran dan keberadaan religiusitas dalam perkembangan peradaban manusia. Tentu saja perlu ditegaskan di sini juga bahwa posisi yang demikian ini adalah posisi yang melihat religiusitas sebagai sebuah fenomena kemasyarakatan, bukan fenomena iman.
Pada titik ini saya teringat pada tahap perkembangan masyarakat yang dibuat August Comte. Menurutnya ada tiga tahap perkembangan masyarakat yakni tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Comte barangkali memisahkan secara tegas ketiga tahap ini. Namun melihat perkembangan masyarakat tidaklah bisa tegas terpisah satu tahap ke tahap yang lainnya. Tak ada revolusi seratus persen dalam ilmu-ilmu sosial.
Di dalam humanisme ada religiusitas dan bahkan religiusitas itu adalah sumber humanisme saya kira bisa dilihat dalam kerangka tersebut bahwa perkembangan masyarakat selalu saja membawa hal-hal dari tahap sebelumnya di dalam tahap kehidupan yang baru. Dengan demikian bukanlah sesuatu yang mencengangkan bila hal itu tampak. Yang terpenting sekarang apakah humanisme masih tetap mungkin menjadikan manusia benar-benar manusia di tengah zaman ini; di tengah kesenjangan ekonomi yang besar, di tengah rekayasa-rekayasa para penguasa yang terus-terus saja menjajah kaum tertindas. Apakah humanisme dengan induknya religiusitas itu mampu membuat seorang pemilik pabrik memberi upah yang layak sehingga para pekerjanya bisa hidup setidaknya seperempat persen setara dengan dirinya? Dengan lain perkataan, apakah humanisme mampu menciptakan surga di dunia dan tidak hanya, mengikuti sumbernya religiusitas, menciptakan surga di Surga?
[1] Nicholas Bunnin dan Jiyuan Yu, The Blackwell Dictinoary of Western Philosophy, (Oxford: Blackwell Publishing), 2004, hlm. 312-313.
[2] Jens Zimmermann, Humanism and Religion: A Call for the Renewal of Western Culture, (Oxford: Oxford University Press), 2012, hlm. 36.
[3] “Humanism, after all, has religious roots, and these roots are worth recovering for the sake of a cultural ethos that no longer has to oppose religion to humanistic aspirations of human dignity, freedom, and rational inquiry. Religion is not the enemy of humanism, but its very source”. Jens Zimmermann, Humanism and Religion: A Call for the Renewal of Western Culture…. hlm. 3.
[4] Jens Zimmermann, Humanism and Religion: A Call for the Renewal of Western Culture…. hlm. 5.
[5] Jens Zimmermann, Humanism and Religion: A Call for the Renewal of Western Culture…. hlm. 6.
*Catatan: Tulisan ini dibuat untuk Mata Kuliah “Humanisme dan Agama” di Program Magister Filsafat, STF Driyarkara, 15 Januari 2015.




