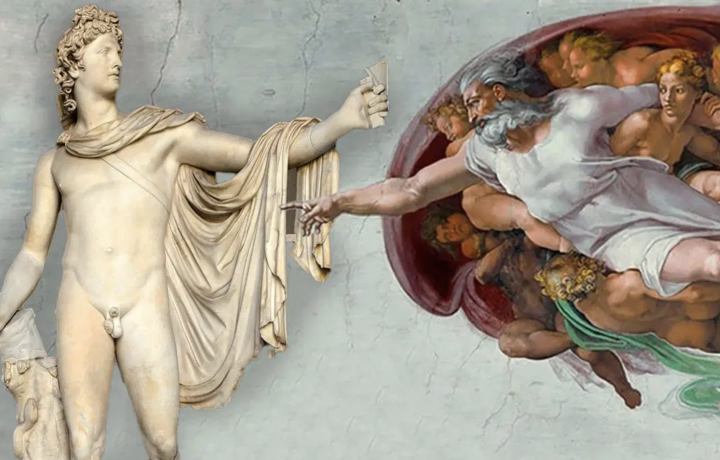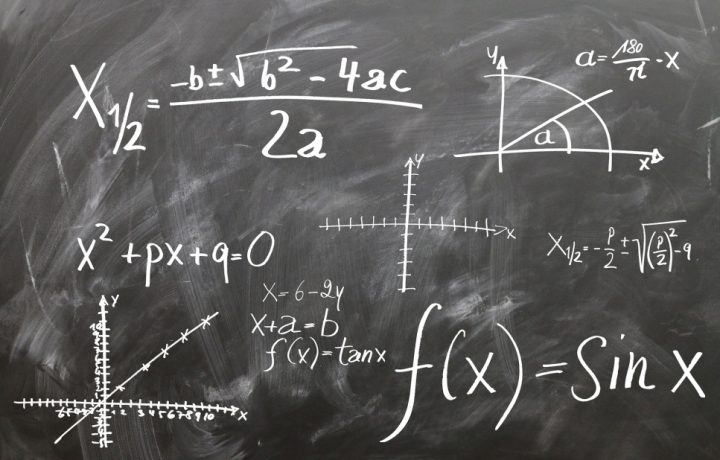Sangat sering, ketika Anda kehabisan ide menulis, menimba inspirasi dari tulisan orang lain bisa sangat membantu. Itulah yang kini terpaksa saya lakukan. Selain itu, tentu saja, saya harus angkat topi—ini memang secara harafiah karena sekarang saya kerap memakai topi—pada orang yang memberikan jalan ke luar atas mentok-nya ide untuk menulis itu.
Betapa tidak! Selama bertahun-tahun, setiap minggu, ia menelorkan sebuah esai singkat. Dibukukan dalam beberapa seri pulak! Yah, tentu saja penghormatan ini tidak mengurangi kenyataan yang dibuktikan kawan kami yang pernah melabelinya dengan ungkapan ‘sekadar desas desus.’ Dengan kata lain kita tahu formulanya menulis. Menulis sekadar desas-desus tentu sering kita lakukan. Dalam kasus saya, itu kerap saya lakukan untuk paper sebuah mata kuliah yang tak terlalu menarik. Namun demi sebuah nilai, Anda harus membuat sebuah tulisan. Kutip sana kutip sini tanpa benar-benar paham apa yang dikutip, dijahit, dan jadilah sebuah tulisan utuh. Dalam kasus saya, kerap tulisan yang demikian dapat nilai, syukur-syukur C+, seringnya C saja.
Saya lupa, rutinitasnya pada tanggal berapa, tulisan yang muncul dengan judul Racun itu. Belakangan, Wisnu Suryapratama membuat tanggapan atas tulisan tersebut. Yang terakhir ini sungguh telak sebagai penangkal Racun.
Membaca paragraf demi paragraf tulisan Racun itu, kita seolah-olah bertemu dengan seorang skyzofren yang masih berada dalam bayang-bayang gelap totalitarianisme. Dengan mengutip seorang profesor yang hidup dalam tekanan Nazi Jerman, makin kentaralah kesan itu. Apalagi ketika pertemuan itu diangkatnya sebagai obat penangkal racun tersebut. Pertemuan yang membuat saya teringat pada Emmanuel Levinas, filsuf yang lebih terkesan sebagai teolog Yahudi, dan karena itu kerap dianggap seorang Rabai. Bahkan, rumornya, Paus Yohanes Paulus II pernah pada suatu ketika menyapanya sebagai Rabai. Barangkali ia memang mengambil ide Levinas, barangkali juga tidak.

Levinas tentu saja seorang Yahudi. Ia lahir di Lithuania yang lantas belajar di Prancis dan sempat mengikuti beberapa kali kuliah Edmund Husserl, juga seorang Yahudi. Selepas Perang Dunia II, Levinas muncul dengan pemikiran bahwa etika lebih penting dari metafisika. Dan dalam pertemuan dengan wajah yang lainlah etika itu dimungkinkan. Penghargaan atas yang lain, yang alpa dalam filsafat Eropa pasca aufklaerung inilah yang, menurutnya, memunculkan kebobrokan dunia modern yang memuncak dalam genosida Hitler.
***
Pada 9 November 1918, Kekaisaran Jerman Kedua berada pada kehancurannya. Pangeran Max menyerahkan tampuk pemerintahan pada Kanselir Friedrich Ebert, Ketua SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Partai Sosial Demokrat Jerman). Pemimpin SPD, Philipp Scheidemann, lantas memproklamasikan Republik Jerman. Di saat yang bersamaan, Karl Liebknecht, pemimpin Spartakus Bund, memproklamasikan Republik Sosialis. Pada 11 November 1918, Ebert dan koleganya bersama USPD (Partai Sosial Demokratik Independen) mendirikan pemerintahan yang baru. Dari sini, konflik pun menyeruak di antara keduanya; kubu Sosial Demokrat dan Komunis di Jerman. Dari akhir Desember 1918 hingga pertengahan tahun 1919, konflik-konflik kecil banyak terjadi, beberapa di antaranya berdarah. Pihak militer lantas berinisiatif untuk membentuk suatu unit yang dapat beraksi cepat dan tanggap. Selain itu, dibentuk juga kelompok-kelompok paramiliter dengan izin melakukan kekerasan yang ekstrem.
Kelompok Pekerja Radikal Berlin dan Partai Komunis Jerman melancarkan pemberontakan bersenjata pada Januari 1919. Namun, kelompok paramiliter sayap kanan dan tentara, dengan persetujuan pemerintah, membantu pemerintah menumpasnya. Dua pemimpin utama Spartakus Bund, Karl Liebknecht dan Rosa Luxemburg dibunuh dalam penumpasan pemberontakan ini.
Di sisi lain, ketika SPD berkuasa dan mengumumkan gencatan senjata dalam Perang Dunia I, beribu tentara Jerman masih ada di segala penjuru medan perang. Mereka semua ditarik pulang dan kemenangan di depan mata hilang tiba-tiba dari genggaman mereka. Wietz mengungkapkan, bagi para perwira angkatan bersenjata Jerman saat itu, muncullah anggapan kemenangan yang ada di depan mata yang hilang itu diakibatkan oleh musuh dalam selimut; kaum sosialis, orang-orang Yahudi. Salah satu tentara berpangkat kopral yang harus kembali dari perang kala itu adalah Adolf Hitler.

Fase awal Republik Weimar diwarnai oleh koalisi SPD, DDP (Partai Demokrasi Jerman), dan Partai Katolik Jerman. Republik Weimar menjadi negara demokratis yang ideal. Pendidikan, kesamaan gender, tunjangan sosial, perindustrian berjalan dengan baik di negeri itu. Bahkan pada 1928, industri dan perkebunan Weimar berhasil mencapai level tertinggi. Pada 1929, semuanya mulai berubah dimulai dengan jatuhnya pasar di Amerika pada Oktober. Dampaknya di Jerman tidak perlu menunggu lama karena ekonomi Jerman bergantung juga pada modal di Amerika. Namun, akibat beban membayar kerugian perang yang adalah salah satu dari isi perjanjian gencatan senjata pada 1918, ditambah resesi ekonomi dunia, Republik Weimar mulai mengalami kemunduran. Kala itulah Nazi, yang membawa nostalgia kemenangan di depan mata pada Perang Dunia I, dengan mengambing-hitamkan Sosialis dan Yahudi, diterima penuh gegap-gempita. Hitler muncul sebagai Sang Pembebas. Dielu-elukan di mana-mana.
***
Demikianlah. Mengangkat Nazi di Jerman dan sering pula Stalin di Uni Soviet sebagai contoh dari totalitarinaisme yang bengis, memang hobinya para penggemar humanis universal dan juga pemeluk teguh demokrasi. Namun yang sering dilupakan, sejauh yang saya baca dalam konteks Hitler dan Nazi, adalah akar apa yang menyebabkan keduanya begitu populer di Jerman kala itu. Permasalahan ekonomi politik, tentang resesi dan krisis yang dialami Jerman akibat jatuhnya pasar dunia di Amerika, hilang dalam cerita tentang Hitler yang pendek dan barangkali juga cadel, serta Goebles yang mampu memanipulasi kesadaran. Lalu, seperti Levinas, misalnya, mengajukan permasalahan etika sebagai obat dari kebengisan itu.
Bayangkan sepotong roti yang masih laik makan tergeletak di depan mata. Anda tengah dihajar kelaparan sangat. Apakah Anda akan mencari tahu dulu sang empunya roti, meski pun ia, barangkali, berjarak 3 km jauhnya dan baru kemudian memakannya? ‘Orang baik’ pastinya akan melakukan itu. Tetapi saya, ketimbang mati lapar, akan segera memakannya. Tak peduli apakah roti itu beracun atau tidak.***
*Catatan: Dipublikasikan pertama kali di Rubrik Oase IndoProgress, 24 Februari 2014.
**Tulisan ini sebetulnya berhutang pada dua esai lain yang saya sertakan pranalanya di dalam tulisan ini. Sayang, sepertinya dua pranala tersebut sudah tidak aktif lagi. Saya sendiri tidak menyimpan arsip kedua esai tersebut.