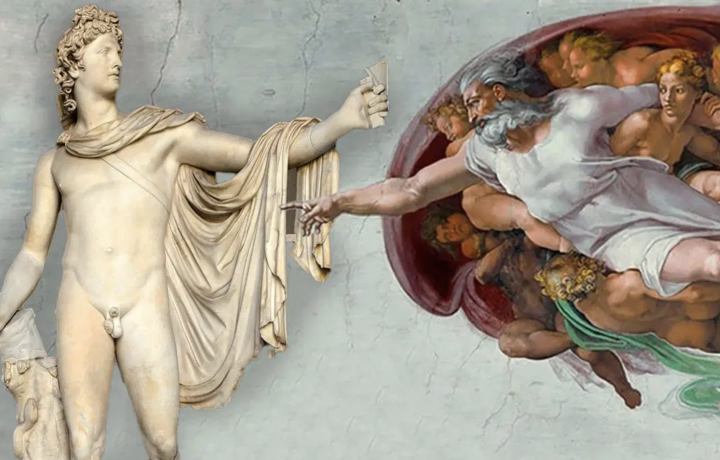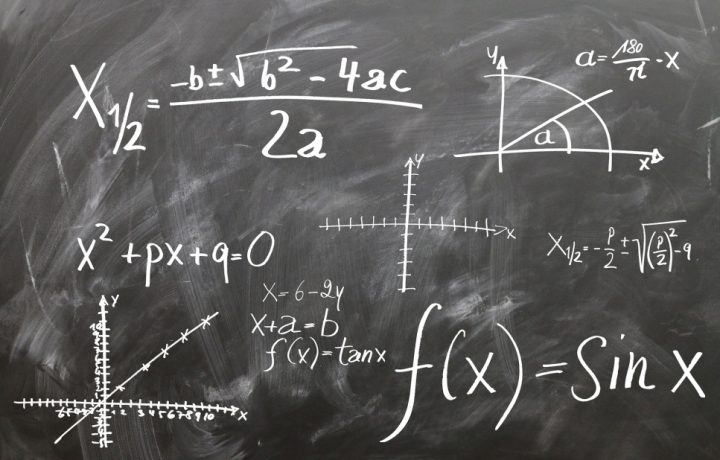TERUS terang, saya agak heran dan berusaha menebak-nebak makna frasa ini, ‘Lapak Gratis,’ pada pesan singkat seorang kawan. Kata kawan itu, ada ‘lapak gratis.’ Penasaran, saya pun mendatangi ‘Lapak Gratis’ yang dihela di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, 25 Juli lalu. Di sana, berkumpul beberapa komunitas di Jogja dengan beberapa kegiatan. Zine-zine dijejerkan untuk dibaca di tempat, baju-baju layak pakai bekas, dan beragam hal lainnya. Inti dari ‘Lapak Gratis,’ sepenangkapan saya yang sekadar lewat, adalah ‘berbagi barang layak tidak terpakai yang menyesakan kamar atau gudang, begitu saja. Sederhana sekali bukan? Namun ia sekaligus mengajak kita menjadi kritis dan memikirkan ulang banyak hal.’
Sebenarnya, dalam kuantitas, tidak banyak orang yang aktif berada di sana. Mungkin tak lebih dari 150-an orang. Acara ini pun barangkali tanpa izin resmi. Alhasil, Satpol PP datang dan membubarkannya. Seperti biasa, sedikit terjadi percecokan. Sayang, tanpa adu jotos. Tiba-tiba, ada nama tuhan diteriakkan, lalu bincang-bincang keras, lalu sedikit semrawut, lalu tenang lagi. Satpol PP pergi dan, mungkin panitia melakukan evaluasi. Beberapa remaja Eropa terlihat berbincang-bincang tentang sebuah pengalaman yang seru untuk mereka. Detil-detil lainnya memang tak saya perhatikan benar.
‘Lapak Gratis.’ Frase ini agak paradoks dalam keseharian kita di Indonesia. Atau lebih tepatnya, untuk kota-kota besar di Indonesia. Lapak, setahu saya, merujuk pada gelaran beberapa centi meter untuk berjualan. Meski pun lama kelamaan kata ini melebar penggunaannya. Bahkan toko online pun kerap disebut lapak oleh penggunanya. Kata ‘lapak,’ dengan demikian, dalam pemikiran saya, lebih banyak merujuk pada kegiatan ekonomi; bukan kegiatan ‘filosofis peneguh iman diri.’ Sebuah ‘lapak’ adalah kemungkinan transaksi antara penjual dan pembeli. Dan ‘lapak’ model ini tentu butuh sekeping tanah. Konsekuensinya, ‘lapak’ tak mungkin ‘gratis.’

Dalam sejarah, penguasaan terhadap sekeping tanah ada lebih dahulu sebelum tanah dimanfaatkan sebagai ‘lapak.’ Dan tanah sebagai suatu hal yang gratis, letaknya lebih jauh lagi dari itu, ketika manusia baru sedikit berbeda dari kera. ‘Lapak Gratis’ tadi, misalnya, dilaksanakan di atas sekeping tanah yang sudah dimodifikasi menjadi trotoar nan permai pemanja mata dan kaki para turis mancanegara dan domestik di depan Benteng Vredeburg. Dengan demikian, sudah ada sebuah kerja tertentu yang dilakukan di atas sekeping tanah yang dijadikan ‘lapak.’ Nilai dari kerja atas sekeping tanah tersebutlah yang memungkinkan sang tanah bisa menjadi ‘lapak.’ Nah, ketika lapak yang digelar di atas sebuah tanah yang punya nilai tertentu lantaran kerja tertentu diberi embel-embel ‘gratis,’ kita bisa melihatnya sebagai sebuah ketakhormatan terhadap nilai kerja tertentu tadi.
Mungkin saja, yang ada dalam kepala Satpol PP demikian sehingga mereka datang dan membubarkan ‘Lapak Gratis.’ Sebagai manusia sekadar lewat, saya memang tidak mengikuti dengan saksama perbincangan antara Satpol PP dan ‘panitia Lapak Gratis.’ Yang jelas, ‘Lapak Gratis’ tak berlanjut setelah didatangi beberapa anggota Satpol PP kala itu. Kabarnya, sebelum itu, Satpol PP sempat datang beberapa kali namun ‘Lapak Gratis’ masih ‘kepala batu’ untuk digelar.
Bagi Satpol PP bisa jadi ‘Lapak Gratis’ menggratiskan juga mereka. Tidak bayar pajak, tidak minta izin, dsb. Singkatnya, melangkahi sebuah kerja yang harusnya menjadi milik Satpol PP. Tentu, tak ada nilai dari keberadaan Satpol PP jika demikian. Maka, sekali lagi, barangkali, Satpol PP menghentikan kegiatan ‘Lapak Gratis’ agar kerja dan keberadaan mereka menjadi bermakna. Dan mereka memang semacam timer angkot berseragam. Atau jawara pasar yang legal. Tentang mereka memang hanya mampu menjual fisik dengan sedikit ancaman demi sekadar hidup, saya kira tak perlu dipanjang-lebarkan. Pembaca lebih mafhum adanya dari saya. Setali tiga uang sebenarnya mereka dengan fenomena FPI atau FBR. Konon, di kamar sempit seorang pemuda tanggung di kampung kumuh Jakarta, ada dua seragam tergantung; seragam FPI dan seragam FBR. Tergantung, tawaran gawean dari pihak mana maka salah satulah yang dicomot dari gantungan.
Namun begitulah. Setiap tanah, setiap tempat ada yang mempunyai. Jika ada yang tidak bertuan, mungkin kita hanya butuh menunggu. Saat ini kita mungkin bisa pergi ke pantai di beberapa daerah di Timur Indonesia dengan bebas. Tak perlu membayar karcis, tak perlu pula ‘terpaksa’ membeli makanan dan minuman di sana. Petani di beberapa daerah tersebut saat ini mungkin masih dengan senang hati membiarkan kita memetik buah kelapanya dan meminumnya. Dan itu bukan berarti mereka baik hati. Mereka hanya sekadar ‘belum maju’ saja. Atau dengan bahasa lain; mereka belum tersentuh lirikan investasi.
Investasi ini jualah yang membuat tanah tak bertuan menjadi bertuan dan lantas memungkinkan ada lapak di sana. ‘Lapak Gratis’ sedikit banyak memang juga bertujuan merespon hal-hal yang demikian. Di Kulonprogo ada rencana penambangan pasir besi. Jika rencana ini berjalan mulus, selain akan mengganggu produksi pangan, lebih jauh bisa jadi dengan pola cluster industry, DI Yogyakarta akan berubah wajahnya sama sekali. Penambangan pasir besi akan diikuti dengan bermunculannya berbagai macam pabrik untuk pengolahannya beserta penunjang lainnya. Konon, pelabuhan laut untuk kepentingan tersebut sedang dibangun.
Orang sekadar lewat seperti saya, dengan memori sepenggal-sepenggal, pada kunjungan berikutnya barangkali akan merasa sama saja dengan aroma tempat ini. Tentu berbeda dengan mereka yang menetap dan bergelut dengan tanahnya. Aroma yang semakin hari semakin berubah, pelan-pelan menyesakkan dada.
Tetapi untuk mempertahankan aroma sebuah kota barangkali bukan dengan bermimpi tentang Firdaus yang Hilang lantas berusaha kembali ke Firdaus itu. Yang hilang tetaplah hilang. Manusia sudah tertiup ke luar dari Firdaus dan tak mungkin ia kembali. Tanah yang gratis dan segala yang gratis memang pernah ada, bahkan sebelum Achilles dipanah pada kakinya atau bahkan sebelum Sangkuriang berbirahi pada ibunya sendiri.
Tiba-tiba saya merindukan jalanan Jakarta dengan kesemerawutan dan kemacetannya. Kemacetan yang terkadang membuat kepala kita sedikit berbisik, ‘sesungguhnya belum ada yang benar-benar menjadi tuan di ini negara. Jika ada yang menjadi tuan, titahnya tentu mampu mengurai macet.’ Dan kesemerawutan yang menyisahkan kepercayaan diri, ‘jika kau cepat dan pandai mengendarai kendaraanmu, cita-cita dan tujuanmu akan tercapai tepat waktu.’ ***
*Catatan: Dipublikasikan pertama kali di Rubrik Oase IndoProgress, 28 Juli 2013.