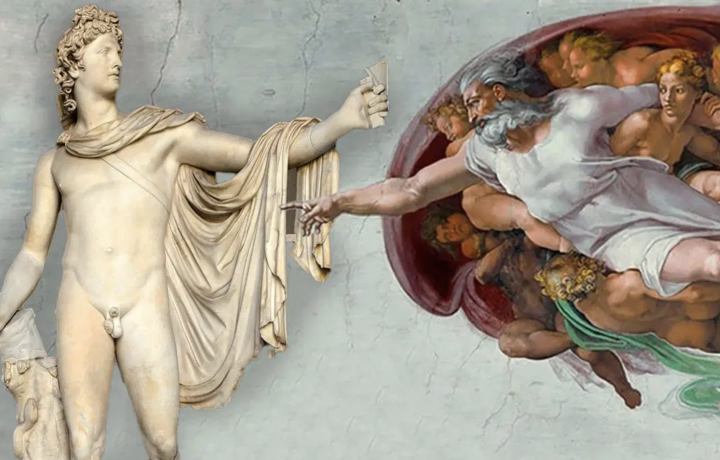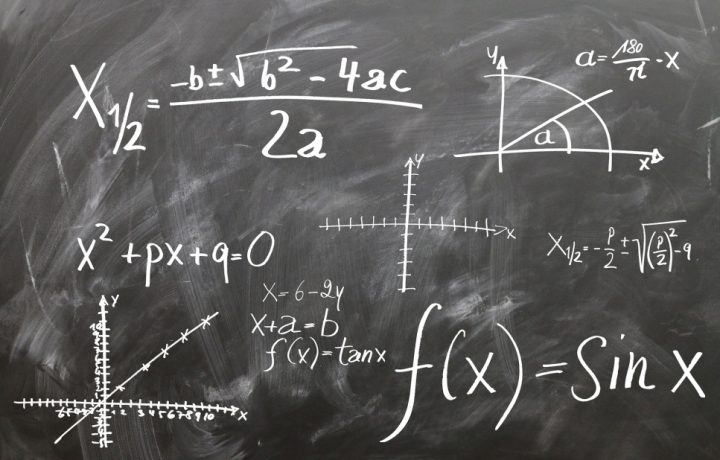Problem bagi saya ketika mendengar kata rekonsiliasi adalah bagaimana memahaminya secara sederhana. Pikir punya pikir, ternyata makna rekonsiliasi itu mirip dengan makna ‘baikan’ (bedakan dengan ‘balikan’). Tentu saja pemikiran sederhana ini jauh dari usaha untuk menyederhanakan keseluruhan makna dan keruwetan dari pemahaman akan rekonsiliasi itu sendiri. Tentu saja rekonsiliasi tak sesedernaha ‘baikan’. Jika sesederhana itu, pasti kita di Indonesia ini khususnya tidak butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Nyatanya, kita masih saja ruwet dengan masalah rekonsiliasi itu hingga hari ini.
Kembali lagi soal rekonsiliasi sebagai ‘baikan’ di atas. Peristiwa rekonsiliasi atau ‘baikan’ hanya mungkin terjadi ketika ada minimal dua pihak yang terlibat di dalamnya. Karena ‘baikan’ yang hanya mengandaikan satu pihak yang nyata — dalam pengertian pihak yang secara fisik dan material bisa diindrai entah dengan bantuan teknologi tertentu atau dalam arsip-arsip tertentu— hanya mungkin terjadi di dalam doa. Untuk ‘baikan’ yang demikian, bukan tempatnya tulisan ini untuk membicarakan ketulusan doa seorang yang taqwa. Hal yang penting selain pihak yang terlibat dalam peristiwa, pada ‘baikan’ juga terbersit makna perubahan kualitas yakni dari yang buruk menjadi lebih baik.
Nah, dengan demikian, pada ‘baikan’ ada pengandaian sebuah keadaan negatif tertentu sebelumnya. Tentu agak aneh ketika ada dua orang atau ada dua pihak yang tidak punya masalah sama sekali di masa lalu, tiba-tiba berinisiatif untuk berekonsiliasi atau ‘baikan’. Sama aneh dan tak logisnya dengan seorang jejaka yang belum pernah pacaran tetapi berusaha sekuat tenaga untuk balikan dengan mantannya. Rekonsiliasi dengan demikian bukan perkara trendi mengikuti zaman; rekonsiliasi pada dasarnya adalah upaya untuk mengubah sesuatu yang negatif yang terjadi antara beberapa pihak sebelumnya menjadi sesuatu yang lebih baik untuk hari ini dan untuk hari-hari selanjutnya.
Maka jelaslah, rekonsiliasi sebagai aksi ‘berbaik-baikan’ mengandaikan atau bahkan mensyaratkan dua hal di muka; keterlibatan lebih dari satu pihak dan adanya perubahan kualitas yang diharapkan terjadi setelah rekonsiliasi terjadi.
Ihwal Pertama
Di dalam konteks rekonsiliasi sebagai ‘baikan’ di muka itulah kita — minimal saya — barangkali bisa membicarakan dengan lebih menyenangkan perihal rekonsiliasi pelanggaran HAM di Indonesia. Di Indonesia ini — tentu saja bukan hanya Indonesia karena kita ini negara besar dengan budi pekerti seluhurluhurnya; pasti kejahatan yang kita lakukan itu adalah juga kejahatan yang dilakukan orang lain yang budi pekertinya tak seluhur kita sejak nenek moyang — tak berbilang sungguh hal yang menyesakan hati alias pelanggaran HAM-nya. Dari masalah seorang nenek tua yang divonis bertahun-tahun penjara lantaran mencuri singkong tetangga demi perutnya yang lapar — padahal kenyang adalah hak setiap orang — hingga pembantaian dan pemenjaraaan tanpa pengadilan bagi para anggota, pendukung, dan simpatisan PKI pasca peristiwa G 30 S 1965.
Nah, masalah terakhir di atas, seperti yang mungkin banyak dari kita sudah ketahui, pada tahun 2015 ini berusia genap 50 tahun. Dilihat dari angka tersebut maka wajarlah bila usaha rekonsiliasi yang di tahun-tahun sebelumnya pernah dicoba oleh pelbagai kalangan di tahun ini kembali didengungkan dan digencarkan. Atau minimal ‘dirayakan’. Tentu dengan pelbagai strateginya. Orde Baru Ok. Video, sebuah festival media arts besutan ruangrupa misalnya pada perhelatan tahun 2015 ini mengangkat tema Orde Baru. Grand Illusion, tema Festival Film Dokumenter dan Eksperimental Arkipel juga dengan sedikit kejenialan imajinatif bisa kita baca dalam kerangka itu.

Membicarakan perayaan dan usaha-usaha itu bagi saya pertama-tama harus dijernihkan dulu duduk perkara sesiapa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Karena rekonsiliasi sebagai ‘baikan’ tidak bisa tidak harus melibatkan lebih dari satu pihak yang terlibat dalam peristiwa 1965 dan turunannya itu. Sudah terlalu banyak buku, film, dan juga memoar tentu saja mengenai peristiwa ini. Dari sana sebetulnya kita sudah bisa menemukan pihak-pihak mana sajakah yang terlibat. Tentu saja kita diandaikan rajin membaca. Pertanyaan tentang pihak yang terlibat ini nantinya akan membawa kita kepada soal perlukah kita terlibat di dalam usaha rekonsiliasi itu, penting atau tidakkah kita melakukan rekonsiliasi atau ‘baikan’ tersebut.
Dari literatur-literatur tentang peristiwa 1965 — untuk selanjutnya, sebutan Peristiwa 1965 di dalam tulisan ini merujuk tidak hanya pada peristiwa G 30 S 1965, tetapi juga merujuk pada peristiwa turunannya yakni pembantaian, pemenjaraan tanpa pengadilan, serta pencabutan hak-hak sipil pada mereka yang dianggap terlibat — dengan beragam versinya, tentu banyak pihak yang bisa dituduhkan. Untuk tulisan ini baiklah saya menyebutkan beberapa yang paling sering terdengar; PKI, negara, tentara, bangsa Indonesia sendiri, dan pihak asing.
Dari kelima pihak yang disebutkan di atas, beberapa di antaranya tentu saja tak terkena langsung kepada kita. Jika kita melihat PKI sebagai pelaku, maka sesungguhnya tak perlu ada rekonsiliasi-rekonsiliasi lagi. Pasalnya, PKI itu sendiri sudah tidak ada di bumi Indonesia ini sejauh TAP MPRS XXV/1966 belum dicabut. Maka, membicarakan rekonsiliasi tanpa salah satu pihak yang terlibat di dalamnya sudah tidak eksis lagi, sama saja dengan berharap balikan tetapi mantan pacar kita sendiri sudah wafat. Jika bukan gila, minimal stress beratlah yang menjadi latar belakang keinginan kita untuk rekonsiliasi itu.
Maka jika kita masih melihat PKI sebagai salah satu pihak yang terlibat di dalam sebuah hal yang hendak direkonsiliasi itu, maka memulihkan kembali keberadaan mereka yang selama ini dihilangkan adalah salah satu hal penting dalam usaha ‘baikan’ itu. Toh, ‘baikan’ bukan berarti kita melupakan dan menghilangkan salah satu pihak yang terlibat di dalam sebuah peristiwa, melainkan menerima juga keberadaannya. Rekonsiliasi adalah juga pengakuan akan keberadaan pihak lain, meskipun seujung rambut pun kita tak setuju dengan isi kepala mereka, tak searoma pun yang kita sukai dari bau badan yang menguap dari pori-pori mereka.
Nah, karena PKI itu keberadaannya pun tak diakui di negeri ini setidaknya selama TAP MPRS XXV/1966 belum dicabut, maka sudah jelaslah bahwa kita — yang saya maksudkan dengan kita adalah kawula muda yang udara Orde Baru pun kita hirup secara naluriah tanpa ada pemahaman bahwa manusia itu butuh bernafas untuk hidup — bukanlah bagian dari mereka. Maka, jika memang benar rekonsiliasi itu ada dan kita termasuk bagian di dalamnya, kita tentu berada pada pihak yang lain.
Ihwal Kedua
Bayangkanlah Anda berbaikan kagi dengan seorang karib yang menelikung pacar anda atau gebetan anda. Alasan di balik berbaikan itu — misalnya ternyata gadis atau jejaka yang menjadi sumber percecokan anda ternyata ke pelaminan bukan bersama anda atau pun karib anda — tentu tidak kita perbincangkan di sini. Ada kualitas perkariban tertentu di antara anda dan karib anda yang ikut dipulihkan bersama peristiwa berbaikan tersebut. Misalnya, karib anda sudah boleh nginap kalau kemalaman di kosan anda atau anda sudah boleh meminjam duit jika kesulitan ke karib anda.
Nah ketika berbicara tentang rekonsiliasi dalam rangka pelanggaran HAM misalnya, kualitas apa yang hendak kita ubah? Tentu saja perubahan kualitas ini bisa 100 persen bisa beberapa persen saja. Dan tentu saja, niat yang benar dan baik selalu berharap pada perubahan 100 persen, bila perlu 1000 persen. Kembali ke contoh Anda dan karib anda tadi misalnya, ternyata perubahan setelah berbaikan adalah anda berdua kembali saling menyapa tetapi tidak sampai ke tingkat minjam vinyl misalnya.
Jika kita tarik ke perihal rekonsiliasi dalam rangka peristiwa 1965 yang sudah berusia 50 tahun itu, kualitas apa yang kita inginkan berubah? Jika kualitas yang ingin diubah itu adalah dikembalikannya hak- hak sipil dari tertuduh di peristiwa itu, rupanya sudah sangat terlambat. Apalagi yang diharap akan didapat oleh mereka-mereka yang sudah uzur itu dengan dikembalikannya hak-hak sipil mereka? Permohonan maaf kepada mereka? Memang hal- hal terakhir di atas bukanlah tidak penting. Tetapi apakah kita memang hanya mau seminimalis itu dan seolah-olah tetap melihat mereka sebagai korban, sedangkan di pihak lain, negara bangsa, yang juga terlibat di dalamnya tidak terjadi perubahan apa- apa? Perubahan yang baik adalah perubahan yang terjadi pada semua pihak yang berbaikan.
Dengan demikian, perlu ada pengakuan dari yang melakukan kesalahan terhadap mereka yang diberlakukan tidak adil. Rekonsiliasi tidak bisa hanya berdampak ‘positif’ pada satu pihak saja. Negara bangsa sebagai pihak yang juga terlibat, bahkan mungkin yang paling berperan, dalam peristiwa- peristiwa pelanggaran HAM perlu juga mengubah dirinya. Jangan sampai kita memahami rekonsiliasi sebagai pihak yang satu mengembalikan hak-hak tertentu dari pihak lainnya, sedangkan pada dirinya sendiri dianggap tak ada apa-apa yang perlu dan butuh untuk diubah menjadi lebih baik.

Pada hemat saya rekonsiliasi adalah momen di mana setiap pihak yang terlibat memeriksa diri masing-masing dan meletakkan di belakang hal-hal yang bersifat negatif pada dirinya masing-masing dan berniat memperbaikinya. Dalam konteks Peristiwa 1965 misalnya, sebagai negara bangsa, rekonsiliasi perlu kita lihat sebagai cara untuk menyadari kesalahan, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan kekerasan yang membabi buta dengan semena-mena. Di sini pun perlu dilihat kekerasan seperti apa yang dilakukan itu.
Penutup
Di akhir-akhir tulisan ini tiba-tiba ada sesuatu yang terbersit di pikiran saya. Rekonsiliasi atau berbaikan itu hanya bisa terjadi lantaran sebelumnya ada kesalahan tertentu di setiap pihak yang terlibat di dalam sebuah peristiwa yang hendak dipulihkan. Namun apakah rekonsiliasi dengan demikian cocok untuk sebuah kesalahan di masa lalu yang dilakukan hanya oleh satu pihak saja namun dampaknya mencapai banyak pihak?
Kembali ke Peristiwa 1965 sendiri, pembacaan saya masih simpang siur dan belum ada kejelasan seperti apa sebenarnya peristiwa itu terjadi. Kejernihan pihak mana melakukan apa dan karena apa, belumlah pula jelas. Setidaknya dalam kerangka pembacaan saya pada ihwal peristiwa itu sejauh ini. Maka rekonsiliasi atau berbaikan sebagai meninggalkan yang negatif di masa lalu begitu saja agar kita bermaaf-maafan, saling menerima, dan lantas hidup berdampingan dengan harmonis, barangkali sesuatu yang perlu dipikirkan kembali. Apakah langkah itu justru mendiamkan begitu saja sejarah yang terjadi?
Dalam kerangka pelanggaran HAM, bagi saya rekonsiliasi haruslah dimulai dengan penjernihan duduk masalahnya terlebih dahulu. Mengenal dan mengetahui pihak-pihak yang terlibat, dampaknya seperti apa, dan bagaimana peran segala pihak yang terlibat di dalam peristiwa yang hendak dipulihkan tersebut. Jika ternyata Peristiwa 1965 ternyata adalah ulah hanya satu pihak saja yang keblinger dan lantas dampaknya meluas seluas-luasnya dan menguntungkan pihak yang keblinger itu sendiri serta merugikan sungguh bagi pihak yang lainnya, jangan-jangan kita bukan butuh rekonsiliasi. Melainkan, kita butuh absolusi.
*Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di zine Pamflet, Edisi 5, Agustus 2015.