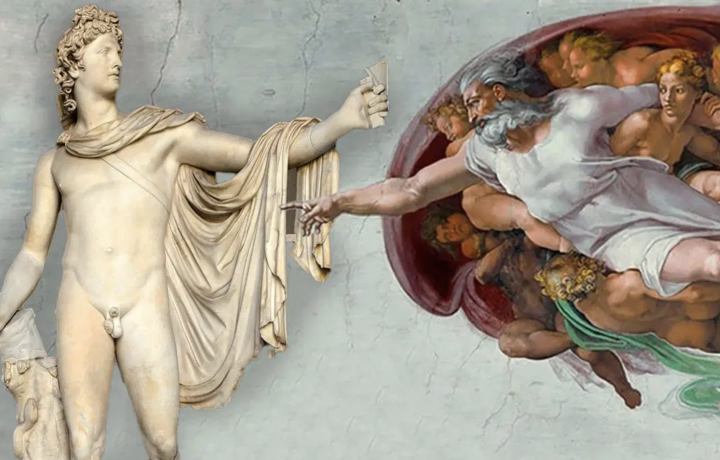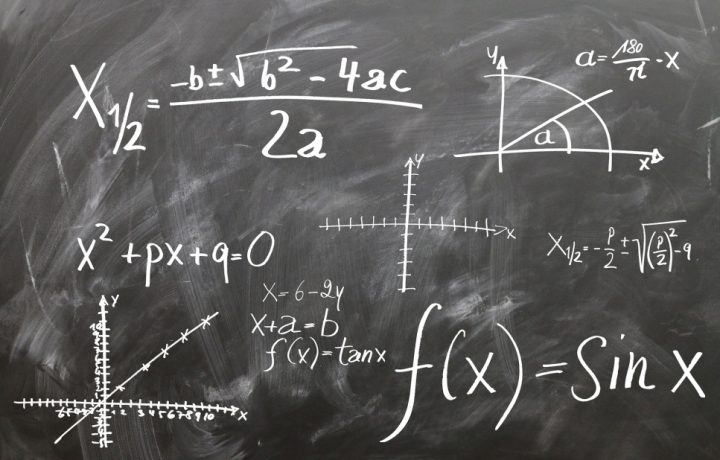Tentang Pemilu Legislatif yang baru saja lewat sebagai sebuah pemilu yang meninggalkan banyak noda hitam tentu kita semua telah mengamininya. Bahkan, Kompas, salah satu harian terbesar di negeri ini pun menurunkan sebuah judul tulisannya dengan sangat provokatif demikian, “Pemilu yang Paling Amburadul” (Kompas, 17/4/2009).
Bukan sebuah kesalahan bila kita menilai pesta demokrasi yang telah lewat itu demikian. Ketidak-beresan Pemilu yang sejatinya tidak terjadi di Pemilu 1999 dan 2004 malah terjadi di Pemilu 2009 ini. Sepertinya, bangsa ini tidak pernah belajar dari pengalaman. Padahal, kita semua tentu sudah tahu dan hafal luar kepala dengan pepatah ini, “pengalaman adalah guru kehidupan” dan “siapa yang tidak belajar dari sejarah, akan dihukum oleh kehidupan”. Tapi begitulah laku hidup demokrasi di negeri kita ini.
Beberapa hari lalu, saya menemukan sebuah pendefinisan ulang akan demokrasi yang cukup mengejutkan namun menyenangkan. Hal itu terjadi di Komunitas Saliahara, Pasar Minggu. Di sana, pada 13 Mei 2009 lalu, diselenggarakan diskusi atas buku Demokrasi dan Kekecewaan. Diskusi ini menampilkan pembicara, di antaranya, A. Setyo Wibowo, pengajar STF Driyarkara dan Sandra Hamid, aktifis LSM.
Buku Demokrasi dan Kekecewaan sejatinya adalah kumpulan tulisan untuk menanggapi orasi ilmiah Goenawan Mohammad pada acara Memorial Lecture Nurcholis Madjid beberapa bulan yang lalu. Namun, bukan tentang buku itu pembicaraan kita di tulisan ini. Saya akan mecoba memaparkan sebuah arti demokrasi yang disarikan Setyo Wibowo dalam makalahnya untuk diskusi tersebut.
Dalam makalah bertajuk “Kesetaraan sebagai Presuposisi La Politique”, Wibowo memaparkan pembacaannya atas pemikiran filosof kontemporer Prancis Jaques Rancière. Demokrasi bagi Rancière adalah kesetaraan, sebuah kesetaraan yang radikal. Berangkat dari ilustrasi tentang demokrasi di Athena pada masa lampau, demokrasi mengandaikan kesetaraan hampir pada segala bidangnya bagi seluruh warga Polis. Rancière memang agak menyepelekan kenyataan bahwa ada distingsi tegas antara “kelas bebas” dan “kelas budak” yang berlaku di Athena saat itu.

Bagaimana praktek radikalisasi kesetaraan ini di Athena? Rancière, sebagaimana dipaparkan A. Setyo Wibowo, mengafirmasikan kesetaraan ini dengan kesempatan menduduki kursi jabatan wakil rakyat Athena saat itu. Laku demokrasi menjadi seperti melempar dadu. Artinya, semua orang, tanpa kecuali, punya kesempatan untuk menjadi wakil rakyat (senat kota). Dan kesempatan itu diatur dengan cara melempar dadu. Mekanisme pelemparan dadupun diatur sedemikian sehingga tak ada satu warga pun, tanpa kecuali, yang berkemungkinan menjabat kedudukan itu dua kali dalam masa hidupnya.
Dengan ilustrasi ini, kita harus membuang jauh-jauh dari kepala kita distingsi antara politisi dan warga non politisi. Dengan demokrasi sebagai laku melempar dadu, semua warga negara adalah politisi. Inilah demokrasi dalam artinya yang radikal. Demokrasi sebagai sebuah kesetaraan radikal. Tak ada lagi di sini, kedudukan-kedudukan yang berbeda-beda. Tak ada yang lebih mampu dan tak ada yang lebih tak mampu. Tak ada yang bermodal dan tak ada yang lebih tak bermodal. Semuanya sama. Maka, dengan demokrasi sebagai sebuah pelemparan dadu, Pemilu sebagaimana yang kita ketahui dan kita bayangkan saat ini jelas tak berlaku lagi. Tak ada lagi pemilihan umum sebagai artikulasi demokrasi. Karena demokrasi radikal dalam pemahaman sebagai kesetaraan radikal tak mengandaikan siapa yang lebih didukung dan siapa yang lebih tak didukung, siapa yang lebih pantas dan siapa yang lebih tak pantas, melainkan semuanya setara dalam dukungan dan semuanya pantas saja untuk mendukung.
Bila kesetaraan radikal ini kita kaitkan dengan nitos mesias atau ratu adil yang terus muncul dalam setiap Pemilu kita dan di setiap kebudayan, maka kesimpulannya gampang saja; semuanya bisa dan pantas menjadi Sang Ratu Adil. Dengan demikian, mitos yang utopia ini terbunuh dengan sendirinya. Maka, upaya radikalisasi utopia yang coba diupayakan oleh kaum Neo Marxisme semisal Fredrich Jameson (lih. Adam Roberts, 2000; A Routlege Critical Thinkers; Fredrich Jameson khusus pada bagian Modernism and Utopia: Fables of Aggression) mendapat bentuknya yang tepat di sini atau bisa juga tidak dibutuhkan lagi karena niscaya sudah hadir pada diri setiap warga. Warga tak perlu lagi menunggu datangnya ‘masa keemasan nan jaya’, karena masa itu akan hadir bila diupayakan oleh sang Ratu Adilnya; yakni warga itu sendiri.
Demokrasi sebagai kesetaraan yang radikal ini saya kira sangat tepat untuk menghapuskan kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di negeri ini dan dunia selama ini. Sebagaimana yang diutarakan A. Setyo Wibowo, demokrasi kita selama ini hanya dimiliki oleh para oligharki saja; mereka yang punya uang yang lebih, oleh mereka yang punya dukungan yang lebih, dan oleh mereka yang punya intelegensia yang lebih pula. Demokrasi sebagai sebuah kesetaraan ternyata, tanpa kita sadari, dipraktekan sebagai sebuah ketidaksetaraan. Tepatlah bila mulai sekarang kita memikirkan tentang demokrasi sebagai sebuah kesetaraan radikal. Anda, saya, tukang ojek di depan STF Driyarkara, Jeihan di warung kopi pojok, Si Ucok di Proyek Senen, semuanya berhak dan harus diberi kesempatan menduduki jabatan untuk mengatur negara ini. Karena kita semualah pemilik dari negara ini, dan karena kita semua sepakat tentang bentuk demokrasi sebagai yang terbaik dari kumpulan yang jelek. Tentu bersamaan dengan itu, kita pun memikirkan mekanisme yang tepat untuk mewujudkan demokrasi sebagai pelemparan dadu itu, memikirkan instrumen-instrumen pendukung, pengawas, pemantau untuk mewujudkan itu. Demokrasi adalah kesetaraan yang radikal. Di luar dari pada itu adalah penjajahan yang berkedok demokrasi.
*Catatan: Edisi tulisan lama, ditulis pada 2009 yang lalu untuk keperluan perkuliahan.