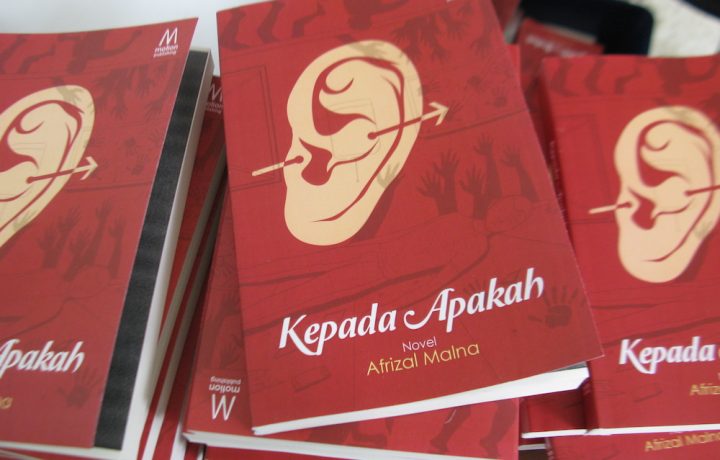Tulisan ini merupakan ringkasan atas buku Saatnya Muslim Bicara: Opini Umat Muslim tentang Islam, Barat, Kekerasan, HAM, dan Isu-isu Kontemporer Lainnya. Buku ini adalah sebuah usaha untuk mencari tahu apa sebenarnya isi pemikiran orang Muslim tentang Barat dan Islamnya serta pandangan orang Barat tentang orang Muslim dan Islam mereka. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa buku ini semacam mau menjadi sebuah wadah rekonsiliasi pandangan kedua belah pihak. Tentu sebuah usaha rekonsiliasi mengandaikan sebuah kesalahan pandangan sebelumnya, jika tidak mau kita sebut dengan pertikaian.
Rencana tulisan ini adalah pertama kita akan melihat ringkasan isi buku ini. Kedua, kita akan sedikit mempermasalahkan isi buku, menimbang-nimbang relefansi buku dengan Indonesia saat ini, lantas kita akan member sedikit kesimpulan yang sudah terlihat secara sekilas dari judul tulisan ini.
Ringkasan Buku
Buku ini merupakan rangkuman dari sebuah survey raksasa yang dilaksanakan oleh Gallup dalam rentang waktu sekitar enam tahun dan mencakup 35 negara berpenduduk lebih mayoritas muslim. Dengan teknik survey yang mumpuni, survey ini mengklaim telah menjadi menjadi “…..kajian terbesar dan paling serbacakup yang pernah dilakukan terhadap Muslim kontemporer”.
Survey ini tentu saja dipicu oleh sebuah peristiwa menghebohkan pada 11 September yakni penyerangan terorisme atas dua gedung di Amerika yang menandakan supermasi Negara tersebut. Yang menjadi tertuduh dalam peristiwa itu adalah Islam. Tuduhan itu semakin menjadi opini publik atawa keharusan tentang kaum musli; bahwa Muslim adalah teroris, bahwa Muslim adalah pembunuh, dan bahwa Muslim itu barbar dsb. Tentu tak ada yang lebih bertanggung-jawab atas pandangan ini selain mass media. Kita tahu, dunia saat ini adalah dunia informasi. Bahkan mantra Bacon-pun sudah direvisi oleh banyak orang misalnya Castels, “informasi adalah kekuatan.”
Pandangan ini tumbuh subur di dunia barat pasca 11 September dan bahkan merembes pula pada sebagian kecil ras manusia yang hidup di dunia Muslim yakni para minoritas yang mungkin selama ini hidup dalam kerangkeng keminoritasannya sendiri sehingga bahkan buta tentang lingkungan sekitarnya, sehingga meng-copy paste begitu saja propaganda media barat.

Siapatah Kaum Muslim
Seperti yang sudah menjadi pembuka kita dalam tulisan ini, pandangan dunia barat pada dunia muslim pasca 11 September adalah pandangan-pandangan yang beraroma negatif dengan berbagai varian kenegatifannya. Survey Gallup ternyata membuktikan bahwa sesungguhnya hampir 60 % masyarakat barat sesungguhnya tidak tahu apa itu muslim dan bagaimana orang muslim berpikir. Maka, sesungguhnya pandangan masyarakat barat yang negatif tentang masyarakat muslim adalah sebuah pandangan tanpa alasan atau memang tak ada pandangan seperti itu melainkan hanya sebuah rekayasa saja.
Umat Islam di dunia mencapai 1,3 milyar. Kenyataan menarik bahwa mayoritas umat Islam tidak tinggal di Arab, melainkan tersebar di berbagai penjuru bumi. Mayoritas umat Islam ada di Asia yang bukan Arab dan Afrika. Menariknya lagi, jutaan dari umat Muslim itu hidup di Eropa, Amerika, dan Kanada. Itu berarti Muslim sudah terintegrasi juga dalam dunia barat. Ini tentu saja mematahkan anggapan selama ini yang tentu saja salah bahwa mayoritas Muslim hidup di Arab.
Dalam hal agama, Muslim sendiri terbagai dalam berbagai aliran dari yang paling radikal sampai yang paling moderat. Sebut saja dua aliran besar yakni Sunni dan Syi’ah. Sunni dan Syi’ah ini sendiri di dalamnya masih terbagi lagi ke dalam beberapa aliran kecil lainnya. Satu ciri khas utama umat muslim yang beragam dalam aliran-alirannya ini yakni dalam kehidupan masyarakat Muslim, keimanan akan apa yang dipercayainya dalam ke-Islam-annya dan keluarga menjadi hal penting bagi mereka. Kepercayaan dan keluarga dianggap sebagai sebuah jalan menuju masa depan yang lebih baik.
Cinta kasih dan kedamaian adalah juga hal penting bagi masyarakat Muslim. Hampir mayoritas responden survey menjawab bahwa mereka pro atas kedamaian dan cinta (95% di Mesir, 92% di Arab Saudi). Dari kenyataan ini adalah mustahil mengidentikan dunia Islam dengan kekerasan.
Demokrasi atawa Teokrasi
Demokrasi yang dilabeli sebagai system bernegara yang baik dari segala sistem bernegara lain adalah juga mayoritas pandangan kita saat ini. Dengan alasan inilah, Amerika yang menganut demokrasi liberal itu mengangkat dirinya menjadi ‘polisi dunia’. Demokrasi yang demikian baik di dalam benak Amerika itu menjadi suatu sistem yang dianggapnya ‘harus’ dianut setiap bangsa di dunia ini. Dengan alasan inilah Amerika merasa benar dan tak berdosa untuk menginfasi Afganistan dan Irak.
Bagaimana pandangan masyarakat Muslim atas faham demokrasi ini? Hal ini menjadi salah satu survey Gallup juga. Mayoritas masyarakat Muslim memang hidup di dalam negara dengan sistem yang bukan demokrasi. Namun, bagaimana pandangan masyarakat muslim pada demokrasi, entah mereka ada dalam sistem itu mau pun tidak? Ternyata, kesimpulan dari survey tersebut mengindikasikan bahwa hampir mayoritas muslim menerima dan menganggap baik nilai-nilai demokrasi.
Sekali lagi, adalah salah kaprah bila memandang dunia muslim sebagai dunia yang membenci dan menaruh curiga terhadap sistem demokrasi.
Di lain pihak, syariat Islam sebagai pendasaran negara didukung juga oleh mayoritas muslim. Namun demikian mereka pun melihat peran pemuka agama dalam menangani peraturan dan undang-undang kenegaraan sebagai sesuatu yang negatif. Bagaimana mendamaikan kedua pandangan yang berbeda ini; di satu sisi memandang demokrasi sebagai sesuatu yang baik dan di sisi lain syariat Islam pun tak kalah pentingnya posisinya dalam kehidupan bernegara. Gallup mensinyalir adanya kecenderungan dari masyarakat muslim untuk menjadikan Syairat Islam sebagai sebuah pokok dari sebuah sistem demokrasi.
Pandangan Muslim atas Amerika sebagai ‘polisi demokrasi dunia’ ternyata lebih bersifat negatif. Masyarakat Muslim di Lebanon, Sierra Leone dan Afganistan menganggap Amerika tidak serius dalam menegakan demokrasi (54%, 68%, dan 53%). Yang menarik adalah kaum muslim yang radikal (72%) dan kaum muslim yang moderat (52%) sepakat dalam hal kesangsian terhadap keseriusan Amerika dalam menegakan demokrasi. Penyebab hal ini adalah syarat ganda yang dipakai Amerika Serikat dalam menegakan demokrasi dan HAM di Negara Muslim.
Tentang Teknologi dan Moralitas
Citra diri Amerika Serikat sebagai negara yang sungguh menegakan HAM ditanggapi oleh masyarakat Muslim dalam dua pandangan yang berbeda yang bisa dikatakan ambigu. Di satu sisi, pandangan mereka atas Amerika Serikat dan dunia barat sangatlah positis dalam hal kemajuan teknologi, kebebasan berpendapat dan sistem peradilan. Yang terakir, dianggap sebagai konsekuensi dari sikap negeri-negeri barat yang menjunjung tinggi HAM. Namun di sisi lain mereka melihat kejanggalan ketika peradilan dan HAM ini diterapkan di dunia mereka yakni dunia muslim. Mereka menganggap Amerika Serikat tidak serius dalam hal HAM ini karena fakta membuktikan bahwa Amerika Serikat sungguh kejam dalam memperlakukan masyarakat muslim di Guantanamo dan Abu Gharib.
Survey Gallub di sepuluh Negara bermyaoritas muslim menunjukan keambiguan dalam pandangan terhadap Amerika Serikat. Tak sedikit yang mengasosiasikan AS dengan kekejaman, keagresifan, keangkuhan dan kerusakan moral (68%, 66%, 65% dan 64%). Namun mereka juga sangat mengagumi dan menghargai kemajuan teknologi dan sains yang dicapai Amerika Serikat (68%).
Islam yang Radikal
Peristiwa 11 September dijadikan tolok ukur oleh Gallup dalam rangka membedakan golongan radikal dan tidak. Pertanyaan yang intinya mencari tahu pendapat seputar dapat dibenarkan atau tidaknya peristia 11 September dan apakah AS adalah musuh adalah senjata pembedaan itu. Hasilnya adalah 7% adalah golongan radikal dan selebihnya tidak.
Simpulan survey ini semakin menguatkan kesalah-kapraan pandangan masyarakat barat terhadap Islam itu. Pasca 11 September Islam lantas identik dengan radikalisme yang berarti menghalalkan kekerasan. Angka hasil survey (7%) sungguh menunjukan realitas yang jauh dari penilaian tersebut.
Ada perbedaan mendasar dari kaum radikal dan kaum moderat. Kaum radikal lebih merasa takut atas ketidakberdaulatnya negara mereka akibat intervensi asing. Sedangkan kaum moderat lebih takut pada keselamatan ekonomi negara mereka. Di sini simpulan bisa kita ambil bahwa radikalisme adalah sebuah reaksi atas kesewenang-wenang negara barat yang merasa berhak mengintervensi kedaulatan negara lain. Maka, pokok permasalahan radikalisme bukanlah terletak pada soal agama melainkan politik. Budaya dan agama dari masyarakat barat ternyata bukanlah hal penting yang memicu perlawanan kaum radikal.
Keinginan Perempuan Muslim
Islam oleh masyarakat barat sering dilihat sebagai sebuah agama paternalisitik. Dengan demikian, penindasan terhadap perempuan adalah hal lumrah dan bahkan direstui oleh agama, demikian pemikiran masyarakat barat. Penyerangan Amerika Serikat atas Irak dan Afganistan salah satu alasannya adalah mengeluarkan kaum perempuan muslim dari belenggu ini.
Survey membuktikan bahwa hal ini merupakan sebuah kesalahan pandangan barat terhadap dunia muslim. Senada dengan masalah kepercayaan masyarakat muslim pada agama mereka, pandangan mereka terhadap perempuan dan pandangan perempuan mereka terhadap diri mereka pun demikian; bahwa hak-hak perempuan sudah diatur dengan sangat baik oleh agama mereka sehingga ketika diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari hal itu menjadi sesuatu yang baik adanya.
Tentu saja pandangan barat atas perempuan berbeda dengan pandangan muslim atas perempuan. Ada banyak pihak yang menganggap pandangan barat atas perempuan akan menyelamatkan perempuan muslim dari belenggu mereka ketika negara mereka mengadopsi pandangan-pandangan barat tersebut. Memang banyak kaum perempuan muslim yang menganggap aspek-aspek tertentu dari pandangan barat tentang perempuan sebagai sesuatu yang baik. Namun untuk mengadopsinya begitu saja, mereka tak sepakat. Yang lebih mereka tekankan adalah proses penyaringan unsur barat ini sehingga bisa bersinergi dengan pandangan dan budaya mereka.
Kaum perempuan muslim tidak melihat kesejajaran mereka dengan laki-laki sebagai sesuatu yang penting benar. Kaum muslim perempuan dalam hal ini lebih menganggap kesalahan-kesalahan dalam ranah publik sebagai sebuah masalah yang perlu segera dicari jalan keluarnya. Masalah seperti korupsi, kurangnya persatuan adalah isu-isu yang dianggap mereka perlu untuk ditanggulangi segera.

Kebersamaan atau Saling Membenci
Setelah hasil survey menyatakan dengan gamblang kesalahan-kesalahan dari pandangan masyarakat barat, buku ini sampai pada kesimpulan bahwa dunia harus hidup bersama tanpa ada saling membenci, syak wasangka, dan saling menyerang. Namun, dari pembacaan saya, tidak terlihat sama sekali bagaimana solusi seputar menghentikan kesombongan bangsa barat dalam hal ini Eropa untuk berhenti mengintervensi negara lain. Kecemasan kaum radikal bahwa bangsa mereka akan kehilangan kedaulatan karena intervensi pihak asing sepertinya menjadi sebuah kenyataan yang ditinggalkan sepi di belakang sana. Jika diandaikan dengan lembaran kertas, maka 7% yang radikal itu pada akhirnya harus bersedia ditempatkan di tumpukan paling bawah. Sekali lagi, demokrasi yang notabene adalah milik barat mendiamkan sebagian kecil dunia muslim. Ingatlah bahwa ketika buku ini menggunakan sistem survey dan itu berarti menggunakan pola pikir barat, dengan sendirinya dia sudah berpihak barat dan dengan demikian sesungguhnya alih-alih mau membuka dialog, buku ini sendiri sudah menempatkan dirinya di satu pihak tanpa mau masuk ke pihak lainnya.
Sedikit Catatan
Poin satu. Seperti yang sudah sedikit diutarakan di awal tulisan ini, bahwa hubungan dunia barat dan dunia muslim itu sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, bahkan hampir selama adanya dua kebudayaan itu. Bahkan, sebuah masjid pertama di Inggris bisa berdiri atas restu ratu Inggris waktu itu. Bahkan Aristoteles kembali bisa menggerakan filsafat barat lantaran dunia Islam, bahkan adu otot dan senjata antara dunia barat dan dunia muslim sudah terjadi berkali-kali dan yang paling melegenda adalah serial Perang Salib itu.
Kenyataan sejarah ini memusingkan kepala kita. Apa pasal? Sebuah pengalaman pertemuan yang begitu lama ternyata tidak jua membuka pintu saling memahami. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah apakah manusia memang sebodoh itu sehingga membutuhkan waktu beribu-ribu abad untuk saling memahami di antara sesama mereka? Saya rasa, terlalu dini untuk menjawab ya atas pertanyaan retoris ini.
Kenyataan kedua yang kiranya penting untuk diutarakan di sini adalah bahwa banyak masyarakat muslim hidup di dunia barat. Itu berarti, dalam sistem yang demokratis ala barat, seharusnya masyarakat muslim sudah membaur dan menjadi satu bagian dengan barat itu sendiri. Walau pun mereka minoritas, namun bukankah justru sistem demokrasi itu akomodatif terhadap minoritas? Lagi pula, ketika kaum muslim bisa hidup di sebuah negara dengan sistem demokrasi, itu berarti sungguh tak ada sebuah pertentangan berarti antara muslim dan barat (dalam hal ini demokrasi).
Dua kenyataan ini, sejarah pertemuan yang panjang serta fakta kekininan di mana di satu negara bersistem demokrasi Muslim dan Barat hidup berdampingan, membuat kita akan memandang munculnya pandangan negatif barat terhadap muslim sebagai suatu peristiwa yang aneh, bagaikan gitar tanpa snar namun bisa menghasilkan intro stairway to heaven yang bagus.
Mari coba menjelaskan kejanggalan ini dari sebuah pokok pemikiran Karl Marx. Marx menjelaskan bangunan masyarakat dalam dua tingkatan yakni basis struktur dan supra struktur atau lebih lazim disebut dengan bangunan bawah dan bangunan atas. Pada awalnya, bangunan bawahlah yang menentukan bangunan atas, namun dalam perjalanannya kemudian, bangunan atas ini mungkin untuk mengintervensi bangunan bawah. Jika pada tataran bangunan atas (sejarah pertemuan yakni pengalaman, sistem negara, toleransi, kepercayaan agama, dll) sudah tidak ada masalah, tentu bangunan bawahlah (ekonomi) pemicu kejanggalan itu.
Fakta bahwa Sadam Hussein menaikan harga minyaknya yang menyebabkan ekonomi dunia terguncang pra invasi Amerika ke Irak adalah salah satu bukti kebenaran analisa ini. Jadi, bukan soal Irak itu tidak demokratis atau perempuan di sana hidup dalam belenggu abad pertengahan (ingatlah kekristenan yang menjadi salah satu dasar peradaban barat itu pun sampai sekarang masih patriarkis) lah yang menyebabkan invasi itu, melainkan harga minyak dari Timur Tengah yang menjadi mahallah pemicunya.
Penyerangan terhadap dua gedung kembar yang salah satunya menyimbolkan ekonomi Amerika Serikat pun bisa kita lihat sebagai reaksi atas kondisi ekonomi dunia. Saat itu globalisme sedang dalam masa-masa awal kemunculannya. Kehadirannya di dunia ini membuat negara-negara yang ingin berdaulat mengalami kesulitan menghadapi invasi ekonomi negara lain yang dibenarkan oleh sistem baru dunia yakni globalisme. Jika hal ini kita sandingkan dengan ketakutan kaum radikal di atas, kita bisa menemukan benang merahnya bahwa factor eknomilah pemicunya. Jika bukan factor ekonomi melainkan factor lain semisal agama, kenapa para teroris itu tidak menyerang Vatikan saja?
Point dua. Alasan diterjemahkannya buku ini ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul Saatnya Islam Bicara!, bisa kita pahami alasannya. Pertama, Indonesia adalah negara dengan peringkat satu dalam hal mayoritas penduduknya memeluk Islam. Itu berarti, survey Gallup dijalankan juga di negeri ini. Jadi, mungkin alas an teknis semata buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kedua. Sebagai negara bermayoritas pemeluk Islam, Indonesia mungkin merasa perlu turut rembuk dalam isu global soal Islam. Maka, penerjemahan buku ini bisa dipandang sebagai usaha melawan kesalahan pemahaman dunia atas Islam. Namun, jika kita kembalikan alasan ini pada catatan point pertama di atas, akan kita lihat kebodohan yang dimunculkan oleh usaha ini.
Dengan penduduk bermayoritas Islam—yang mengindikasikan sejarah islam yang bukan baru kemarin sore di negeri ini—harusnya kesalahan-kesalahan bodoh dalam hal pemahaman seperti itu tidak lagi terjadi. Kecuali kalau bangsa kita memang bangsa dengan ingatan yang cukup diragukan kemampuannya. Saatnya Islam Bicara! Adalah sesuatu yang tidak relefan menurut saya untuk negeri ini. Dengan toleransi yang dijunjung tinggi, harusnya masalah tidak saling memahami itu sudah dikubur lama sebelum Osama Bin Laden belajar membidik senapan.
Jika penerbitan buku ini adalah salah satu usaha Gallup mensosialisasikan survey mereka, itu soal lain. Tetapi jika sampai alasan ini pun mati di tengah begitu tertariknya orang Indonesia membaca buku ini karena mereka ingin tahu seperti apa sieh islam itu, ada baiknya kita semua saling memeriksa diri. Saya yakin, jika memang kita di negeri ini menjalankan toleransi, kita tidak akan tertarik untuk membaca buku ini karena kita sudah tahu, itu problem orang-orang yang belum menjalankan hidup toleransi di negaranya. Namun kenyataan bahwa kita masih perlu untuk membaca buku ini, itu mengindikasikan bahwa kita tidak toleran, maka sebaiknya dihentikan saja peringatan hari sumpah pemuda itu.
Inilah ujung jalan analisa kita. Rupa-rupanya, walau kita mendengungkan toleransi, kita sebenarnya menyimpan kebencian di dalam hati kita terhadap satu dengan yang lain. Kebencian ini timbul ketika kita menganggap agama dan kepercayaan sebagai satu-satunya pegangan dalam hidup ini. Ketika anggapan itu muncul, sejauh apa kita berusaha saling mengenal dan memahami, sejauh itu pula kita dengan diam-diam, setelah lelah berdialog di siang hari, malam harinya kita merenung di dalam kamar dan berkata kepada diri kita sendiri, “agama dia salah, agama saya yang benar.” Saatnya Islam Bicara! secara tak sadar sebenarnya membuka bobrok kita dan mengingatkan kita pada kepicikan kita dalam lindungan agama dan kepercayaan.
Data Buku :
Judul: Saatnya Muslim Bicara : Opini Umat Muslim tentang Islam, Barat, Kekerasan, HAM, dan Isu-isu Kontemporer Lainnya
Judul Asli: Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think
Penulis: Prof. John L. Esposito dan Dalia Mogahed
Penerjemah: Eva Y. Nukman
Penerbit: Mizan (Bandung, Agustus 2008)
Tebal: 249 hlm.
*Catatan: Tulisan ini dibuat dalam rangka mata kuliah Islamologi di STF Driyarkara pada 2010 – 2011.