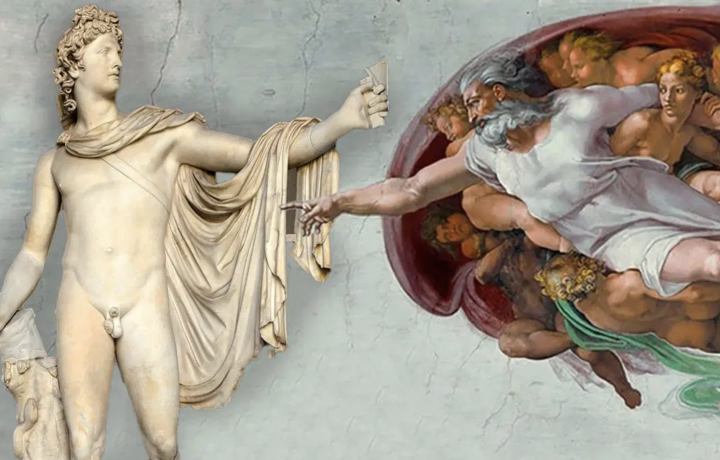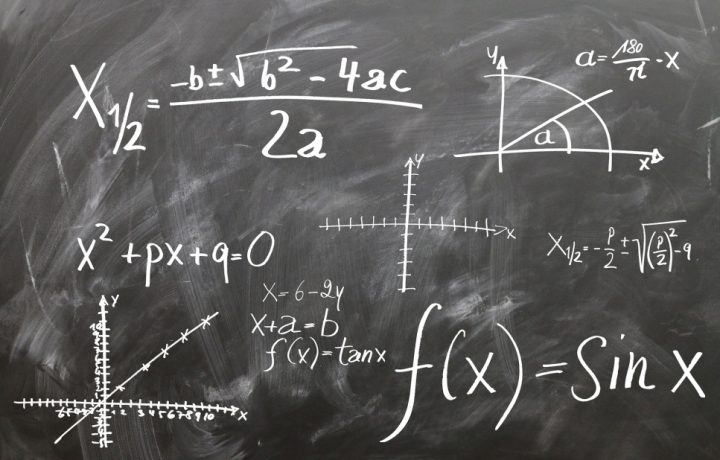Beberapa tahun belakangan, konsumsi kopi memang cukup meningkat dengan signifikan di tanah air. Bukan sekadar gerai kopi yang menyebar di pelbagai tempat hingga di pelosok-pelosok kota kabupaten saja yang menandai hal itu, pun pula pencarian pada pelbagai jenis kopi di Nusantara. Keuntungan dari negeri kita Indonesia ini memang keberagamannya. Keberagaman geografis dan juga keberagaman budaya. Dua hal ini sedikit banyak menjadi ciri penanda dari kopi-kopi di Indonesia, begitu juga Kopi Bajawa. Kita tahu, tanaman kopi akan berkembang sesuai dengan karakter tempat di mana ia ditanam, karakter geografis dan karakter budayanya. Keduanya itu sesungguhnya pula saling berhubungan. Demikianlah maka pada wilayah tertentu, kopi yang dihasilkan akan bercita rasa tertentu dan ini tentunya berbeda, meski pun juga punya karakter sama dengan kopi-kopi dari wilayah lain. Tentu saja kekhasan geografis yang beragam itulah penyebabnya. Di dalam konteks karakter budaya, penamaan pada sebuah jenis kopi memberikan sugesti yang berbeda pada konsumennya. Katakanlah, penamaan Kopi Bajawa membawa di dalam benak kebudayaan tanah Bajawa itu. Hal ini bahkan terjadi pada konsumen yang belum pernah sama sekali datang ke tanah Bajawa. Sang konsumen kopi itu setidaknya merasa ia mereguk sesuatu dari tanah yang jauh, meski ia belum ke sana. Barangkali hal ini mirip dengan perasaan orang-orang Eropa ketika menghirup aroma rempah meski pun belum pernah datang ke Hindia Belanda pada abad-abad yang silam.
Usia Kopi Bajawa sendiri, menurut beberapa sumber, tidak setua usia kolonialisme tersebut. Bahkan belum seusia Republik Indonesia. Adalah Matheus John Bey, Bupati Kabupaten Ngada periode 1978-1988-lah, orang paling berjasa di balik kehadiran Kopi Bajawa jenis Arabika yang terkenal itu kini. Pada 1977, ia mendatangkan bibit kopi dari Jawa untuk dibudidayakan di Kabupaten Ngada. Kopi ini lantas dibudidayakan di dua kecamatan yakni Golewa dan Bajawa, dua kecamatan yang ketinggiannya di atas 1.000 mdpl, cocok dengan sifat arabika. Sejak itu, kopi Bajawa jenis Arabika semakin meluas dan terus dibudidayakan secara telaten oleh masyarakat di Kabupaten Ngada. Pada sumber-sumber yang lain, kita mendapatkan informasi bahwa Kopi Bajawa menjadi terkenal semenjak film Ada Apa Dengan Cinta 2. Di dalam satu adegan film itu, Rangga dewasa yang baru pulang dari New York karena pada hari itu memang tak ada New York menemui Cinta yang tengah berlibur di Jogja bersama geng SMA-nya. Pada salah satu kedai kopi, dua pasangan cinta monyet masa SMA itu menyeruput kopi sambil saling berdiskusi.
Jadi demikianlah. Kehadiran Kopi Bajawa di Kabupaten Ngada terjadi lantaran inisiatif dari seorang pamong praja yang barangkali melihat potensi yang ada pada daerah tersebut. Sedangkan faktor yang membuatnya menjadi sangat populer didorong oleh kerja kebudayaan yakni sebuah film. Tentu saja bukan AADC 2 semata yang membuat remaja tanggung di Jakarta Selatan misalnya menyeruput Kopi Bajawa pada kencan pertamanya. Ada petani di Ngada yang begitu telaten mengerjakan kebun kopinya serta ada distributor-distributor yang mampu memastikan hasil panen kopi di Bajawa bisa tersaji dalam kemasan yang cantik di gerai-gerai kopi di Jakarta. Jika popularitas Kopi Bajawa akibat nongol sebentar di dalam film AADC 2 tidak diimbangi infrastruktur perdagangan Kopi Bajawa yang baik, maka sia-sialah semuanya itu. Ia hanya diingat bebebrapa hari saja setelah orang menyaksikan film itu dan lantas dilupakan. Beruntunglah bahwa kopi itu sudah tersedia di gerai-gerai seusai film itu muncul. Sehingga ingatan orang tentangnya bisa terjaga dan bahkan dipupuk terus menerus.
Hal yang diungkapkan di atas menunjukkan sebuah fenomena penting untuk kita. Bahwasanya pembangunan kebudayaan mestilah berjalan beriringan dengan pembangunan sektor lainnya sehingga mampu membawa kemaslahatan untuk banyak orang. Atau kerja-kerja kebudayaan mestilah juga jeli mengangkat potensi-potensi lain. Dengan begitu barulah kesejahteraan secara keseluruhan bisa menampak.

Bicara tentang kopi dan Flores, saya teringat larik dari seorang penyair, Djoko Saryono yang kira-kira jika diparafrasekan berbunyi demikian, ‘ketika kuminum seteguk kopi, sesungguhnya aku menghirup jejak kolonialisme.’ Tentu saja larik dari Djoko Saryono tidak setepat itu. Ketika membuat tulisan ini saya lupa meletakkan di mana buku kumpulan puisi beliau. Sudah coba saya cari tetapi tak bersua jua. Di mesin pencari google pun puisi yang saya maksudkan tidak saya jumpai. Namun demikian, mengapa larik puisi ini begitu melekat pada saya, tentu saja lantaran kebenaran yang teramat puitis, bukan puitisnya puisi tersebut, di balik kalimat itu. Kita barangkali jarang betul membayangkan kolonialisme ketika ngopi-ngopi cantik dengan para sahabat. Tetapi memang apa yang kita banggakan dengan kopi Indonesia tersebut adalah memang warisan Kolonial. Sejarah kopi di Indonesia mencatat bahwa pada tahun 1696 VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) mendarat di Jawa. Di dalam bawaan mereka yang begitu banyak, mereka juga membawa kopi dari Malabar, India, berjenis arabika. VOC lantas menanamnya di Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau-pulau lain di HIndia Belanda. Bahkan, kopi menjadi salah satu komoditas andalan untuk VOC. Ketika itu, tahun 1700-an, penjualan kopi dari Hindia Belanda begitu besarnya hingga ke Belanda pun memonopoli pasar kopi dunia pada waktu itu. Hingga di level dunia pun Pulau Jawa termasuk pusat produksi kopi. Hingga ketika itu secangkir kopi jadi populer dengan nama atau istilah a cup of Java.
Setali tiga uang dengan sejarah kopi, ketika kita menambahkan embel-embel Flores di belakang kopi, maka kita pun sesungguhnya berbenturan dengan suatu hal yang sama. Nama Flores sendiri bukanlah nama asli. Itu adalah nama yang muncul akibat kolonialisme pula. Nama asli dari Pulau Flores sendiri sebetulnya Nusa Nipa atau Pulau Ular. Nama Flores berasal dari bahasa Portugis, “cabo de flores” yang berarti “Tanjung Bunga”. Nama tersebut semula di berikan oleh S.M. Cabot untuk menyebut wilayah timur dari pulau Flores. Akhirnya dipakai secara resmi sejak tahun 1636 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu, Hendrik Brouwer, untuk menyebut pulau yang sekarang dikenal sebagai Pulai Florres itu.
Pada nama Kopi Flores – Bajawa dengan demikian kita sebetulnya secara berlebihan menunjukkan warisan dari kolonialisme kepada kita. Kopi itu sendiri adalah warisan kolonial dan nama pula tempat asal dari kopi yang dirujuk adalah nama yang diberikan oleh kolonial pula. Namun demikian, terlepas dari sejarah yang demikian adalah kemampuan kita untuk membalikkan warisan kolonial tersebut untuk kebutuhan dan kepentingan kita sendiri. Di dalam kasus Kopi Bajwa Flores sesungguhnya tampak pula upaya untuk ke luar dari jebakan kolonialisme itu. Kopi Bajawa Flores kini menjadi salah satu komoditi yang mengharumkan nama pulau berbentuk menyerupai ular tersebut.
Maka, sambil menyeruput Kopi Bajawa dari Flores, bersamaan dengan itu juga mari kita bertekat melestarikan sejarah budaya kita, melestarikan warisan-warisan yang ada pada kita, baik pewarisan dari sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif, tetapi yang utama adalah pemaknaan kita atasnya dan pemanfaatan kita atasnya di masa kini untuk kesejahteraan dan kehidupan hari ini.***
*Catatan: Tulisan ini dibuat pada 2019 untuk dipublikasikan di web diversity.id yang kini sudah tidak terbit lagi.