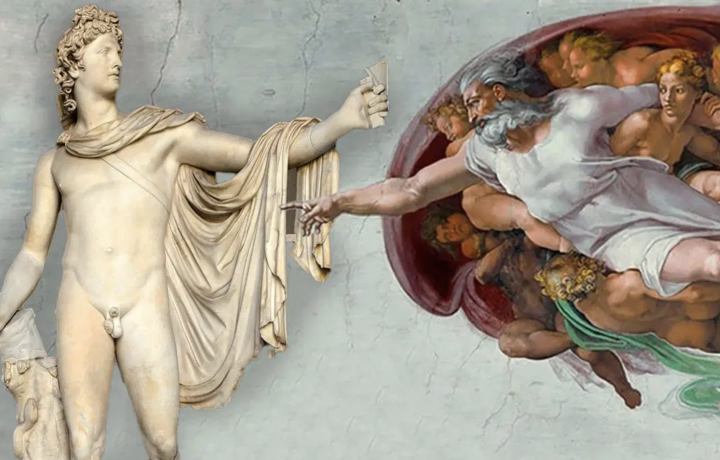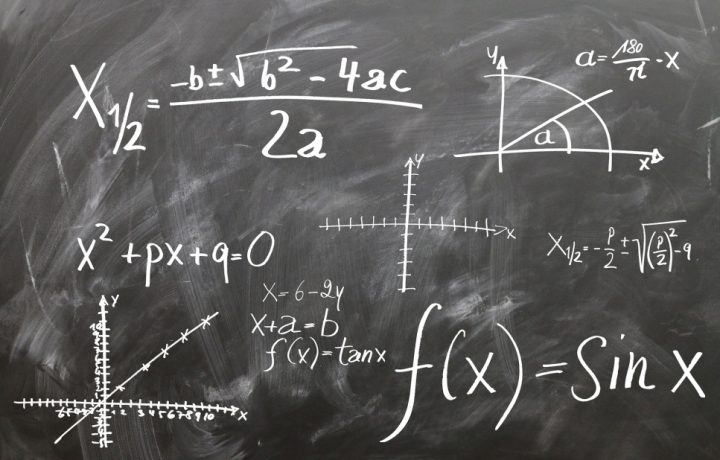BEBERAPA berita dan cerita dari kawan-kawan senasib sepenanggungan membuat saya berkesimpulan bahwa dari hari ke hari semakin sulit orang dari kelas bawah untuk naik tingkat kelas sosialnya. Tentu saja mereka yang ingin naik kelas ini tidak menggunakan frasa ‘naik kelas.’ Seringnya mereka menggunakan frase ‘mengubah nasib hidup’.
Sejauh pemahaman saya dan sejauh yang saya temui, cara untuk mengubah nasib ini tidak lain dan tidak bukan adalah pendidikan. ‘Supaya jadi orang’, demikian ungkapan harapan hasil dari pendidikan itu kita dengar. Dalam kasus kita, frasa ‘supaya jadi orang’ memang kerap digunakan sekadar kelakar. Tapi tidak demikian untuk pegawai rendahan atau petani atau nelayan atau buruh kasar atau satpam atau bahkan preman bayaran ormas di seantero negeri ini ketika mengucapkannya. Terselip harapan besar dan doa nan keras ketika menyebutnya. Ketika seorang ayah yang penghasilannya pas-pasan mati-matian bekerja demi menyekolahkan anaknya di bangku perguruan tinggi, harapan utamanya biasanya terwakilkan dengan ungkapan supaya sang anak ‘tidak hidup seperti orang tuanya.’
Bagi para orangtua ini, tentu saja yang penting anaknya kuliah. Kualitas kampus tempat anaknya menuntut ilmu atau sejauh apa sumbangsih jurusan yang diambil anaknya untuk masyarakat berada di nomor kesekian. Atau malah tidak dipikirkan sama sekali. Walhasil, ketika Dikti menonaktifkan ratusan kampus ‘abal-abal’ tahun lalu, pupus sudah harapan ‘mengubah nasib’ ribuan calon sarjana.
Dengan sedikit imajinasi a la sinetron, kita gampang membayangkan seorang ayah nun jauh di pelosok negeri ini lemes kaki tangannya, bisa jadi seketika terserang stroke ringan, ketika mendengar kabar itu. Betapa tidak. Dua tiga tahun banting tulang hanya agar anaknya bisa kuliah. Bukan di kota semetropolitan Jakarta ini tentu saja, tapi sekadar di kampus kecil di kota provinsi kecil. Itu saja sudah membuat keluarga itu berstrategi.
Misalnya si adik yang baru lulus SMA membantu ayahnya di kebun. Setelah sang kakak selesai kuliah, dia pun diharapkan mendapat pekerjaan supaya membantu biaya sang adik berkuliah. Dalam keadaan begitu, terdengar kabar bahwa kampus sang kakak adalah kampus abal-abal yang dinonaktifkan. Remuk redamlah usaha keluarga selama bertahun-tahun.
Bung dan Nona, derita dan getir masyarakat kecil itu adalah makanan sehari-hari. Mereka hidup, mengutip Walter Benjamin dalam state of emergency, dalam kondisi kedaruratan. Jadi Bung dan Nona, ada orang yang sudah tidak bisa lagi menitikkan air mata ketika tersiar kabar Irma Bule dipatuk ular. Ada orang yang tidak bisa lagi gusar ketika Ibu-ibu Kendeng membeton kakinya di depan Istana Negara. Tentu saja Anda berhak dan sewajarnya gusar ketika dua hal itu terjadi beberapa waktu lalu. Tapi poin saya adalah, sadarlah bahwa kegetiran itu terjadi setiap hari. Bukan karena rezim yang ini lebih jahat dan rezim yang sebelumnya seumpama neraka, tetapi memang sistem kapitalisme inilah biang keladinya.

Kita tentu saja sudah maklum akan kritik atas sistem pendidikan kita yang tidak seideal pendidikan untuk pembebasan a la Paulo Freire, misalnya. Kita pun maklum pada usaha-usaha membuat orang desa cinta akan ladang dan lautnya agar tidak capek-capek menjadi laron di kota-kota. Masalahnya, mereka bukannya tidak cinta pada ladang dan lautnya, tetapi bagaimana hal yang mereka cintai itu betul-betul memberi hasil bagi hidup mereka. Di sini kita akan bersua ketimpangan demi ketimpangan yang luar biasa kompleksnya; transportasi, pasar, sistem perumahan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
Di tengah ketimpangan itu, para pekerja kerah putih yang meningkat seiring birokratisasi dan juga kebutuhan kapitalisme memamerkan di muka pintu mereka bentuk hidup yang lebih sejahtera. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian pun mendapatkan maknanya yang baru. Tak apa generasi yang kini berkesusahan dan sulit hidupnya sebagai petani dan nelayan dengan penghasilan tak seberapa yang juga tak tentu, asalkan generasi berikutnya bisa bersenang-senang di kantor-kantor berpendingin daripada berpanas-panas di ladang dan laut. Manusia mana yang tak mau hidup lebih layak, tinggal di rumah-rumah yang lebih baik dan bekerja di tempat yang lebih nyaman?
Tentu cita-cita ‘mengubah nasib hidup’ dengan cara ‘naik kelas sosial’ bukan dosa. Wajar saja jika manusia berusaha mendapatkan hidup yang layak. Idealnya memang setiap wilayah, setiap profesi berhak untuk mendapatkan hidup yang layak. Namun apa daya, Indonesia bukanlah negara sosialis yang diandaikan memperhatikan hal-hal itu. Bahkan, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara-pun sejak ditetapkan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda keberadaannya yang nyata. Teranglah, problem ketimpangan ini menumpuk-numpuk. Pendidikan tadi misalnya, sejak dahulu hingga kini tetap dilihat sebagai senjata untuk ‘biar jadi orang’.
Barangkali memang tidak semua kasus bisa dipukul rata seperti itu. Bagi sebagian besar masyarakat Jakarta yang digusur dari pemukiman kumuh lantas dipindahkan ke rusun-rusun, ekosistem hidup mereka justru dihancurkan. Tetapi, bisa jadi untuk seorang preman kelas teri yang merantau ke Jakarta dan tinggal di pemukiman kumuh lantas dipindahkan ke rusun yang di matanya lebih layak dari rumahnya di kampung, itu keberuntungan. Cobalah piknik sejenak di sebuah kampung tanpa perlu pusing-pusing mencari wi–fi atau hotel standar; menginaplah di sebuah rumah biasa-biasa saja, jangan rumah kepala desa, dengan lantai yang sekadar disemen kasar dan kamar mandi yang berjarak beberapa meter dari rumah utama. Mungkin Anda akan merasa bahwa kos-kosan 3×3 m yang Anda tinggali di Jakarta tiba-tiba terasa begitu mewah. Tapi tentu juga tidak semua orang demikian.
*Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Rubrik OASE IndoPROGRESS, 24 April 2016.