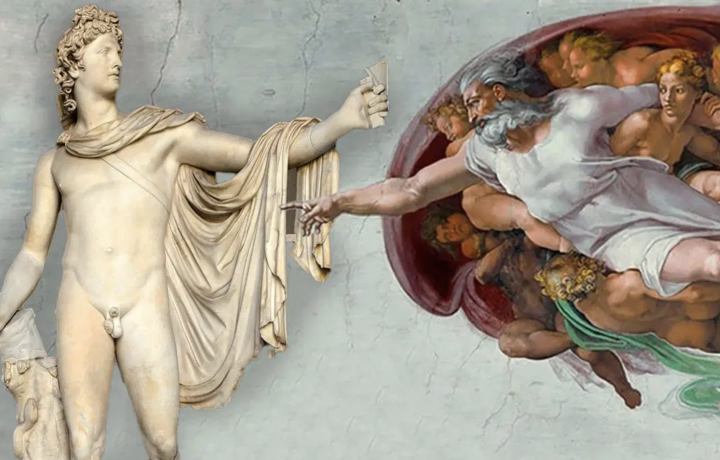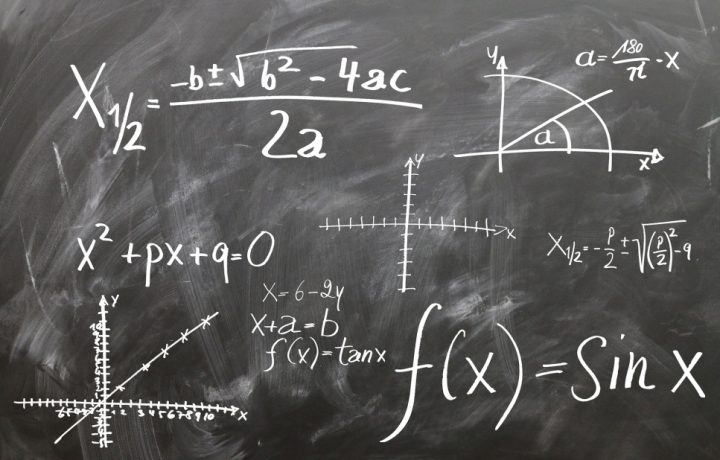Ini cerita dari beberapa kawan yang bukan siapa-siapa
I
SEBUT saja si Mamat. Dulu ketika kuliah di FIB UI, ia mahasiswa gahar yang selalu mengepalkan tinju kirinya ke udara. Jangan ditanya kaos-kaos yang dikenakannya; dari Tan Malaka hingga jalan lain ke Havana. Dari mulutnya yang kerap minta sebatang rokok itu pula saya pertama kali mendengar cerita-cerita partai kiri dan para pendekarnya. Saya menyimaknya bak membaca mitos. Betapa tidak. Partai, bagi saya kala itu, adalah spanduk-spanduk dan bendera-bendera yang kadang ramai memenuhi jalanan, plang nama bahkan di kota kecil saya di ujung Pulau Flores sana, hingga berita di koran-koran mainstream yang tertangkap mata sebelum serius membaca rubrik olahraga; atawa kaos-kaos oblong bersablon gampang luntur yang dikenakan petani dan nelayan di kampung-kampung.
Itu dulu. Mamat kini tak lagi gahar. Ia bekerja sebagai wartawan di perusahaan media besar. Lama tak bersua, kami ngopi bareng beberapa hari silam. Teringat kegaharannya masa lalu, saya menghakiminya perihal pilihan tempat kerjanya, juga cita-citanya dulu. Tentu dengan selipan jargon-jargon revolusioner yang membakar—dan tak lupa melabelinya ‘kelas menengah ngehek’. ‘Yah, aku mah apa atuh, teman,’ ujarnya mulai membela diri. Singkat cerita, ia memang pernah mencoba ‘tetap di jalur yang benar’. Tetapi tuntutan ibu yang makin tua, seiring kepergian ayahanda tak lama setelah kelulusannya, membuat Mamat harus banting setir. Ia menyebutnya ‘momen realistis’.
II
Akhir-akhir ini saya banyak meluangkan waktu untuk bertemu kawan lama ketimbang berasyik-masyuk dengan literatur seputar neoliberalisme. Selain Mamat, saya juga bersua Adit. Tentu di waktu dan tempat berbeda. Ia bekerja di kantor sebuah perusahaan Jepang. Penampilannya necis. Istilah kerennya, pekerja kerah putih. Berbeda dengan Mamat, Adit memang sudah necis sejak kuliah, sekitar sepuluh tahunan lalu. Ia juga jarang mengepalkan tangan ke udara; alih-alih kiri, kanan pun tidak. Ngobrol ke sana ke mari, Adit menyelipkan kesalnya perihal demonstrasi yang bikin dia telat sampai ke kantor. Tentu saja saya naik pitam.
Meski berteman cukup baik sejak dulu, kami kerap berselisih pendapat untuk hal-hal seperti ini. Saya heboh menghakimi: kamu asosial, kamu tak peduli pada masalah rakyat kecil. Usut punya usut, tempat kerja Adit mengerikan. Beberapa kali terlambat, saya lupa angka pasti yang ia sebutkan, ia bakalan menerima SP dari bosnya. Dan itu berarti pemotongan upah yang cukup signifikan. Bisa dipastikan, sendi-sendi kehidupan keluarganya—ia sudah menikah dan dikaruniai dua anak yang lucu-lucu—akan morat-marit untuk satu bulan ke depan. ‘Yah, gua mah apa atuh. Nggak berani juga demo kantor gua sendirian.’ Tentu saja saya masih punya segudang senjata untuk mendebat dia; mengurangi lauk-pauk selama sebulan tetapi tidak memaki demonstrasi buruh, misalnya.
III
Di kesempatan yang lain, saya bertemu kawan yang kini menjadi dosen di salah satu kampus swasta tak ternama di Jakarta. Dulu, ia kawan yang paling rajin mengajak saya ke acara-acara diskusi. Kebetulan ia bisa mengendarai motor dan saya tidak. Alhasil, saya kerap nebeng. Suatu ketika, saya mempromosikan beberapa diskusi yang akan diadakan dalam waktu dekat. Ia tak antusias. Katanya, tak ada yang baru dari diskusi di luar sana. Saya tentu saja tak setuju dengan pernyataannya itu. ‘Saya lebih suka berdiskusi dengan mahasiswa saya. Di kelas, saya putarkan Samin vs Semen dan meminta mereka menuliskan perihal film itu, lalu kita berdiskusi.’ Ia juga mendaku lebih suka menjalankan penelitian literatur secara independen, bukan untuk kampus tempatnya mengajar. Tentu saja seputar tema-tema lama yang sedari dulu kami sukai. Namun yah, katanya lagi, penelitian literatur mah apa atuh, tak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

IV
Berikut ini memang bukan kawan lama. Ia saya jumpai di sebuah layanan print on demand. Lazimnya mahasiswa dunia ketiga, saya kerap memanfaatkan situs penyedia ebook gratis dan jasa cetak digital. Nah, tokoh kita kali ini salah seorang operator komputer di tempat itu. Ketika saya menghampirinya, ia buru-buru ‘menutup’ aplikasi photoshop. Namun ia sudah berhasil menarik perhatian mata saya pada apa yang sedang dilakukannya di sana; menjukstaposisikan wajah Haji Lulung dengan Obama. Tentu saya tak berhasil tahu hasil akhirnya seperti apa. Saya, yang juga kerap bermain-main dengan photoshop dengan hasil yang sesekali bagus sesekali nggak, serasa mendapat teman. Namun apa daya, posisi sebagai pelanggan dan operator tidak memberi kesempatan berkenalan lebih jauh.
Bagi si operator, memproduksi meme adalah pengisi waktu mepet (bukan waktu senggang) antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan lainnya, dari melayani satu pelanggan ke pelanggan berikutnya. Tentu saja si operator tidak dibayar untuk membuat meme. Barangkali kalau ketahuan bos-nya, justru ia di-SP-kan. Adalah Si Macan Asia, jika Anda masih ingat, yang menuduh agen rahasia Korea Utara sebagai biang kerok air bah meme dirinya dan Hatta Rajasa pada pemilu presiden kemarin. Tapi yah, meme mah apa atuh—bukan seruan sungguh-sungguh untuk menghancurkan neoliberalisme hingga ke akar-akarnya—hanya bisa menciptakan senyum sesaat lantas hilang sudah, kembali pada realitas hidup yang menyebalkan.
V
Ketika sedang berusaha menyelesaikan tulisan ini, seorang kawan yang sedang berada di Papua mengirimkan pesan whatsapp berisi beberapa lelucon baru yang didapatkannya di sana. ‘Eh, Pak Pendeta. Saya bukan setan, cuma bekas Permesta saja.’ Itu salah satunya. Salah duanya, ‘Dokter tanya Mace Mince yang hamil, kenapa dia hamil terus. Apa dia tidak minum pil KB? Mace Mince langsung jawab Pa Dokter, ‘E Pa Dokter. Pil KB saya su minum. Tetapi waktu celana turun, pil KB itu sudah kering.’’ Ah, tetapi humor mah apa atuh. Hanya produksi ibu-ibu di pasar yang barangkali tak tamat SD.
VI
Ah ya, sebelum menutup tulisan ini, barangkali kita periksa sejenak perihal curhatan dan humor ini. Seringnya, orang lebih berkonsentrasi pada hal-hal nyata; yang materil sifatnya. Sesuatu yang keras, tampak nyata, dan menuntut kerja-kerja otot maha berani. Berdemonstrasi, turun ke masyarakat, mendampingi tuntutan upah, sampai pada penyatuan kekuatan gerakan untuk mendobrak pintu keras penguasa. Hal-hal mental kerapnya dipandang sebelah mata. Lelucon, tekad, keberanian, semangat, humor, dan juga ‘teori’ misalnya. Hal-hal ini oleh Walter Benjamin dianggap perlu diperhatikan dengan saksama karena hal-hal tersebut adalah juga produk dari kehidupan nyata yang berlangsung sejak lama. Ah, tapi semua itu mah apa atuh, kerjaan mereka-mereka yang tak bersentuhan langsung dengan massa.
* Tulisan ini sepenuhnya terinspirasi dari lagu Aku Mah Apa Atuh dari Cita Citata yang ada pada link di awal tulisan ini.
*Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Rubrik Oase IndoPROGRESS, 22 Maret 2015.