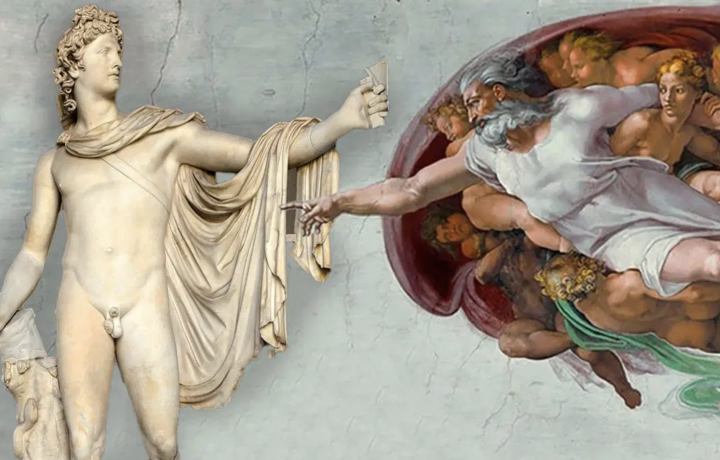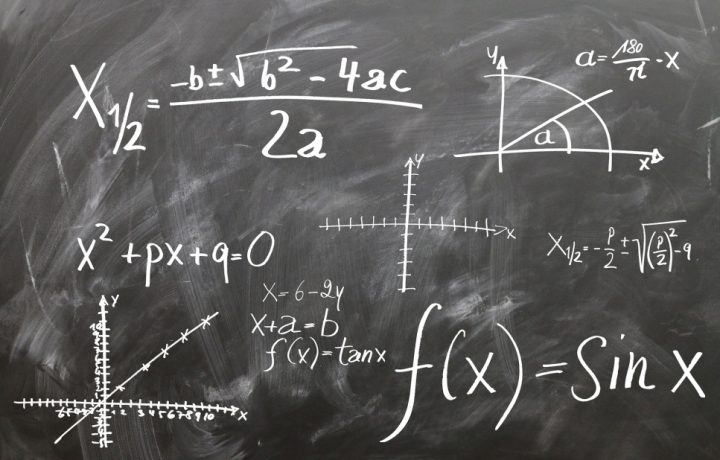MAAF, saya akan sedikit diskriminatif kali ini. Dari judul di atas, tentu Anda tahu, saya tidak membicarakan sebuah perihal yang bisa dipahami dengan begitu baik untuk Anda semua. Atau barangkali tidak semua Anda punya pengalaman dengan judul yang saya sebutkan di atas.
Jadi begini. 7-Eleven yang akan saya bicarakan ini memang baru ada di Jakarta. Kota-kota besar yang lain barangkali masih menunggu giliran untuk dikunjunginya. Di Jakarta, bisa dikatakan, 7-Eleven masuk ke sebuah kota yang sesungguhnya sudah punya hampir semua hal. Yang saya maksudkan bukan semata perihal fasilitas, tetapi juga strata sosial. Sebuah ilustrasi mungkin bisa menggambarkan hal itu. Cobalah sesekali, di malam minggu, Anda jalan-jalan di sekitaran Jalan Sudirman, Jakarta. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat mobil Ferrari, sepeda motor butut, sepeda kayuh, bahkan vespa yang dimodifikasi berbentuk pondok-pondokan di sawah, ada di atas satu ruas jalan yang sama di dalam radius sepenangkapan mata Anda. Dan Jakarta pun memungkinkan, seorang penulis yang saya lupa siapa, pernah menuliskan perihal ini dengan menarik: seseorang menyeruput kopi di sebuah gedung bertingkat dan ketika ia memandang ke bawah ia akan melihat seseorang yang lain sedang menyeruput kopi pula. Perbedaan antara keduanya adalah kopi yang ada di lantai ke sekian itu seharga setengah gaji orang yang sedang menyeruput kopi di bawah sana.
Itulah keistimewaan Jakarta. Tempat menghabiskan waktu senggang ada beraneka rupa. Dari yang bertemaram lampu romantis dengan harga kopi yang selangit, hingga sekadar di atas badan jembatan dengan modal rokok ketengan. Dalam keadaan kota yang demikian, 7-Eleven muncul. Ia menjelma malaikat penyelamat bagi sebagian, barangkali juga lebih dari separuh, penduduk Jakarta. Tak heran, toko klontong waralaba ini pun menjamur di Jakarta. Saking menjamurnya convenience store 24 jam asal Amerika ini, saya merasa seolah-olah jumlahnya hampir sebanyak Puskesmas. Bisa jadi malah lebih. Dalam satu kecamatan di Jakarta terkadang memang ada dua atau lebih 7-Eleven.

Pada pertengahan 2012 saja, 7-Eleven di Jakarta secara keseluruhan melayani 75.000 konsumen per hari. Sebuah angka yang menurut saya cukup fantastis. Bahkan, bagi siswa-siswi SMP, nongkrong di 7-Eleven itu sudah menjadi semacam gaya hidup. Tapi 7-Eleven tidak hanya menjadi mode untuk anak SMP ini. Di beberapa 7-Eleven tertentu, para pekerja kantoran memanfaatkannya juga untuk menghabiskan waktu atau menunggu macet reda.
7-Eleven sesungguhnya sekadar fenomena terbaru dari kenyataan Jakarta yang sudah ada sejak lama. Hilangnya ruang yang bisa dimanfaatkan masyarakat dengan leluasa bukanlah cerita baru. Rekreasi, sebagai sebuah aktivitas yang sangat penting, baik buat mereka pikirannya hanya mengejar keuntungan atau pun mereka yang berpikir dengan tujuan kemanusiaan di dalam selubung hatinya terdalam, menjadi sesuatu yang mahal di kota ini. Kehilangan ruang untuk rekreasi yang murah dan kalau bisa tak perlu bayar, tentu bikin berang semua kita. Caci maki pun bermunculan entah dari siapa saja. Yang paling sering kita dengar adalah tergerusnya ruang publik.
7-Eleven datang mengisi kekosongan itu. Ia muncul dari keresahan yang sama, tentu dalam level yang paling sederhana; tak ada ruang rekreasi untuk masyarakat Jakarta yang gundah gulana. Atau dengan sebuah pertanyaan, ‘kenapa tak diberi saja ruang tertentu bagi mereka yang berceceran bercengkrama di atas jembatan-jembatan dan warung kopi-warung kopi berbangku sempit itu?’ Lantas orang-orang pun datang bak laron ke tempat baru bernama 7-Eleven itu. Menikmati kursi-kursinya, menikmati lelampu sewarna ruang tunggu praktik dokter gigi. 7-Eleven dengan demikian mengumpulkan apa yang berceceran di jalanan, menempatkannya di satu tempat, dan mensentralisasinya. Ia bagaikan lampu-lampu yang menarik laron-laron yang selama ini bersembunyi di kegelapan. Ia boleh jadi merampok transkaksi-transaksi yang sebelumnya terjadi dalam kegelapan. Di lain pihak, ia pun memberi ruang baru, ruang yang lebih nyaman bagi mereka-mereka yang selama ini bersembunyi dan berceceran di tengah kegelapan.
7-Eleven hadir dan memberi sedikit jawaban atas ruang-ruang yang hilang. Ruang-ruang yang selama ini sebenarnya diresahkan dari semua orang. Keresahan itu dipandangnya sebagai kesempatan. Dan memang tak ada yang salah toh. Duduk, ngopi, berbincang-bincang, melepas sedikit penat, bahkan terkadang bekerja bukanlah sesuatu yang ada di luar manusia bukan? Sebuah keresahan menciptakan komoditas baru. Sedangkan yang resah kembali mendapatkan komoditas keresahan baru. Resah dan tinggal resah tanpa merebut ruang hanya akan tinggal dalam ratapan yang abadi..***
*Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Rubrik OASE IndoPROGRESS, 6 Oktober 2013.