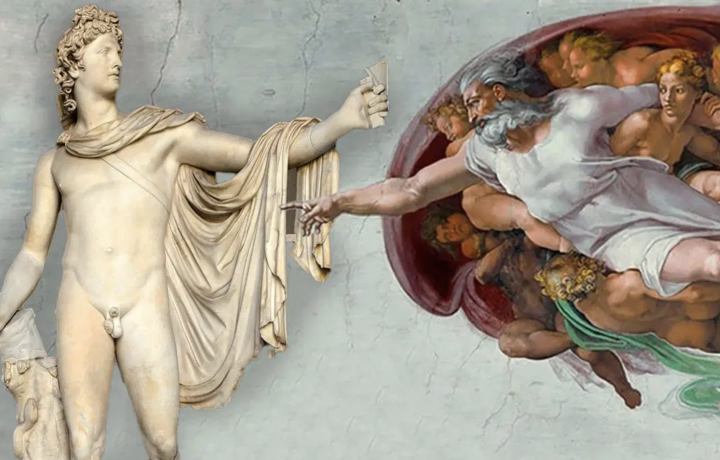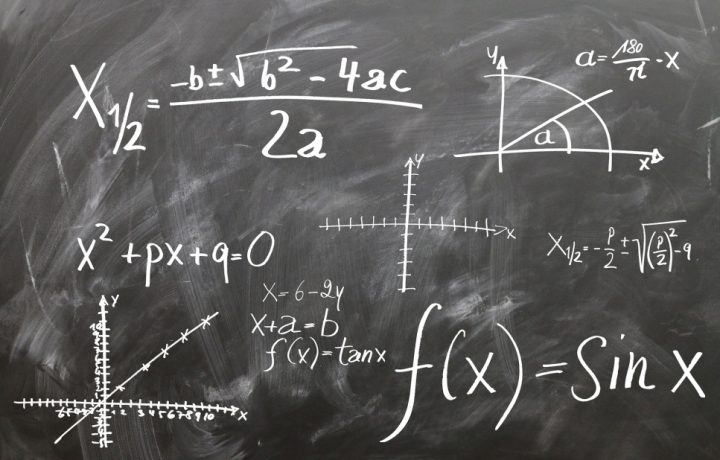PERINGATAN keras: hilangkan (Anda bebas menambah kata ‘sejenak’) segala caci maki dan stereotipe kita pada kelas menengah. Karena, saya kira, tulisan ini dibuat oleh seorang kelas menengah dan kebanyakan pembacanya adalah juga kelas menengah. Jika Anda dan saya adalah seorang mahasiswa atau pernah menjadi mahasiswa, sebuah kampus swasta paling ngehek sekali pun, apalagi pernah drop out dan lantas seenak jidatnya pindah ke kampus yang lain dengan harga per semester yang tak jauh berbeda, di situlah Anda dan saya ‘beruntung’ secara ekonomi.
Di situ kita menjadi berbeda dengan pemuda cungkring, si kelas bawah proletariat yang menyedihkan itu, tak tamat SMP, tak jelas juga kesehariannya diisi dengan kegiatan apa, dan sesekali cari uang rokok dengan ikut demo seharga 50 ribu + nasi kotak. Yang diksinya tentu jauh dari ‘waktu adalah fana/kita abadi’. Yang paling puitis untuknya bisa jadi hanya ‘es teh pahit saja/karena teteh sudah manis’. Kelas sosial yang kita bicarakan ini memang bukan datang dari ‘perasaan’, ‘identifikasi diri’, ‘politik identitas, ‘aliran yang dipilih penuh heroik’, atau ‘pengennya’ kita. Ia juga bukan hadir secara serta merta lantaran Marx dan Engels bersabda demikian. Ia merupakan penggolongan atas tingkat ekonomi dan segala macam tetek bengeknya. Tingkat ekonomi ini yang lantas membentuk segala jeroan di dalam diri hingga aroma air ludah yang diproduksi masing-masing orang. Oke. Kalimat sebelum kata ‘oke’ tadi berlebihan.
***
Dikotomi daerah dan pusat barangkali sudah tidak relevan benar dibicarakan saat ini. Di ranah sastra misalnya, perdebatan perihal ini sudah berakhir berdekade-dekade lampau. Namun, tentu saja, kita sadar sepenuhnya di dalam praktiknya, di segala bidang, dikotomi itu masih ada. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, hal itu tentu sangat relevan untuk dibicarakan. Dikotomi ini tentu saja bukan terberi dari langit. Ia dibentuk oleh sejarah panjang peradaban; perdagangan dan administratif kepemerintahan semenjak Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya hingga Jokowi dengan Revolusi Mentalnya.
Gerry van Klinken di dalam bukunya The Making of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota Kupang, 1930-an-1980-an memberi sebuah pandangan yang menarik, setidaknya untuk saya. Menurut van Klinken, di kota-kota periferi provinsilah justru Indonesia itu dibentuk. Di kota-kota yang jauh dari hingar percaturan politik a la Husni Thamrin di Voolkstrad atau pun Tiga Serangkai di Putera inilah keindonesiaan, sejak 1949 setidaknya, terus diuji. Indonesia ‘tak pernah gagal’ di dalam ujian itu lantaran peran yang dimainkan oleh kelas menengah di kota-kota provinsi tersebut. Mereka memainkan peran sebagai, “manusia broker (perantara) yang mampu secara pribadi menghubungkan satu sama lain jaringan-jaringan sosial yang terpisah-pisah dari sisi geografis di seluruh kepulauan itu” (van Klinken, 2015: 16).
Berbeda dengan golongan kelas menengah di wilayah pusat Indonesia, Jawa dan sebagian Sumatra, golongan kelas menengah di kota-kota provinsi, katakanlah daerah, muncul dari kaum tani yang mengalami kenaikan status sosialnya. Sedangkan sejawatnya di golongan masyarakat yang sama di kota-kota pusat lebih banyak berasal dari kaum feodal lama yang terus bertahan. Bukan berarti tidak ada satu pun yang berasal dari kaum tani.
Kita tentu perlu menyadari bahwa kenyataan ini bersamaan juga dengan persoalan perkembangan kapitalisme ‘yang tak merata’. Wilayah-wilayah yang lebih terbelakang pasti akan mendapatkan lirikan belakangan. Pendidikan, mengikuti perkembangan kapitalisme itu, pun setali tiga uang. Kaum priyayi di Jawa sudah mulai terbentuk di awal abad 20. Di daerah-daerah, baru belakangan menjadi lebih masif pendidikannya. Bersamaan dengan itu, kemunculan kelas menengahnya. Van Klinken, sebagaimana juga Bennedict Anderson, memandang positif kaum kelas menengah. Mereka-mereka yang berpendidikan, mampu ‘memainkan’ wacana yang nantinya memperjuangkan atau memunculkan ide perihal kemerdekaan. Tentu saja ini bukan satu-satunya alasan kehendak untuk merdeka dari kolonialisme. Ada begitu banyak keresahan di tengah masyarakat yang mendahului sungguh wacananya. Buktinya, Pemberontakan PKI 1920 itu.

Para kelas menengah ini mejadi broker dari pusat untuk berjuta-juta rakyat kelas bawah. Mereka menjaga keseimbangan antara penguasa pusat dan masyarakat-masyarakat kecil nan miskin di daerah-daerah. Yang sebagian besar tentu saja nelayan dan petani itu. Melalui kelas-kelas menengah provinsi inilah bantuan-bantuan dari pusat ke daerah disalurkan. Van Klinken mencatat Program Benteng di masa Soekarno dicanangkan setelah lepas pemberontakan PRRI-Permesta. Alhasil, ia merupakan program yang diberikan pemerintah pusat untuk mengurangi ketidak-sukaan daerah kepada pusat. Otonomi daerah pasca Orde Baru bisa pula dilihat dalam kerangka ‘Program Benteng’ model baru; upaya untuk meredam ‘kemungkinan’ gejolak-gejolak di daerah.
Tentu saja broker yang dimaksud di sini bukan bersifat negatif. Dari mereka, para broker ini merambah bercecabang: pertama, ide modernisasi, progresivitas, kekuatan kelas bawah, dan ide-ide baru yang mencengangkan lainnya. Tentu saja juga mereka menjadi broker untuk, kedua, kekuasaan status quo, pasar bebas, kepentingan-kepentingan ekonomi, dan hal-hal yang bikin terenyuh lainnya. Pembantaian pasca G30S 1965 mengena dengan telak juga pada kelas menengah di kota-kota provinsi. Mereka yang kalah, ini istilah dari van Klinken, adalah para broker jenis pertama di atas. Sedangkan yang menang, jenis kedua, tentu saja terus menjadi penghubung pusat dan daerah, menjadi penguasa di kota-kota provinsi, hingga hari ini.
***
Peran broker dari kelas menengah di kota-kota provinsi di atas tidak banyak berubah. Bahkan lebih menjadi-jadi lantaran Otonomi Daerah dan juga perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi kita. Ranah-ranah kehidupan lainnya, yang geliat-geliatnya muncul di hampir seluruh wilayah, pun adalah berkat mereka-mereka, kaum kelas menengah ini. Advokasi untuk kaum tani dan kaum nelayan, buruh migran, eknomi kreatif, pemberdayaan masyarakat adalah buah kerja kolaborasi kaum kelas menengah pusat dan kelas menengah di daerah-daerah. Ide-ide brilian dari pusat mendapatkan lapangannya dan bentuk konkretnya lewat kerja sama dengan kawan-kawan ‘sealiran dan sejalan pikiran’ di daerah-daerah. Demikian juga sebaliknya; ide-ide berdasarkan kebutuhan konkret di daerah-daerah mendapatkan jalan lapangnya berkat kolaborasi dengan kawan-kawan ‘sealiran dan sejalan pikiran’ di wilayah pusat.
Barangkali para pembaca sekalian pernah berada di dalam posisi ini di dalam konteks yang berbeda-beda; terkadang menjadi penghubung, terkadang menjadi yang membutuhkan penghubung. Sekali lagi, demikianlah Indonesia selama ini berjalan. Setidaknya menurut pemahaman saya atas temuan van Klinken. Orang Jakarta, dengan segala macam keperluannya selain sekadar piknik, memenuhi bandara Soekarno-Hatta, beterbangan menuju pelbagai penjuru Indonesia. Sesekali transit di kota-kota ramai, dan mendarat di kota-kota provinsi. Lagi-lagi, di seluruh Indonesia. Mereka bersua sesama kelas menengah di daerah yang ‘sealiran dan sejalan pikiran’. Orang-orang dari daerah memenuhi pesawat yang sama, tetapi dengan rute sebaliknya, datang ke Jakarta dan bertukar pikiran dan membicarakan sistem kerja dengan kelas menengah di Jakarta yang ‘sealiran dan sejalan pikiran’
Sekilas pandang, semuanya baik-baik saja. Namun terkadang, di antara mereka yang dari Soekarno-Hatta menuju daerah merasa membawa kebaikan yang tak terperi untuk orang-orang di daerah. Membawa sesuatu yang progresif untuk kemajuan daerah-daerah. Keberjarakan sejak di dalam pikiran ini berefek pada silaunya mata mereka-mereka di daerah. Ditambah lagi dengan ‘gaya hidup Jakarta si orang Jakarta’—yang disumbangkan juga oleh pandangan ‘orientalis’ mereka—ketika mereka berada sepenggal waktu di daerah. Silau itu tak terperikan. Apakah akan ada hal baik yang bisa muncul dari keberjarakan sejak di dalam pikiran serta efek silau yang ditimbulkannya? Tentu saja ada, tetapi tidak untuk semua pihak. Atau bisa juga manfaat yang sesaat saja ditimbulkannya. Selesai kunjungan, selesai pula manfaatnya. Tetapi jenis yang ini masih bisa dikatakan baik. Setidaknya, ada niat baik tetapi sudah salah sejak dari huruf pertamanya. Ada pula yang lebih menyedihkan dari itu. Tetapi, bukan tempatnya di tulisan ini.
Yang perlu kita perhatikan baik-baik dan belajar darinya adalah hubungan-hubungan ‘sealiran dan sejalan pikiran’ dari pusat dan daerah yang membangun kerja berkesinambungan, tanpa lelah, dengan efek yang tidak tampak mencolok tetapi perlahan-lahan dari hari ke hari. Dengan serius live in di tengah-tengah masyarakat, mendapatkan dirinya ternyata bodoh dan berbalik diberi pelajaran oleh masyarakat, dan lantas perlahan-lahan membuat metode kerja baru dari pertemuan-pertemuan itu. Kunjungan selesai, manfaatnya tidak langsung nampak, tetapi ada kegiatan-kegiatan berkesinambungan baru di tengah masyarakat sebagai jejak kunjungan yang singkat itu. Manfaatnya barangkali tidak seheboh merevisi undang-undang, tetapi ada perubahan kegiatan di keseharian masyarakat. Perubahan di dalam keseharian yang nantinya bisa jadi menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru.
Jadi, ketimbang mencaci-maki kelas menengah, mari kita cari bersama-sama contoh-contoh kerja yang demikian.***
Rawasari, 19-20 Maret 2015
*Catatan: Tulisan ini dipublikasikan pertama kali di Rubrik Oase IndoPROGRESS, 20 Maret 2016.