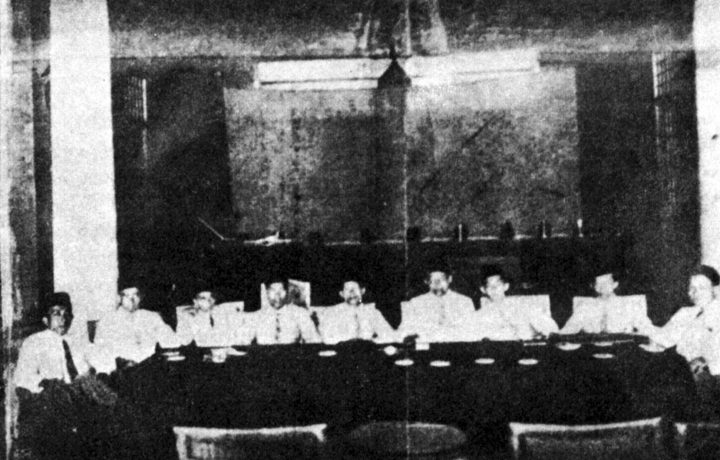Bagaimanakah kebebasan dan bagaimanakah pembatasan atas kebebasan itu? Di dalam konteks kebebasan berkesenian (berekspresi) pertanyaan itu tidak bisa tidak harus dilihat sebagai pertanyaan yang muncul dari pernikahan antara estetika dan etika. Estetika tentu saja urusannya dengan kesenian itu sendiri (dengan berbagai variannya tentu saja) dan etika urusannya dengan bagaimana sikap manusia dalam kerangka moral sebagai individu mau pun makhluk sosial. Di kerangka etika, kebebasan selalu berhubungan dengan tanggung jawab dan, dalam konteks pembicaraan kita ini, kebebasan punya batas-batasnya. Secara fisik manusia yang memang membatasi kebebasannya mau pun di dalam konteks manusia sebagai anggota dari masyarakat. Jadi, jika setuju dengan pendapat ini, tidak ada kebebasan yang absolut.
Masalah terakhir di ataslah, pembatasan kebebasan manusia lantaran manusia adalah anggota masyarakat, problem utama kita di dalam diskusi ini; ketidak-bebasan budaya (budaya yang harus dibebaskan dari segala pembatasan-TOR). Seni dan kesenian adalah produk budaya. Dan budaya adalah produk dari dan juga yang memproduksi adalah masyarakat itu sendiri. Posisi kebudayaan berjalan berbarengan dengan perkembangan masyarakat. Di dalam perkembangan masyarakat itu tentu saja tidak pernah lepas dari konflik (tesis-antitesis-sintesis). Dengan demikian juga kesenian sebagai garda depan kebudayaan itu. Konflik itu bahkan terjadi di dalam proses mencipta karya itu sendiri; kenapa memilih tema ini bukan yang itu, kenapa memilih bentuk dan media ini bukan bentuk dan media yang lainnya, kenapa memilih pemirsa yang ini dan bukan yang lainnya, dsb. Proses ‘kuratorial’ ini secara tidak disadari merupakan bagian atau mencerminkan ‘konflik-konflik’ itu tadi yang merupakan hasil penyerapan seniman atas keadaan masyarakat yang di dalamnya si seniman adalah salah satu bagiannya. Di sini tentu saja seniman tidak dipandang sebagai individu yang berbeda dengan anggota rnasyarakat lainnya atau individu yang punya kedudukan lebih tinggi dibandingkan anggota masyarakat lainnya. Kesenian, budaya dan masyarakat dengan demikian bersifat dialektis.
Nah konflik yang terjadi di aras internal penciptaan seni ini nantinya mewujud dengan lebih nyata ketika karya tersebut, atau fenomena kesenian tersebut, tampil di tengah masyarakat luas.
Di Indonesia akhir-akhir ini, apa yang kerap kita sebut sebagai pembatasan kebebasan berekspresi itu, saya kira adalah konflik ini. Apalagi, pasca reformasi, kekuasaan di dalam masyarakat, meminjam konsepsi Foucault, tidaklah tunggal sifatnya. Kekuasaan secara kecil-kecilan dan berserakan ada di mana-mana dengan penguasanya sendiri-sendiri. Fenomena ini bisa juga dilihat sebagai pemahaman yang begitu luas yang ditawarkan oleh reformasi mau pun upaya reclaiming terhadap apa-apa yang selama Orde Baru direpresi atau minimal berada di bawah kontrol Negara.

Maka tidak heran jika tiga hari lalu kita mendengar pembubaran acara kesenian dengan tema G30S 1965 misalnya dan lantas tiga hari lagi kita akan mendengar demonstrasi menentang pandangan islam tertentu di sebuah sekolah tinggi seni. Tentu saja masing-masing kita akan punya pandangan dan simpati berbeda atas kedua contoh kasus di atas; pertama mendukung dan lantas mengutuk mereka-mereka (bisa aparat atau masyarakat sendiri) yang melarang acara di kasus pertama dan kedua mendukung penolakan pandangan islam tertentu di kampus seni dan mengutuk mereka yang menyebarkan pandangan itu. Atau sebaliknya, atau varian lainnya. Permasalahannya adalah tadi; setiap anggota masyarakat berhak pula atas ruang publik dan ketika sesuatu hadir di ruang publik, dia akan berjumpa dengan beragam kepentingan itu. Bagi saya pribadi, pemberangusan akhir-akhir ini bukan perkara bahwa pemerintah yang tidak suka dan menggunakan tangan-tangan tertentu untuk memberangus, tetapi karena memang kekuasaan yang bersifat fragmentaris tadi dan juga pengetahuan serta latar ideologi yang berbeda-beda di aras masyarakat.
Bukan berarti saya mengamini bahwa kebenaran itu bersifat perspektif dan ada kebenaran di mana-mana. Tentu ada hal yang benar dan ada yang pseudo-benar. Tetapi untuk semua elemen masyarakat memahami itu tentu bukan pekerjaan gampang. Perlu waktu dan kesabaran untuk itu. Apalagi di tengah pendidikan yang begini-begini saja ini. Nah, di titik inilah tantangan para seniman dan pekerja kebudayaan; bagaimana dengan caranya memberikan pemahaman kepada masyarakat, sesama anggota masyarakatnya. Tentu perlu pemahaman atas masyarakat/pemirsa yang dihadapinya itu. Beberapa contoh bisa kita cari untuk usaha-usaha ke arah ini.
Sebuah kebudayaan (biar lebih gampang, kesenian) yang betul-betul bebas, melihat paparan di atas, saya kira jelas; tidak mungkin ada baik di pemerintahan saat ini, pemerintahan nanti, atau di belahan bumi mana pun. Permasalahannya, sifat kesenian itu yang dialektis. Tentu saja ini mengandaikan bahwa yang kita maksudkan adalah kesenian yang merupakan bagian dari produk masyarakat, bukan kesenian sebagai kesenian itu sendiri. Kesenian yang tidak bisa diceraikan dari masyarakat, bukan kesenian yang seolah-olah terpisah dan punya lahan perkembangan yang berbeda dengan lahan perkembangan masyarakat. Kecuali jika memang ada suatu kondisi masyarakat yang semua anggotanya punya pandangan yang sama, sikap yang sama, dan ideologi yang sama. Hal yang terakhir ini saya kira sangat rentan terjebak pada absolutisme – otoritarianisme.
Berbicara tentang keadaan kesenian yang terus berada dalam tegangan di tengah masyarakat yang juga selalu berada dalam tegangan ini, di dalam kasus Indonesia, akan terus terjadi. Dan bagi saya, justru tegangan-tegangan itulah yang membuat kesenian di Indonesia menarik. Indah kiranya melihat bagaimana seniman berhasil ‘menyusupkan’ ide pembaruan dan kritiknya di tengah masyarakat dengan form (bungkusan) yang soft, yang pada saat dipresentasikan misalnya, membuat masyarakat bergembira, tetapi bersamaan dengan itu juga pelan-pelan mengganggu pemahaman dan kesadaran masyarakat. Hal ini semenyenangkan melihat, referensi lama, tokoh Ali Topan yang keren; dikenal preman sekaligus kritis. Tentu saja keadaan ini butuh waktu yang lama untuk berubah. Di dalam konteks itu, keadaan kesenian sepuluh atau lima tahun ke depan saya kira masih akan tetap seperti ini. Sepuluh tahun bukan waktu yang lama. Pada 2005 misalnya, karya Agus Suwage dan Davy Linggar di CP Open Biennale ditutup akibat intervensi FPI. Hal serupa itu masih kita Iihat di 2016 ini. Tetapi pada tahun-tahun ke depan, saya kira kita akan semakin sering menemukan seniman dan kolektif seni yang benar-benar mengenal pemirsanya, bekerja bersama anggota masyarakat yang lain, dan dengan demikian memungkinkan untuk mereka ‘menyusupkan’ ide pembaruan dan kritiknya di tengah masyarakat; tanpa membuat masyarakat itu syhok, marah, dan atau membakar karya.***
Catatan: Tulisan lama, disampaikan pada diskusi Cultural Liberation yang diselenggarakan Departemen Kajian dan Aksi Strategis, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (Kastrat BEM FEB Ul), 30 September 2016 di Sunset Limited Cafe, Jakarta.