Nama Ariel Heryanto dalam kancah ilmu sosial budaya Indonesia, terkhusus cultural studies, tentu tak asing lagi. Karya terbarunya yang terjemahan bahasa Indonesianya baru diluncurkan, Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia, menegaskan hal itu.
Meskipun dinyatakan di awal buku bahwa buku ini akan membahas bagaimana generasi muda Indonesia merumuskan identitas mereka pada awal abad ke-21, apa yang kita temukan di buku ini bukan sekadar pembahasan perihal kekinian. Namun, kekinian itu dicari akar permasalahannya hingga jauh ke belakang, bahkan hingga masa sebelum kemerdekaan. Indonesia sebagai sebuah proyek yang belum selesai, menyitir Bennedict Anderson, benar-benar tampak pada buku ini.
Sebagai sebuah resensi, tulisan ini tentu saja punya keterbatasan untuk membahas semua hal yang menarik dan penting di dalam karya yang diterjemahkan dengan baik oleh Eric Sasono ini. Untuk itu, saya akan menspesifikasikan pembahasan ini pada hubungan budaya populer dan identitas serta budaya populer dan sejarah bangsa.
Satu hal yang perlu dipahami sedari awal adalah apa yang dimaksud dengan budaya layar di dalam buku Ariel Heryanto ini pertama-tama tidak hanya merujuk·pada film layar lebar semata. Melainkan merujuk pada semua media komunikasi yang menggunakan audiovisual. Karena itu, tidak heran jika buku ini merambah dati sutradara Nyai Dasimah, Lie Tek Swie, hingga kesuksesan gemilang Facebook di Pasar Indonesia.
Budaya Populer dan Identitas
Pembedaan antara seni rendah dan seni tinggi yang lantang dikumandangkan modernisme menyingkirkan budaya populer dari perbincangan akademis yang serius. Tak terasing dari panorama itu, studi tentang Indonesia pun setali tiga uang.
Padahal, mayoritas penduduk Indonesia begitu tergiur dan berperan aktif di dalam budaya populer (hlm 24-26). Alhasil, mayoritas akademisi tentang Indonesia terasing secara tak sengaja dari subjek yang sesungguhnya memengaruhi sebagian besar identitas manusia Indonesia itu. Panorama yang dernikian membuat Identitas dan Kenikmatan patut disambut dengan sukacita.
Jika kita masih melihat Pancasila, budaya nasional sebagai identitas bangsa, Heryanto dengan bukunya ini menunjukkan secara gamblang bahwa itu salah besar. Memang ada pengaruh kecil dari hal-hal yang demikian, namun identitas didominasi oleh pengaruh dari budaya populer.
Budaya populer, menurut Heryanto, perlu dipahami sebagai pelbagai, “… suara, gambar, dan pesan yang diproduksi secara massal dan komersial” dan juga “…berbagau bentuk praktik komunikasi lain yang bukan hasil industrialisasi, relatif independent, dan beredar dengan memanfaatkan berbagai forum dan peristiwa seperti acara keramaian public, parade, dan festival” (hlm 22.)
Identitas masyarakat Indonesia dengan demikian adalah sebuah perjalanan dialog yang Panjang antara kebudayaan lokalnya, agamanya, dan hal-hal yang “datang dari luar”. Seumpama budaya populer yang kerap dicap sebagai “budaya Barat” dengan konotasi negatifnya.
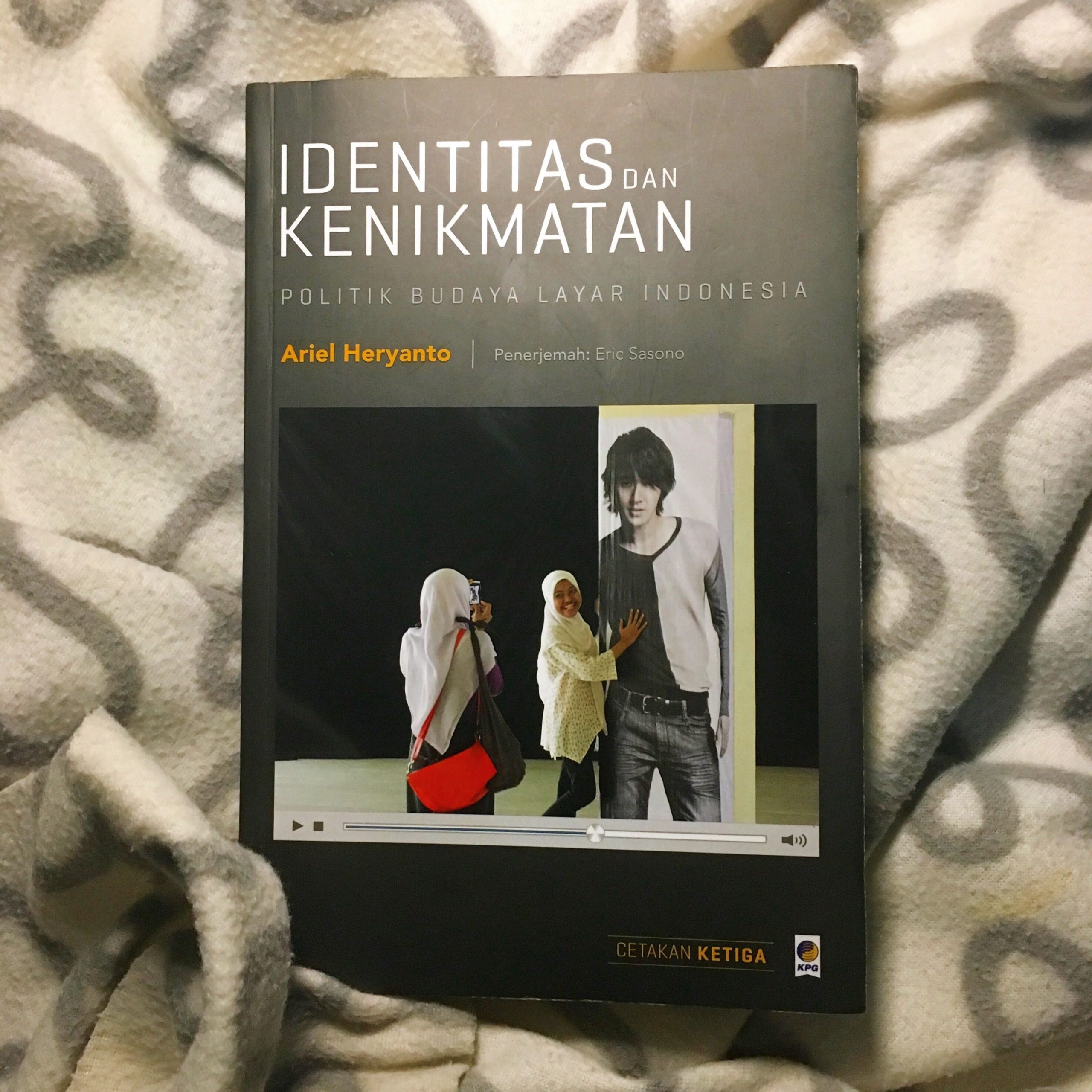
Heryanto menegaskan bahwa suka ataupun tidak, justru hal yang terakhir itu punya peran teramat besar. Perlu dicatat, tidak berarti masyarakat menerima begitu saja pesan dan muatan yang dibawa produk-produk budaya pop, penelitian lapangan yang juga menjadi bahan utama buku ini menunjukkan adanya pengubahan pesan oleh konsumen ketika menghadapinya.
Hal itu sebenamya bukan hal baru. Penelitian Ien Ang pada 1980-an tentang serial televisi Dallas sudah menunjukkan hal tersebut. Itu menjelaskan—sebagaimana secara panjang lebar diurai buku ini—bagaimana fenomena post-islamisme yang ditandai dengan kesalehan yang menyeruak di kalangan muda modern Indonesia berjalan berdampingan dengan penerimaan yang tinggi bahkan fantastis terhadap fenomena K-Pop.
Budaya Populer dan Yang Disingkirkan
Post-islamisme dan K-Pop membawa Heryanto menengok sejarah Indonesia. Secara tidak langsung, dua fenomena itu berutang pada dua hal yang disingkirkan seeara politis di Indonesia, yakni tradisi kiri (sosialisme, komunisme) dan identitas Tionghoa. Islam yang dibahas Heryanto di buku ini adalah Islam yang dibahas dari kacamata sosiologis, bukan teologis.
Pada hemat saya, simpati penulis buku sebenarnya terletak pada sekurelisme. Di Indonesia, dan di dunia pada umumnya, sekulerisme hampir dinyatakan gagal. Salah satu jawaban yang diberikan Heryanto atas kegagalan itu adalah tersingkimya kelompok kiri yang terdiri dari PKI serta partai dan organisasi nasionalis sekuler dan populis lainnya. Kita tahu, kelompok itulah yang juga terlibat dalam perdebatan seru perihal landasan negara, termasuk soal Piagam Jakarta.
Bersamaan dengan penyingkiran tradisi kiri, diskriminasi terhadap Tionghoa Indonesia tampak sebagai anomali di tengah kegandrungan akan K-Pop.
***
Ketika membicarakan budaya pop, budaya populer dan Islam, agaknya, perlu pula melihat fenomena di kalangan musik indie beberapa tahun terakhir. Yakni, munculnya band-band yang membawakan genre-genre music populer Barat, namun dengan muatan lirik serta niatan yang kental pada Islam.
Selain itu, fenomena beralihnya para praktisi dunia seni pop yang entah meninggalkan dunia tersebut demi keimanan mereka atau menggunakan popularitas mereka yang didapatkan pertama-tama melalui dunia seni pop tanpa embel-embel Islami menjadi alat untuk mengampanyekan keislaman mereka. Sayang, Heryanto lebih berkonsentrasi pada dunia budaya pop arus utama sehingga hal itu tak sempat dilihatnya.
Terlepas dari lubang kecil tak berarti di atas, buku Heryanto ini herisi beragam hal yang bisa memperkaya pemahaman kita akan Indonesia kini yang dibangun oleh sebuah sejarah panjang yang berliku-liku. Tapi, sebagaimana juga yang diakui penulisnya, buku ini pun punya kelemahan seperti lingkup penelitiannya yangterbatas pada Pulau Jawa semata.
Judul Buku: Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia
Penulis: Ariel Heryanto
Penerjemah: Eric Sasono
Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, Juni 2015
Tebal: 150+xviii halaman
*Catatan: Resensi buku ini pertama kali dipublikasikan di Harian Jawa Pos, 12 Juli 2015.




