
PANTAI TANPA PASIR
Akhir-akhir ini, perahu-perahu kami sering pulang dengan murung menggunung di bibir para lelakinya. Ikan-ikan tidak seramai dulu lagi. Matahari pagi mengkilat-kilatkan sisik beratus-ratus ikan yang dihamparkan begitu saja di pasir putih tak ada lagi kini. Perempuan-perempuan kampung berebut ikan tanpa keserakahan sambil saling melempar-lempar ikan satu dengan yang lainnya pun tak pernah tampak lagi. Malah sebaliknya, mereka mendatangi pantai dengan kantuk yang dipaksakan pergi, diam-diam mendekati perahu lelaki mereka dan memindahkan ikan-ikan di perut sampan ke baskom pelastik, pulang, syukur-syukur bisa terisi setengahnya.
Para lelaki kami tak jarang harus berlayar jauh ke tengah lautan, jauh terus ke tengah lautan, sampai lelampu dari pulau seberang yang dari bibir pantai kami tak terlihat sama sekali bisa terlihat. Lama-kelamaan, kepercayaan diri lelaki kami tak lagi sehebat dulu. Mereka sangat sensitif dan amarahnya bisa tersulut oleh masalah kecil saja. Caci maki dan bunyi benda-benda menubruk lantai mewarnai malam-malam di kampung kami.
Keluhan-keluhan di sana-sini dan bincang-bincang di tengah perut yang lapar akhirnya mencetuskan ide mengadakan upacara Pelipung Belitung. Seingat kami upacara ini terakhir dilakukan lima belas tahun yang lalu, ketika sepuluh ekor buaya putih secara serentak naik ke pantai kami bahkan berjalan terus sampai ke jalanan desa. Pelipung Belitung mungkin bisa melepaskan kami dari petaka ini; setidak-tidaknya sudah beberapa kali menurut cerita ia menjauhkan kampung ini dari masalah besar. Semua mulai tersenyum sedikit demi sedikit.
***
Adu pagi itu didatangi beberapa tetua kampung. Ewa, Gale, dan Simon. Ruang tamu rumah itu masih terlihat seperti pada enam tahun lalu, terakhir mereka ke situ. Kala itu, yang menyambut mereka adalah Nara, ayah Adu. Kali ini, Adu yang menemui mereka. Ayahnya sudah meninggal dau tahun lalu dengan sebuah pesan yang untuk Adu hanyalah igauan orang tua. Bukan. Bukan dia kurang ajar dengan ayahnya, tetapi apa yang dihidupi ayahnya sudah pupus kini bagi Adu.
Adu, anak lelaki satu-satunya Nara. Setelah selesai SMP di kampung halamannya, ia masuk Seminari. Suka cita dan muram durja menghinggapi keluarganya. Ella, ibunya, bersuka cita sedangkan Nara bermuram durja.
JEGRES
Aku tak punya rencana untuk datang ke Solo dalam bulan ini sebenarnya. Ke Solo untuk bertemu apalagi menjemputnya tak pernah terlinas dalam benakku. Yang terpikir dalam benakku tentang datang ke Solo adalah mengunjungi beberapa teman seniman yang sering berkorespondensi denganku via email atau facebook atau beranjang sana ke kosan temanku yang melanjutkan S2 musiknya di STSI.
Namun ikatan memang ada di mana-mana, begitu kata kekasihku pada suatu waktu tentang secuil ingatannya. Kekasihku itu punya masa lalu dengan Solo juga. Dia benar, pikirku. Karena ikatan ada di mana-mana inilah kedatanganku ke Solo untuk pertama kalinya ini tidak sesuai dengan bayanganku tentang kunjunganku ke Solo yang selama ini terbangun di kepala. Ini berhubungan dengan urusan keluarga besar dan saya terpaksa haruslah datang karena hanya saya yang mungkin untuk menjemputnya dibandingkan dengan keluarga besar yang ada di Jakarta. Terlalu rumit sekiranya bila harus kuuraikan perihal adat istiadat dan pertalian saudara yang menyebabkan saya yang mungkin untuk menjemputnya ini muncul. Aku seorang pencinta perjalanan. Namun perjalanan kali ini jauh dari menyenangkan.
Pukul sembilan pagi kereta ekonomi yang kutumpangi tiba di Stasiun Jegres, Solo. Ia sudah menunggu di sana. Itu kuketahui dari sms-nya yang masuk ketika Kereta Begawan tiba di Lempuyangan.
Wajahnya memang tak berubah dari imajinasi yang ada di kepalaku. Dia masih seperti dulu yang kukenal. Tapi yang berbeda, dia kini menggenggam tongkat sebagai penopang berdirinya. Aku langsung mengenalinya kembali ketika mata kami saling bersitatap. Hampir sepuluh tahun kami tak berjumpa.
Ia tak berubah.
Dari stasiun Jegres kami menaiki becak dengan ongkos 7.000 rupiah ke tempat saudara jauhku itu. Belum banyak yang kami perbincangkan, hanya saja sesuai rencana saya sudah mengatakan padanya bahwa sore ini juga kita akan kembali ke Jakarta.
Kami lantas tiba di tempatnya. Sebuah pusat rehabilitasi atau tepatnya Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa. Setelah tiba di pintu depannya, kami pun turun dan berjalan menuju asrama putranya. Saudaraku itu dengan nada bangga dan sedikit berterima kasih berkata bahwa tempat itu sungguh luas dengan segala fasilitas yang lengkap dari ruang kelas, ruang praktek macam-macam kemampuan, lapangan, kantin, aula, mushala, asrama putra, asrama putri, lapangan olahraga, bengkel, dan ini dan itu dan ini dan itu.
Cuaca mendung saat itu, bahkan gerimis turun sejak setengah jam sebelum masuk Lampuyangan tadi dan masih saja turun sebelum masuk Balapan. Tempat itu, di tangga-tangganya, lorong-lorong dari semennya, penuh dengan lumut. Sesekali, sandal jepit lily yang kupakai tak kuasa untuk tidak terpeleset di sana. Aku menangkap aroma kesia-siaan dan ketegaran dalam ketakbergunaan di tempat ini.
Ia mengajakku ke ruang tata usaha asrama putra. Ia hendak meminta ijin untukku yang akan berada di sana sampai petang nanti dan juga sekalian berpamitan dengan para petugas tata usaha di sana. Aku mengiakan sambil melempar puntung Djarum Super. Di dalam ruangan itu ada tiga orang. Seorang bapak dengan senyum yang selalu terkembang serta perawakan yang bersih serta rapih; jika anda mau membawa beliau ke dalam sinetron murahan, tipe ini cocok untuk tokoh sabar dan penuh pengertian serta mau berbuat baik untuk siapa saja. Dua yang lain adalah ibu-ibu berjilbab; tiga puluhan dan lima puluhan yang tak kalah murah senyumnya dan kita semua akan tahu dari raut muka mereka, mereka begitu pengertian dan begitu sabar dalam menangani hal-hal yang untuk kita sangat membosankan.
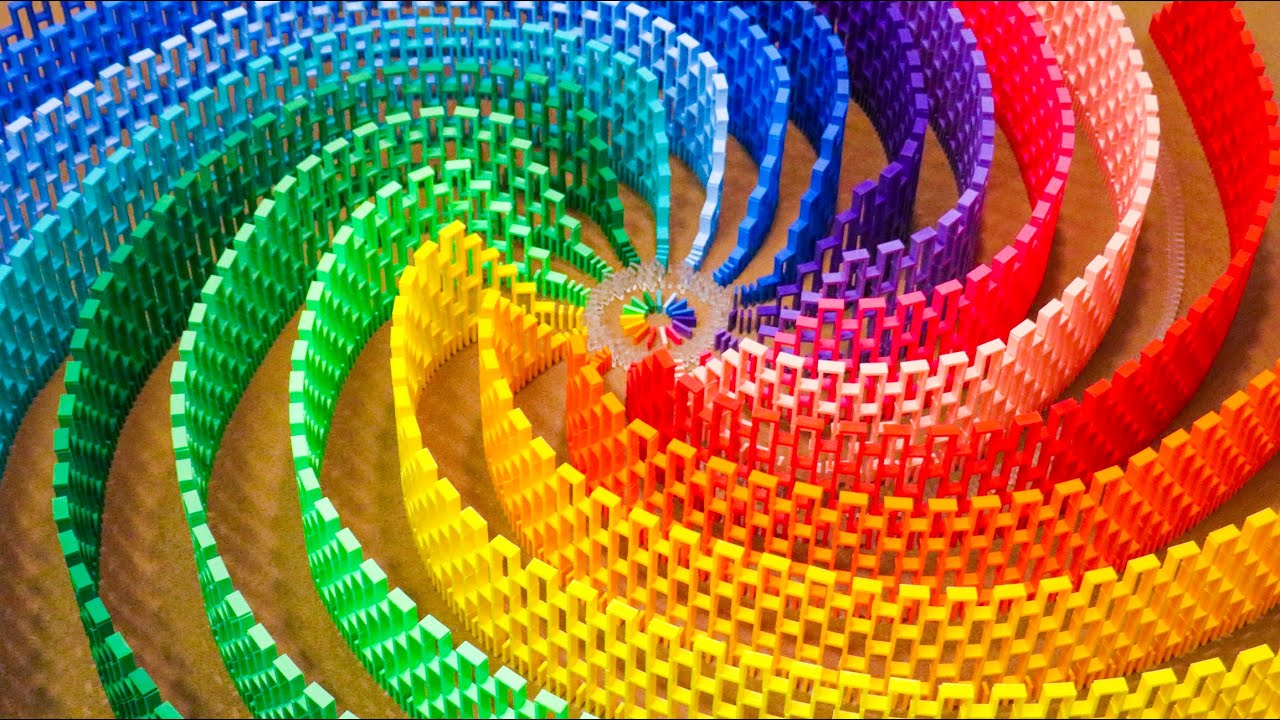
DOMINGGO, JANGAN KAU BERMURAM DURJA
Ini kisah tentang Dominggu atau Dominggus, terserah, terserah engkau lebih enak menyebutkannya seperti apa. Sebaiknya begini dulu. Kita memulainya dengan beberapa contoh untuk memperenak pendengaranmu dan juga penceritaanku. Pasti engkau pernah mendengar kisah-kisah tentang orang-orang hebat sepanjang sejarah kan? Nah, oh yah, mungkin bisa dengan contoh demikian; engkau mengenal Tan Malaka bukan? Atau mungkin lebih akrab untukmu, Kurt Cobain? Baiklah kita memulainya dari Cobain saja. Nah, Cobain bunuh diri di umurnya yang ke 27. Tapi, engkau pasti pernah mendengar rumor tentang sebenarnya Cobain tak bunuh diri tetapi yang mati itu adalah saudara kembarnya? Engkau tak tahu kan kalau ia punya saudara kembar? Nah, inilah yang suka kusebut dengan lapisan terbawah kenyataan yang butuh seorang tukang warta super iseng untuk mengungkapkannya. Si tua dari Argentina itu mungkin salah satu contohnya.
Atau mungkin Tan Malaka. Harusnya engkau tahu kalau ia meninggal di sekitar tahun 1949. Sebenarnya tidak sobat. Ia tidak mati saat itu. Ia baru meninggal beberapa tahun lalu, di tahun 1991, dalam usianya yang sudah teramat tua. Engkau boleh bertanya padak Pak Karmin tetangga kita dulu yang sempat menambil beberapa barang milik Tan. Tan Malaka meninggal dengan nama Tardi. Tak ada sisa-sisa Padang pada kematiannya itu. Sungguh benar-benar seorang Betawi tulen ia.
Begitu juga dengan kisah kehidupan Dominggo. Akirnya, aku menemukan bahwa sebaiknya kita memanggilnya dengan Dominggo saja ketimbang Dominggus. Selain karena itu mengingatkan kita pada masa pelayaran yang gemilang di masa lalu, kata itu pun membuat ia menjadi asing untuk masa kita kini. Aku tak tahu dengan pasti, apakah nama Dominggo-nya itu didapatkan dari seorang Padri Jesuit yang kebetulan dihanyutkan ombak ke pantai kami, ataukah dia sendiri yang memberi dirinya nama Dominggo. Mungkin Dominggo kecillah yang memberi namanya sendiri dengan Dominggo.
Agar cerita kita tak terlalu mengalir jauh ke mana-mana, sebaiknya kita percayai saja bahwa Dominggo adalah nama yang diberikan seorang Padri Jesuit kebangsaan Spanyol padanya. Ini lebih gampang sobat. Anda bisa membayangkan sebuah kapal Spanyol yang datang dari timur di antara Irian Jaya dan Philiphina, oleh karena angin dan mendung nan hebat yang menutupi penglihatan kapten kapal itu; kita harus menambahkan di sini bahwa kapten kapal sewaktu kapal itu meninggalkan Lisabon, bunuh diri ketika pelayaran mereka memasuki bulan ke delapan. Ada kisah yang menarik tentang bunuh dirinya sang kapten ini. Namun, kita akan menyimpannya untuk waktu yang lain.
Ketika Dominggo muda tengah duduk diam di tepi laut. Jauh di sana dilihatnya laut membentang. Ingin rasanya ia pergi jauh ke sana, mencari yang baru di sana.
Tiba-tiba dilihatnya sesuatu bagaikan kayu putih terapung di laut, terbawa arus ke barat. Ia lantas berenang ke sana. Dilihatnya di sana seorang perempuan dengan tangan yang menggapai-gapai meminta tolong. ***




