Baik senjata maupun tubuhku Adalah penyebab penderitaanku Oleh karena ia mengeluarkan senjata dan aku memiliki tubuh Kepada siapa aku harus marah?[1]
Tulisan ini akan saya mulai dengan kisah bagaimana saya akhirnya menulis tulisan ini. Ketika hendak menyiapkan tugas untuk mata kuliah lain, saya mengutak-atik perpustakaan pribadi milik paman saya. Dalam mencari bahan-bahan untuk tugas tersebut, saya menemukan buku berwarna orange dengan tulisan kecil di atasnya, “Sastra Suci Mahayana” dengan judul besar, BODHICHÂRYAVATÂRA. Tiba-tiba, saya langsung menentukan untuk mengangkat buku itu dalam tulisan saya untuk mata kuliah Filsafat Timur. Alasan pilihan itu adalah seperti yang dipercayai dalam Buddhisme bahwa tak ada yang kebetulan dalam hidup ini. ‘Kebetulan’ dipahami sebagai sebuah kelanjutan atau juga akibat dari hidup sebelumnya, sebuah keberlanjutan dalam lingkaran karma[3].
Dengan demikian, kini kita tahu, buku orange yang saya temukan tanpa sengaja itu adalah salah satu kitab dari salah satu aliran Buddhisme modern yakni Mahayana, lebih khusus lagi, sebuah aliran yang dikembangkan kemudian oleh Nagarajuna yakni Madhyamaka atau Fisafat Jalan Tengah. Selanjutnya dalam tulisan ini, kita akan coba, pertama, memaparkan Madhyamaka sebagai salah satu aliran Buddhisme dalam panorama Filsafat India. Kedua, akan sedikit diceritakan tentang Acharya Shântideva, setelah itu, ketiga, kita akan coba sedikit masuk ke dalam teks Bodhicharyâvatâra.

Dari Buddhisme sampai Madhyamaka
Membicarakan Buddhisme, Filsafat India, dalam lingkup sebuah studi filsafat modern, tentu kita tidak pernah bisa lepas dari distingsinya dengan filsafat barat. Padahal, secara simbolis, kata barat dan timur ini cukup bermasalah. Dalam studi-studi orientalisme dan postkolonialisme misalnya nilai rasa kata barat dan timur sungguh jauh berbeda. Barat identik dengan aroma glamour, kapitalis, kekayaan, sang angkuh nan serakah, humanis, laki-laki yang siap menundukan semua perempuan sedangkan timur identik dengan kesederhanaan, sang lugu yang dieksploitasi, kemiskinan, alamiah, perempuan cantik nan lugu yang siap ditundukan lelaki. Itulah peta Planet Bumi saat ini. Baiklah, kita tak akan masuk lebih jauh ke dalam permasalahan dialog antara keduanya; toh segala dialog yang pernah diupayakan tak jua merubah panorama itu[4].
Kebudayaan Timur atau Asia ditopang oleh antara lain Kebudayaan India dan Cina. Dari rahim Kebudayaan India inilah muncul Hinduisme yang nantinya juga ‘menentukan’ munculnya Buddhisme; pada awalnya adalah reaksi terhadap ritual-ritual Veda, seperti juga Jainisme[5]. Dalam perkembangannya, Buddhisme ini, setelah kematian Buddha, berkembang menjadi dua aliran besar yakni Hinayana (kendaraan kecil) dan Mahayana (kendaraan besar). Ada kesamaan-kesamaan dan perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan paling mencolok, bisa secara langsung dilihat pada penamaannya, adalah Hinayana menekankan pembebasan diri sendiri sedangkan Mahayana menekanan ke-Buddhaan bagi semua makhluk. Mahayana merupakan sebuah interpretasi yang terjadi belakangan terhadap Buddhisme. Interpretasi-interpretasi baru itu terjadi kira-kira antara 100 SM sampai 100 M[6]. Sedangkan menurut kronologi yang dibuat oleh Edward J. Thomas, Mahayana sudah mulai muncul pada abad kedua sebelum masehi[7].
Ajaran Mahayana bertujuan untuk mencapai idealisasi kehidupan Boddhisattva yang mana adalah orang yang sudah mencapai penerangan dan sudah berada di pintu masuk Nirvana namun ia tak memasukinya karena ingin menyelamatkan orang lain yang belum mencapai pencerahan. Pada poin ini kita melihat bagaimana Mahayana, sebagai sebuah interpretasi baru terhadap Buddhisme, ingin membawa Buddhisme tersebut sebagai keselamatan bagi semua orang; Buddhisme yang tidak ekslusif. Dengan kata lain, dengan Mahayana, Buddhisme dibuat lebih terbuka bagi banyak orang. Sifat keterbukaan ini terlihat juga pada keyakinan dalam Mahayana bahwa ada banyak Buddha. Mereka juga berpegang pada banyak kitab sebagai kitab utama, yang hadir setelah kanon Pali[8]. Mahayana ini terpecah lagi dalam dua aliran yakni Yogacara dan Madhyamaka. Yang terakhir didirikan oleh Nagarajuna dan diperkuat lagi oleh muridnya yang terkenal yaitu Aryadeva.
Nagarajuna termasuk tokoh besar dan penting peranannya dalam Filsafat India. Oleh para pengikut Madhyamaka, ia sering disebut juga sebagai Buddha Kedua[9]. Ciri pertama dari Filsafat Jalan Tengah ini adalah konsep sunya yakni konsep tentang kekosongan yang sekaligus juga sebagai kepenuhan. Sunyata atau kekosongan sebagai meditasi ini mengarah pada Prajnaparamita, sebuah kebijaksanaan yang sempurna atau kebijaksanaan transendental (ciri kedua). Ciri ketiga adalah konsep tentang tiga tubuh Sang Buddha yakni Dharmakaya (Sang Buddha yang universal dan transendental), Sambhogakaya (letak Sang Buddha atau Boddhisattva di alam lain atau surgawi), dan Nirmanakaya (tubuh Sang Buddha yang fisikly, historis). Ciri keempat adalah dokrin tentang dua model pengetahuan yakni kebenaran relatif (Samvrtti-satya) dan kebenaran absolut (Paramartha-satya). Tujuannya adalah mencapai kebenaran absolut ini.[10]
Nagarajuna sebagai pendiri aliran Madhyamaka semasa hidupnya menghasilkan banyak karya dan pengajaran-pengajaran. Oleh para Sarjana Buddhis Tibet, karya-karya Nagarajuna yang bukan termasuk dalam ajaran Tantra dibagi dalam tiga bagian yakni kitab-kitab analisa, kumpulan himne, dan risalah risalah yang lebih pendek. Salah satu kitab yang termasuk dalam kitab-kitab analisa itu adalah Madhyamakâvatâra; ayat-ayat tentang Madhyamaka dan berisi prinsip-prinsip filsafat Nagarajuna. Karya Acharya Shântideva, Bodhicharyâvatâra, adalah salah satu kitab dengan isi seperti Madhyamakâvatâra namun dengan bahasa yang puitis dan indah.[11] Maka, Acharya Shântideva merupakan seorang Bodhisattva Agung dan atas karya-karyanya, termasuk Bodhicharyâvatâra, dikenal sampai saat ini sebagai seorang Guru dari India sepanjang masa.
Sang Bodhisattva Agung; Acharya Shântideva (695-743 M)[12]
Acharya Shântideva lahir sebagai putra mahkota Maharaja Kushalavarmana dengan nama Pangeran Shantivarman. Dalam usia enam tahun, ia bertemu seorang Yogi dan mendapat pengajaran tentang sadhana Arya Manjushri. Ia mempraktekan pengajaran itu sampai Arya Manjushri sendiri menampakan diri padanya. Menjelang pengangkatannya sebagai raja, Arya Manjushri menampakkan diri dan berkata padanya, “Takhta ini milikku, karena aku gurumu. Tidak pantas bila kita duduk bersama dalam satu takhta.” Selain itu, Dewi Tara datang padanya dalam rupa ibunya dan berkata, “menjadi raja laksana air panas dari neraka, seperti itulah keadaan yang akan engkau masuki.”
Ia lantas meninggalkan kerajaannya sambil membawa pedang kayu yang merupakan simbol kebijaksanaan Arya Manjushri dan berangkat menuju Kerajaan Pancamasimha. Berkat kebijaksanaan dan kecakapannya, raja negeri itu menjadikannya sebagai salah satu menteri. Namun, akibat kecemburuan dari menteri lain, ia dicap sebagai penipu dengan alasan bahwa pedangnya adalah pedang kayu. Raja meminta ia membuktikannya. Shantivarman lantas mencabut pedangnya. Sang Raja yang melihat sinar terang dari pedang itu, copot matanya. Shantivarman mengembalikan keadaan mata raja seperti semula dan meninggalkan tempat itu menuju Nalanda. Sebelumnya ia memperingati raja untuk memerintah dengan mengikuti Dharma dan meminta raja untuk membangun dua puluh pusat Dharma.
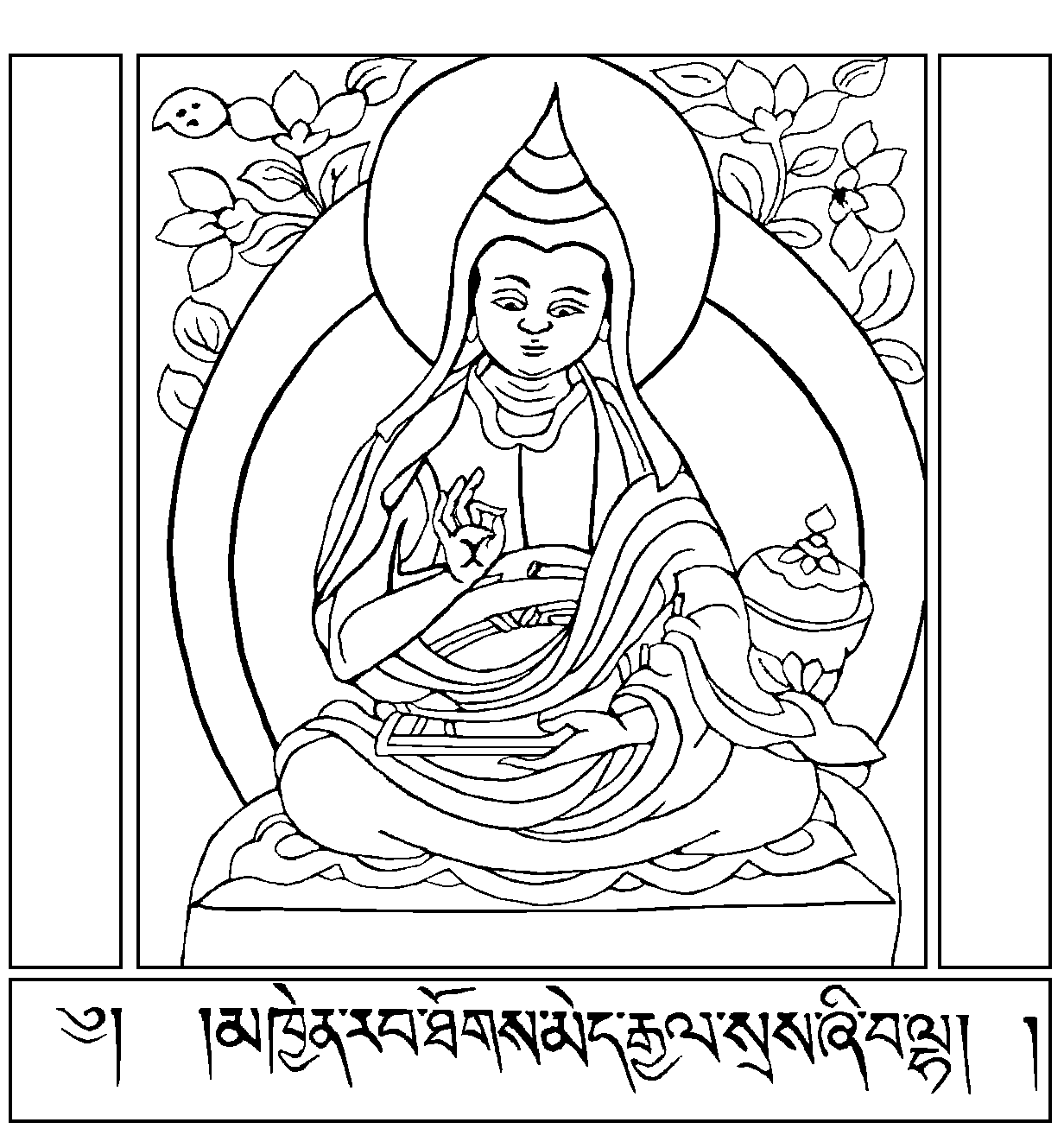
Di Vihara Nalanda ia memperoleh nama upasampada Shantiveda. Di sana ia belajar tentang pengajaran Arya Manjushri dan mencapai realisasi semua bagian terpenting baik sutra mau pun tantra. Orang biasa memandang Acharya Shântideva sebagai orang yang malas; makan nasi lima kali sehari, tidak bekerja, belajar mau pun meditasi. Mereka yang tidak suka padanya bermaksud mengusirnya dari vihara. Namun karena sangat sulit, mereka bermuslihat dan berencana menyuruh semua bhiksu untuk melafalkan sutra. Dengan maksud, ketika giliran Shântideva, ia tak bisa sehingga mereka bisa mengusirnya. Shântideva menolaknya tetapi karena didesak ia bersedia dengan syarat dibuatkan sebuah singgasana. Mereka membuat singgasana yang tinggi tanpa tangga agar Shântideva tidak dapat naik ke atasnya. Shântideva lantas menyentuh singgasana itu dan menekannya dengan kekuatan siddhi dan singgsana itu menjadi rendah dan ia duduk di atasnya.
Ia lantas bertanya pada semua yang hadir, apakah mau mendengarkan pengajaran yang sudah ada atau mau mendengarkan sesuatu yang belum pernah didengar? Mereka memilih yang kedua maka ia memulai pengajarannya tentang Bodhicharyâvatâra. Ia memulainya dengan kalimat, “…Aku bersujud kepada para Sugata dengan penuh rasa hormat, / Yang menyandang / Dharmakaya, / Demikian pula para Jinaputra yang mulia / Serta kepada semua yang pantas untuk dihormati.”
Ketika sampai pada bab kesembilan tentang prajna (kebijaksanaan) tentang sunyata (kekosongan meditasi) yang mendalam, ia terbang ke angkasa sampai tubuhnya tak terlihat namun suaranya terdengar jelas.
Berdiri di Gerbang Bodhicharyâvatâra
Mereka yang mendengarkan ajaran Shântideva dengan baik lantas mencatat ajarannya itu. Di kemudian hari muncullah beberapa versi dari Bodhicharyâvatâra yakni Versi Magadha (India Tengah), Versi Bengala, dan Versi Kashmir. Ketika beberapa pandita menemui Shântideva di Shri Daksina Kalingga (wilayah Trilingga), ia berkata bahwa Versi Magadha yang paling benar.
Bodhicharyâvatâra terdiri dari sepuluh bab. Diperuntukan bagi mereka yang menolak kebahagiaan samsara, menolah kenyamanan kedamaian pembebasan diri sendiri dan bersumpah membebaskan semua makhluk dari derita samsara dengan mencapai Kebuddhaan Yang Sempurna (Samyaksambodhi)[13].
Teks ini disampaikan dalam bentuk renungan meditasi pribadi yang diungkapkan bagi semua orang. Mengenai bentuk puisi dan bahasa puitik yang dipakai, Acharya Shântideva mengatakan, “… Aku tak memiliki kecakapan dalam seni puisi / Karena kurangnya perhatian bagi kebajikan makhluk lain / Aku menulis ini demi meresapkannya ke dalam batinku / sendiri (Bodhicharyâvatâra; Bab I ayat 2, hlm. 2.).
Seni puisi digunakan Shântideva bertujuan untuk perenungannya sendiri. Jadi, melalui bahasa puisi, teks renungan meditasinya diharapkan dapat direnunginya dengan baik. Bukan hanya utuk perenungan diri sendiri, teks ini pun diperuntukan bagi siapa saja yang dalam bahasa Shântideva, “yang sama beruntungnya dengan diriku, semoga ini berguna baginya” (Bodhicharyâvatâra; Bab I ayat 3, hlm. 3). Di sini kita melihat unsur dari Mahayana yakni keselamatan yang tidak diperuntukan bagi diri sendiri melainkan bagi semua makhluk; ia yang sudah di gerbang keselamatan kembali untuk menyelamatkan orang lain. Jadi, pertama-tama, kebahagiaan itu harus ditemukan sang diri sendiri, setelah itu barulah ia mengajak yang lain untuk masuk ke dalam kebahagiaan itu.
Dalam Bodhicharyâvatâra Bab I, kita menemukan suatu motivasi dasar dari Mahayana yakni membangkitkan bodhicitta (penerangan pikiran atau kebangkitan pikiran) yang bermuasal dari kehendak untuk menyelamatkan semua orang yang berada dalam samsara[14]. Dalam Bab I ayat 8-9, Acharya Shântideva berujar,
Mereka yang ingin menghancurkan berbagai penderitaan / keberadaannya dalam samsara / Mereka yang menginginkan (semua makhluk) memperoleh / berbagai kebahagiaan / Dan mereka yang ingin mengalami kebahagiaan / berlimpah-limpah / Seharusnya tidak mengabaikan bodhicitta. // Saat ketika bodhicitta bangkit / Pada mereka yang tak berdaya dan lemah di dalam penjara / samsara / Ia akan dipanggil sebagai Jinaputra / Di dunia ini ia akan dipuja baik oleh manusia maupun dewa. (Bodhicharyâvatâra, hlm. 3-4)
Terlihat di sini bagaimana sebuah motivasi menjadi seorang Bodhisattva; tujuan yang hendak dicapai aliran Mahayana. Jelas bahwa usaha untuk menyelamatkan orang lain atau semua makhluk dari penjara samsara, akan membuat seseorang dipuja manusia mau pun dewa. Pada ayat 10, dilanjutkan bahwa bodhicitta merupakan harta terbaik yang merubah tubuh kotor menjadi permata Buddha yang tiada tara.
Bodhicitta berusaha membangkitkan pikiran namun selain itu ia juga adalah pikiran yang dibangkitkan. Untuk memahami kedua hal ini, Shântideva menggunakan metafora kehendak untuk pergi dan kepergian itu sendiri (Bodhicharyâvatâra; Bab I ayat 15-16, hlm. 5). Pada ayat 24, terdapat suatu yang penting mengenai seorang Bodhisattva yakni ia harus memiliki kebajikannya terlebih dahulu untuk bisa membawa semua makhluk ke dalam kebajikan itu. Jadi, ia harus mengalami kebangkitan pikiran dahulu dan selanjutnya menjalankan pikiran yang dibangkitkan itu; ia harus memiliki keinginan untuk pergi terlebih dahulu sebelum pergi itu sendiri.
Pada ayat 36 Bab I yang merupakan ayat terakhir dari Bab I, Acharya Shântideva mengungkapkan sumber dari kebajikan bodhicitta itu yakni Tubuh Buddha sendiri,
Aku bersujud pada tubuh Dia / Di mana pikiran suci yang berharga telah lahir / Aku berlindung kepada sumber kesukacitaan itu / Yang membawa kebahagiaan bahkan pada mereka yang / telah menyakitinya
Di sini kita masuk pada tiga tubuh Sang Buddha yakni Dharmakaya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Sumber kebajikan itu adalah Tubuh Sang Buddha sendiri.

Demikianlah, kita sudah mencoba masuk pada pintu gerbang Bodhicharyâvatâra. Pada Bab I ini, tampak jelas sebuah ‘semangat’ dasar Mahayana dan Madhyamaka yakni adanya semangat menyelamatkan semua makhluk, membawa mereka semua pada Kebuddhaan. Di sini egoisme sungguh tak berlaku, karena bahkan seseorang yang sudah di pintu gerbang pencerahaan pun rela meninggalkannya demi menyelamatkan semua orang.
Penutup
Dari Hinduisme, lantas Buddhisme, lalu Nagarajunia melahirkan Madhyamaka. Madhyamaka sebagai sebuah ‘puncak’ filsafat India telah kita lihat salah satu ciri mendasarnya yakni semangat keselamatannya bagi semua makhluk, meski pun tentu saja tidak juga sesederhana itu. Bodhicharyâvatâra sebagai salah satu produk dari aliran ini, pada Bab I-nya, kita lihat sungguh menunjukkan ciri ini. Intinya adalah bahwa sebuah kehendak atas pencerahan pribadi yang memungkinkan adanya pencerahan bagi semua makhluk.
Membicarakan Filsafat India (dan juga Filsafat Timur pada umumnya), satu yang tak bisa kita lepaskan adalah keterkaitannya yang sangat dengan religiusitas. Maka, filsafat dan kepercayaan agama bisa berjalan beriringan dan berdampingan dalam Filsafat Timur. Ini sungguh berbeda dari Filsafat Barat yang memisahkan kedua hal itu. Maka, sosok seperti Acharya Shântideva dilihat dalam dua kaca mata ini; seorang Suci dan juga seorang filsuf.
Sesungguhnya, kita tentu tidak bisa berpanjang lebar ‘menganalisa’ filsafat yang dipaparkan Acharya Shântideva sampai sejauh ini (mengingat kita hanya berdiri di pintu gerbang Bodhicharyâvatâra). Satu yang patut diajukan di sini adalah, karena Bodhicharyâvatâra adalah sebuah petunjuk meditasi menuju Bodhiosattva, sesungguhnya cara yang terbaik untuk membaca dan memasuki sari patinya adalah dengan membaca dan merenungkannya serta mempraktikannya dalam kesunyian jiwa kita. Sebab,
Sementara kita mungkin bisa mengambil batang pisang— / Memotong seratnya, tak akan menemukan apa pun. / Demikianlah pula analisa penyelidikan / Akan menemukan tiadanya ‘aku’ tidak berada dalam diri. (Bodhicharyâvatâra; Bab IX ayat 74, hlm. 139)
Daftar Pustaka
Ali, Dr. Matius, Filsafat Asia-Selatan: Sebuah Pengantar Hinduisme dan Buddhisme, diktat kuliah STF Driyarkara, Jakarta, 2010.
Brata, Suwandi Sandiwan, “Essensi Budhisme”, dalam: Tim Redaksi Driyarkara (peny.), Jelajah Hakikat Pemikiran Timur, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
Keown, Damien, Buddhism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 1996.
Priyono, Herry, “Nilai Budaya Barat dan Timur Menuju Tata Hubungan Baru”, dalam: Tim Redaksi Driyarkara (peny.), Jelajah Hakikat Pemikiran Timur, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
Shântideva, Acharya, Bodhicharyâvatâra: Penuntun Jalan Hidup Bodhisattva, diterjemahkan oleh Upashaka Pandita Sumatijnana, Yayasan Bhumisambhara, Jakarta, 2002.
Sumatijnana, Upashaka Pandita, Mengenal Sang Buddha Serta Para Guru Penerusnya, Yayasan Bhumisambhara, Jakarta, 2002.
Thomas, Edward J., History of Buddhist Thought, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 2004.
Williams, Paul, Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations, Second Edition, Routledge, Oxon, 2009.
[1] Acharya Shântideva, Bodhicharyâvatâra:Penuntun Jalan Hidup Bodhisattva, diterjemahkan oleh Upashaka Pandita Sumatijnana, (Jakarta: Yayasan Bhumisambhara), 2002, hlm. 62. Kutipan atas teks Bodhicharyâvatâra dalam tulisan ini selanjutnya merujuk ke pada buku ini.
[2] Edward J. Thomas, History of Buddhist Thought, (New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2004, hlm. 189.
[3] Upashaka Pandita Sumatijnana, dalam bagian kata pengantar. Op cit, hlm. xvii.
[4] Untuk masalah dialog antara kedua budaya itu serta pokok yang menjadi penghayatan kedua budaya itu, bisa dibaca antara lain dalam tulisan Herry Priyono, Nilai Budaya Barat dan Timur Menuju Tata Hubungan Baru, dalam Tim Redaksi Driyarkara (peny.), Jelajah Hakikat Pemikiran Timur, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama), 1993, hlm. 3-14.
[5] Suwandi Sandiwan Brata, Essensi Budhisme, dalam, Ibid, hlm. 32.
[6] Damien Keown, Buddhism: A Very Short Introduction, (Oxford: Oxford University Press), 1996, hlm. 57.
[7] Edward J. Thomas, Op Cit. hlm. xv.
[8] Dr. Matius Ali, Filsafat Asia-Selatan: Sebuah Pengantar Hinduisme dan Buddhisme, diktat kuliah STF Driyarkara, Jakarta, 2010,hlm. 155 dan 158.
[9] Paul Williams, Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations, Second Edition, (Oxon: Routledge), 2009, hlm. 63.
[10] Dr. Matius Ali, Op cit, hlm. 173-175.
[11] Paul Williams, Op cit, hlm. 64-66.
[12] Bagian ini disarikan dari; Upashaka Pandita Sumatijnana, Mengenal Sang Buddha Serta Para Guru Penerusnya, (Jakarta: Yayasan Bhumisambhara), 2002, hlm. 180-185.
[13] Acharya Shântideva, Op cit, hlm. xix.
[14] Paul William, Op cit, hlm. 195.
Catatan: Tulisan ini dibuat dalam rangka kuliah Filsafat Timur I (Filsafat Asia Selatan) di STF Driyarkara, semester IV, tahun 2010. Mata kuliah ini diampuh oleh Dr. Matius Ali.




