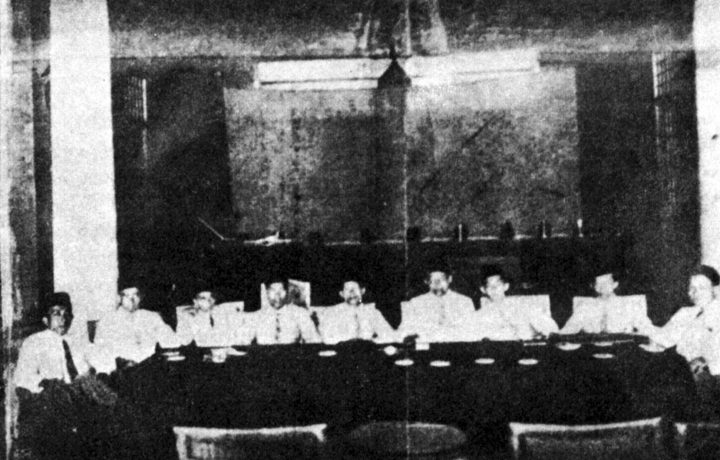Hampir setiap hari di layar RCTI, anda bisa menyaksikan sebuah reality-variety show dengan tajuk menjanjikan, Idola Cilik. Acara yang berpeserta anak-anak 7-12 tahun ini layak diperhatikan dalam rangka rencana KPI mengumumkan program televisi buruk April mendatang. Tulisan ini sekedar catatan kecil acara Idola Cilik itu.
Theodor Adorno dalam pandangannya tentang musik pop mengatakan, sekali pola musikal dan/atau lirikal ternyata sukses, ia dieksploitasi hingga kelelahan komersial. Pernyataan itu bisa diberlakukan juga pada idol-idol show di televisi Indonesia. Dimulai dari AFI di Indosiar, Indonesian Idol di RCTI, API di TPI, Idola Cilik di RCTI dan masih banyak lagi adalah acara-acara bertipe sama. Ketika bentuk acara ini berhasil menduduki rating teratas, menjamurlah acara-acara serupa.
Panggung Gemerlap Selebriti
Televisi kita ‘memberi jalan’ pada siapa saja untuk menjadi selebritis. Janji ini membuai masyarakat kita. Ini artinya, televisi telah memproduksi negative narcissism desire (Piliang, 2003), hasrat untuk diakui, dipuja, disanjung orang lain. Pengakuan kolektif atas individu ini dimungkinkan oleh gaya dan penampilan, image sebagai selebriti.
Televisi yang cengkramannya melampaui batas-batas teritorial ditonton di seluruh Indonesia oleh pemirsa yang hampir semuanya tidak kritis. Hasrat menjadi selebriti yang diproduksi televisi menjadi hasrat kolektif masyarakat kita. Lewat idol shom-idol show, televisi memberi jalan untuk hasrat ini diejawantahkan. Maka, berbondong-bondonglah calon selebriti dengan energi libido komunalnya berlomba menjadi selebriti.

Dengan cara kerja demikianlah, Idola Cilik memboyong anak-anak kota dan desa ke panggung gemerlapan selebriti. Anak-anak ini (khususnya anak desa) dicabut dari hidup tradisional agraris atau maritim lantas dijejali panggung gemerlap selebritis; jenis manusia ‘penting’—bahkan bedaknya dan restoran favoritnya pun ‘wajib’ kita ketahui—yang diciptakan televisi. Di saat yang sama, bangsa ini tengah menghadapi fase melemahnya sektor pertanian dan kelautan.
Anak-anak menyerahkan diri pada Idola Cilik untuk dipoles jadi hebat, jadi terkenal dan jadi sukses dalam waktu cepat. Dengan kata lain, anak-anak membiarkan dirinya menjadi boneka televisi, menjadi selebriti a la televisi yang bisa kapan saja dienyahkan dan diganti dengan yang baru. Lihatlah, betapa cara kerja mesin virtual ini menjadikan manusia sekedar komoditas yang habis manis sepah dibuang. Ironisnya, selebriti di televisi kita begitu mengamini kenyataan ini dan menganggap hal ini wajar saja. Betapa mereka merendahkan derajat kemanusiaan mereka di depan sebuah mesin virtual kapitalis.
Siapa tahu Indonesia ke depan tak lagi punya ilmuwan, pemikir, pekerja keras yang citranya mengabur dan posisinya tak ada di panggung televisi kita? Malahan, kita akan punya berjubelan artis-artis yang bukan lagi sibuk berlatih nyanyi atau akting, melainkan sibuk cerai sana-sini, gemar selingkuh kiri-kanan di televisi. Selebriti-selebriti yang berebutan cari sensasi demi tetap survive.
Mari Berkompetisi
Idola Cilik, sebagaimana idol-idol show lainnya, menerapkan metode kompetisi yang dibaluti varian-varian lain dalam acaranya. Kompetisi paling tidak punya dua kemungkinan; kalah dan menang. Pemenang akan bangga dan disanjung-sanjung, sedangkan sang kalah akan terpuruk dan merasa diri tak mampu. Seluhur dan semulia apa pun tujuan sebuah kompetisi itu, ia tetap bermasalah. Bahkan dari pandangan Everett Reimer, sekolah yang adalah juga ajang kompetisi itu pun menghasilkan hal serupa. Betapa menggenaskan nasib peserta Idola Cilik. Selain masa kanak mereka terampas bangku ‘kompetisi’ sekolah, mereka juga harus berkompetisi pula di Idola Cilik.
Disaksikan berjuta-juta anak Indonesia, berguguranlah mereka yang tak mampu, bersuara jelek, mereka yang tak mampu menjaring banyak SMS. Lihatlah di panggung Idola Cilik. Peserta yang di- just kalah kerap menangis tanpa dihampiri siapa pun, sedangkan yang menang akan dielu-elukan. Terlepas dari ini bisa saja ‘settingan’ demi menarik perhatian pemirsa, namun membiasakan anak-anak meratapi kekalahan adalah naif. Ada paling tidak dua kemungkinan pula ketika yang kalah menangisi kekalahannya; pertama dia akan bangkit dan berjanji akan tetap survive atau kedua, dia akan begitu mendendam pada situasi kekalahannya ditambah minder dan merasa diri tak mampu. Apa yang terjadi ketika itu? Dendam individual yang berpotensi menjadi dendam kolektif. Maka, janganlah heran bila kekerasan, kecemburuan, balas dendam akan terus terpelihara di Nusantara ini.

Idola Cilik bersama idol show-idol show lainnya menjelma kebutuhan manusia Indonesia, serentak menjamurnya televisi di seluruh pelosok negeri. Televisi kita yang perjalanannya dimulai pada 23 Oktober 1961itu, terasa seperti menyimpan bom waktu. Dari bersemangat menyebarkan pengetahuan, memperkokoh persatuan bangsa, hingga mencari keuntungan sebesar-besarnya, televisi mengkreasikan berbagai acara, salah satunya Idol Show Idola Cilik. Terlepas dari berbagai tujuan mulianya yang lain, Idol Show jelas-jelas mencari keuntungan dengan menjual anak-anak Indonesia. Pertanyaannya, apakah keuntungan itu harus beriringan dengan berkembangnya budaya instan, negative narcissism desire, suasan kompetisi yang menghancurkan jiwa anak Indonesia? Rupanya hal ini harus disikapi para stakeholder televisi, sehingga acara anak-anak di televisi bukanlah kotak Pandora yang membawa petaka untuk masa depan bangsa.
*Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Duirna, Jurnal Mahasiswa Komunikasi Unpad (edisi kapannya, saya lupa tetapi kira-kira pada 2008 atau 2009). Lantas, dipublikasikan di blog pribadi saya sebelum ini, kecoamerah, pada 27 Oktober 2010.