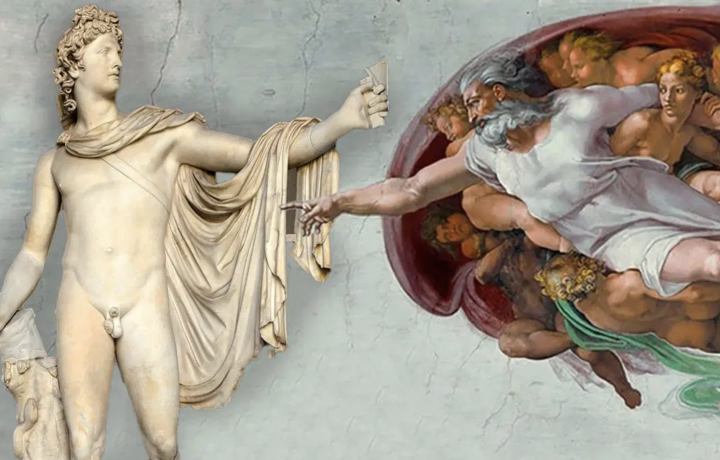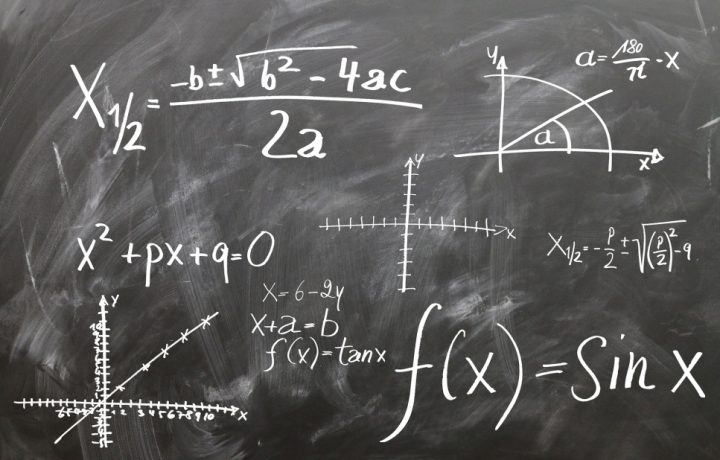Kali ini, saya mau berkisah tentang ikhwal percetakan. Perkara sejarah percetakan, tentu kita semua pernah mendengarnya. Sejak orang Cina menggunakan perkakas tanah liat untuk mencetak aksara hingga Gutenberg menggunakan plat baja, sampai percetakan yang diimpor dari Eropa pertama kali ke Nusantara untuk memenuhi kebutuhan Gereja. Lantas, orang-orang Tionghoa-Nusantara menggunakannya pula untuk mencetak koran-koran berbahasa melayu pasar; sebuah tindakan yang memungkinkan tercetusnya rasa nasionalisme di hari-hari selanjutnya.
Deru mesin dan aktivitas orang-orang percetakan ini bisa Anda jumpai di deretan rumah toko di sekitaran jalan Pramuka Raya, perbatasan antara Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Toko kertas, percetakan dengan beraneka rupa mesin cetak dan ukurannya, toko khusus penyuntigan dan tata letak serta pencetakan film, hingga jasa lem panas, dan jasa pembungkusan buku dengan plastik tipis ada berjejer di tempat itu. Lori menghantarkan kertas, mobil boks menjemput buku-buku, bunyi mesin cetak yang khas dengan aroma—entah tinta, entah lem—yang juga khas, hingga denting pisau besar yang memotong kertas. Ini hanya beberapa hal saja yang sempat saya ingat; jika ingin melengkapinya, kita butuh paling tidak sepuluh sampai lima belas kalimat lagi.
Mendadak saya teringat sebuah mata kuliah dan buku pegangannya di tahun-tahun yang telah berlalu: Sosiologi Sastra. Menurut kuliah itu, ada empat hal yang mewarnai sastra, pengarang, penerbit, pembaca/pasar, dan kritikus. Percetakan rupanya dimasukkan dalam entri penerbitan. Sesungguhnya tidak demikian. Sebut saja sebuah masalah yang dihadapi Penerbit Padasan, Jakarta beberapa waktu lalu. Tiba-tiba saja, buku terbitannya beredar di pasaran dengan harga sangat miring. Orang menduga, percetakannya bermain sapi. Karena itu, dalam sebuah bincang-bincang santai, kawan saya bersikeras membedakan ikhwal penerbitan dan percetakan. Keduanya adalah dua disiplin kerja yang berbeda. Dengan kata lain, masih menurutnya, industri rumahan. ‘Bayangkan! Untuk buku aja—si jendela ilmu pengetahuan itu—kita di Indonesia ini masih industri rumahan lho. Bagaimana bisa membicarakan laboratorium ruang angkasa?’ demikian cibirnya. Tentu saya tak mau kehilangan muka. Saya contohkan padanya Penerbit Gramedia yang lengkap dari hulu ke hilir dalam hal penerbitan dan percetakan.
***
Beginilah yang terjadi di Jalan Pramuka itu; satu percetakan sudah pasti mencetak buku dari berbagai macam penerbitan. Bisa jadi, penerbitan itu beralamat di Pontianak, Kupang, atau Jakarta sendiri dengan jenis-jenis buku yang beragam pula. Entah buku pelajaran, resep masakan padang, biografi seorang bupati di sebuah kabupaten di Kalimantan, buku doa, kumpulan puisi seorang penyair muda, dan sebagainya. Jangan ditanya sticker, spanduk, brosur, dan hal-hal sejenis; dari sticker menuntut turunnya SBY hingga sticker promosi sebuah rumah makan China di daerah Jakarta Pusat. Beragam buku, beragam pengetahuan menemukan bentuk materialnya lewat tangan-tangan operator mesin cetak, yang bisa jadi salah satu di antaranya tidak tamat Sekolah Menengah Pertama.
Di tangan sang operator mesin cetak dan bosnya ini, tak ada diskriminasi untuk setiap buku yang mereka kerjakan. Segala jenis buku harus mengantri, tak peduli apakah itu buku resep masakan atau buku teori politik yang konon mampu membawa negara ini ke luar dari centang-perenang perpolitikannya; tak peduli penulisnya doktor dari universitas google atau doktor lulusan universitas Harvard. Penulis yang sudah langganan penghargaan sastra seperti Ayu Utami pun diperlakukan sama dengan buku kumpulan puisi sang penyair muda. Semua diperlakukan berdasarkan perkara teknis yang tak kasat mata untuk percetakan: jenis kertas, ukuran dan tebal, serta jumlah eksemplar jadi yang diminta.
Di percetakan, isi buku juga tak bermakna. Sang doktor luar negeri yang harus membaca puluhan buku teori politik dan menulisnya banting-tulang, tak akan mendapat ‘belas kasihan’ atau ‘salut hormat’ dari percetakan. Kedoktorannya tak membuat harga cetak bukunya lebih murah atau lebih mahal atau lebih diprioritaskan waktu cetaknya dari buku resep masakan tulisan sarjana Google. Jika perkara teknisnya sama, maka sebuah majalah berisi ide-ide progresif nan heroik pun pasti setara posisinya dengan selebaran harga barang-barang Alfamart.
Namun jika percetakan sedikit bergolak, harga kertas yang tiba-tiba melonjak misalnya, semua penerbitan untuk buku jenis apa pun pastinya kalang kabut. Jika saya tak salah ingat, Media Kerja Budaya pada sebuah nomornya pernah menurunkan permohonan maaf kepada pembaca karena terlambat terbit lantaran melonjaknya harga kertas. Perkara apa pun yang tertuang dalam setiap terbitanmu, engkau harus mampu membayar harga kertas-cum cetaknya. Kertas dan percetakan bahkan tak pernah bertanya niat baik apa di balik tulisanmu, kebergunaan untuk banyak orang sebesar apa yang akan ditimbulkan tulisanmu, atau seberapa orisinalnya tulisanmu. Sungguh, tak ada etika dan moral dalam perkara harga produksi. Tak ada pula perkara iman akan sesuatu ihwal yang dianggap lebih benar di mata percetakan.
Kini, jika kita pergi ke toko buku dan menemukan enam buku yang dibicarakan di atas diperlakukan tak sama, itu sudah di luar kendali percetakan. Buku resep masakan akan berada terselip di antara buku-buku sejenisnya. Nasibnya merana, menunggu waktu diobral tiga eksemplar dua puluh ribu. Sedangkan buku teori politik doktor luar negeri kita akan dicari banyak orang karena baru saja diresensi di harian ternama ibu kota minggu lalu. Buku Ayu Utami akan ditempatkan dengan penuh hormat pada posisi yang memungkinkan setiap orang yang masuk ke toko buku itu untuk melihatnya. Buku kumpulan puisi penyair debutan? Oh, barangkali sudah mendekam di gudang karena dua minggu dipajang di rak sastra pada pojok terpencil dalam toko buku itu, tapi tak satu pun dibeli orang. Majalah progresif kita boleh jadi menghuni setiap kamar mahasiswa pendamba perubahan di Jakarta, sedangkan selebaran harga alfamart bahkan belum sempat dibaca langsung disapu pembantu rumah tangga di salah satu perumahan di Jakarta.

Nah, ketika itu, apakah sahih kita berkata buku si doktor Harvard benar-benar lebih bermanfaat dari buku si sarjana Google? Apakah tulisan Ayu Utami lebih bermutu daripada si penyair debutan? Atau majalah progresif kita lebih inspiratif ketimbang daftar harga di Alfamart? Bayangkan saja setelah lima tahun, perpolitikan tetap carut marut, harga BBM tetap saja naik dan harga nasi padang pun ikut-ikutan naik. Setelah dua puluh tahun puisi-puisi kita ternyata tetap saja mengulang tema-tema Pujangga Baru. Majalah progresif kita? Oh, ia masih menghiasi kost-kostan mahasiswa progresif generasi selanjutnya, meski pun isinya masih mirip-mirip dengan yang dulu. Atau, bisa saja ada perubahan yang berarti. Hanya saya terlampau pesimis. Namun, lima tahun yang berlalu itu sudah jauh dari cukup untuk melupakan si operator mesin cetak yang tak lulus Sekolah Menengah Pertama itu; yang kita ingat hanyalah Jakob Oetomo dan Kwe Tek Hoay. Padahal, tanpanya niscaya kedua nama itu bisa semerbak.
***
Percetakan-percetakan di Jalan Pramuka menunjukkan dengan gamblang betapa dalam hal produksi fisik buku—sang jendela ilmu pengetahuan—diskriminasi pun sirna. Segala jenis buku menjadi setara dalam produksinya. Ketika tinta-tinta yang menjelma huruf-huruf yang membawa kepala kita memikirkan banyak hal atau memahami banyak hal menyentuh kertas-kertas putih tanpa cela, ketika itu, segala ilmu, segala informasi, diperlakukan sama. Ketika segala ilmu dan ide untuk pertama kalinya menjelma daging, mereka semua sama.
Perbedaan baru muncul ketika kita melangkah beberapa kilo dari Jalan Pramuka menuju Toko Buku Gramedia Pusat yang ada di Matraman Raya. Di mana kurasi atas ilmu pengetahuan dan pengkotak-kotakannya dalam kelas-kelas menampakkan diri secara nyata. Atau, perbedaan itu bisa juga mengemuka dalam ruang kelas di sebuah sekolah tinggi filsafat atau di semua kelas dalam sekolah tinggi apa pun, juga di mana ada strata ilmu pengetahuan yang diam-diam tersemat dalam kepala kita. Atau, jangan-jangan karena imajinasi kita tentang buku hanya sebatas pajangan di rak-rak toko buku tanpa pernah mau menyentuh aroma lem panas dan aroma tinta yang bisa menyebabkan TBC?
Apa pun alasannya, kurasi atas jendela ilmu pengetahuan ini tak serta merta membawa perubahan yang diandaikan yang diniatkan sejak awal, meskipun hal itu tetap dibutuhkan. Minimal menjaga agar buku karangan Freddy S tidak masuk dalam kelas PPKN SD. Agaknya, kurasi ini pun butuh belajar dari percetakan; memberlakukan semuanya secara setara pada porsinya yang tepat. Setidaknya, jika buku Ayu Utami dibeli lima puluh eks dalam seminggu, penyair debutan kita bolehlah kebagian dua pembeli. Perkara ini, memang perkara pengkurasian buku. Mengapa harus buku A yang diresensi di koran ternama dan bukan buku B; mengapa harus buku Z yang ramai dibincangkan di media sosial dan bukan buku X; mengapa buku C yang jadi rujukan di kelas-kelas ketimbang buku D? Tapi sudahlah, perkara ini dapat dilanjutkan di kesempatan lain atau bisa kita dapatkan jawabannya pada para pencerita yang lain.
Ketika selesai menulis artikel ini, saya menyempatkan diri melewati rumah toko-rumah toko di Jalan Pramuka Raya itu kembali. Ramainya masih tetap seperti biasanya. Namun, tiba-tiba terbersit tanya di kepala saya; apakah masih relevan membicarakan percetakan di Jalan Pramuka Raya itu dalam sebuah tulisan yang bahkan tak akan bertemu kertas sama sekali sejak saya tuangkan hingga anda baca?***
*Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di rubrik Oase, IndoProgress, 30 Juni 2013.