Stoikisme sebagai sebuah aliran filsafat yang muncul pada kebudayaan Romawi tentu tidak begitu saja hilang setelah tak lagi ada kebudayaan tersebut. Sampai filsafat modern dan juga kontemporer, pengaruh Stoikisme terasa. John Sellars misalnya menyebutkan beberapa nama filsuf yang sangat terpengaruh stoikisme yakni Montaigne, Kant, Nietzsche, dan Deleuze.[1] Tentu menarik melihat bagaimana sumbangan stoikisme terhadap para pemikir itu. Terkhusus untuk kepentingan tulisan ini, kita akan membahas hubungan antara Nietzsche dan stoikisme.
Tentang ketertarikan Nietzsche atas filsafat dan kebudayaan antik memang cukup beralasan. Ia dikenal pada awalnya sebagai seorang ahli filologi terkhusus untuk bahasa-bahasa dari kebudayaan antik. Bahkan, Nietzsche banyak menulis tentang kebudayaan antik itu. Nietzsche memang belajar secara khusus tentang filologi zaman antik ini di Universitas Bonn dan Leipzig dan pada usia 24 tahun dia diangkat sebagai Profesor Luar Biasa bidang Filologi Klasik di Universitas Basel.[2]
Jika ketertarikan Nietzsche terhadap filsafat Yunani langsung terasa dengan melihat saja beberapa judul karya Nietzsche, untuk filsafat Romawi terkhusus Stoikisme hal itu tak bisa kita lakukan[3]. Namun beberapa penulis merujuk ke beberapa karya Nietzsche seperti Beyond God and Evil dan On the Genealogy of Morals dan menemukan adanya pengaruh stoikisme yang begitu besar dalam pemikiran Nietzsche. R. O. Elveton misalnya menulis sebuah artikel khusus tentang hubungan Nietzsche dan tradisi stoik ini dalam artikelnya “Nietzsche’s Stoicism: The Depths Are Inside”.[4] John Sellar menunjukan bagaimana hubungan antara Nietzsche dan stoikisme itu sedikit paradoks; di satu sisi Nietzsche dengan sangat keras menentang ide stoikisme tentang “hidup mengikuti alam” namun di sisi lain Nietzsche memuji Epiktetus dan Senecca sebagai para moralis yang hebat.[5]
Elveton dalam tulisannya yang disebutkan di atas mengunggkapkan bahwa di dalam ide Nietzsche tentang genealogi moral, sangat banyak ditemukan pengaruh dan juga negasi atas stoikisme. Di satu sisi Nietzsche mengamini dan mirip dengan beberapa butir pemikiran stoikisme, di sisi lain Nietzsche juga terlihat mengkritik dan jauh berbeda dengan beberapa pokok pemikiran stoikisme yang ‘mirip’ dengan pemikiran Nietzsche.
Untuk mencerna lebih lanjut hubungan Nietzsche dan Stoikisme maka tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, tulisan ini akan membahas artikel dari R. O. Elveton terkhusus pada bagian-bagian di mana Nietzsche sangat terpengaruh pada tradisi stiok. Kedua, masih membahas artikel tersebut di atas, kita akan menyarikan bagian-bagian di mana Nietzsche mengkritik dan menolak beberapa pemikiran stoikisme dan sekaligus memungkinkan pengembangnnya atas konsepnya sendiri. Ketiga, sebagai bagian terkakir, tulisan ini akan memasukan sedikit catatan atas hubungan antara Nietzsche dan Stoikisme.
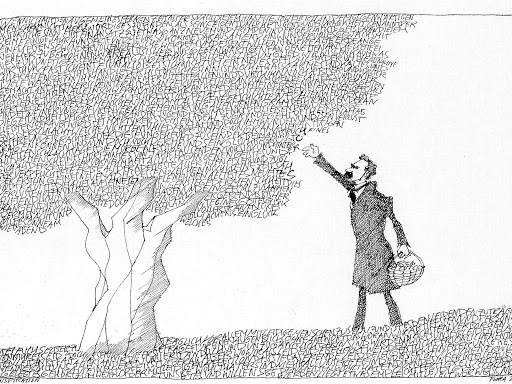
Nietzsche Mengagumi Stoikisme[6]
Di dalam tulisannya, Elveton mencurigai adanya kesamaan antara Nietzsche dengan Stoikisme terkhusus dalam hal filsafat Nietzsche yang disebut sebagai sebuah seni hidup (eine Kunst des lebens). Hal ini memang sejalan dengan stoikisme karena kita tahu untuk stoikisme filsafat adalah latihan untuk hidup. Elveton lantas berspekulasi bahwa konsep Nietzsche “kehendak berkuasa” (the will to power) merupakan konsep yang diambil Nietzsche dengan sebuah peremenungan yang lebih dalam dari formula Stoikisme tentang “hidup mengikuti alam”. Kita tahu, the will to power, secara garis besar, merupakan salah satu pemikiran Nietzsche yang paling terkenal dan merupakan sebuah konsep yang interior untuk hidup dan bukan sebuah konsep metafisika atau transenden yang melampaui hidup.[7]
Menurut Elveton, Nietzsche membahasakan konsep “hidup mengikuti alam” dari stoikisme dengan formula baru yakni “kehendak berkuasa” (the will to power), tentu saja dengan perubahan-perubahan tertentu yang justru membawa konsep “hidup mengikuti alam” menjadi lebih dalam. Lebih khusus, kedekatan Nietzsche dan Stoikisme ini dilihat oleh Elveton dalam hubungan Nietzsche dan Epictetus.
Setidaknya, ada tiga alasan menurut Elveton untuk membuktikan dekatnya Nietzsche dan Epitectus. Pertama, fakta menunjukan bahwa Nietzsche membaca Epitectus dengan kepedulian yang tinggi. Kedua, di dalam pemikiran Epictetus tentang relasi manusia sudah ditemukan pernyataan tentang kehendak manusia (human will). Ketiga, pandangan Epitectus tentang ‘penderitaan’ menawarkan point penting yang kontras dengan internalisasi dari kehendak manusia yang diidentifikasikan dalam genealogi[8] Nietzsche dalam masalah-masalah seperti rasa bersalah, penderitaan, dan suara hati yang buruk.
Elveton juga mengingatkan hal penting ketika membaca pembacaan Nietzsche atas filsafat antik yakni bagaimana ia melihat adanya dekadensi dalam kebudayaan Yunani Kuno. Hal ini bisa kita lihat juga dalam salah satu tulisan Nietzsche “The Problem of Socrates” dalam The Twilight of The Idols. Namun, Nietzsche sendiri juga menemukan bahwa dalam tradisi pemikiran klasik Yunani tersebut adanya hal-hal positif tentang martabat manusia (nobility) yang mana semakin kentara dalam tradisi Stoik.
Kesamaan Nietzsche dan Stoikisme (terkhusus Epitectus) ada pada penekanan bahwa “ide-ide” memiliki konsekuensi untuk hidup. Hal ini, yakni “ide-ide” berkonsekuensi untuk hidup, merupakan sebuah nada utama dalam karya Epitectus, Discourses, yang mana semuanya hampir berisi tentang latihan untuk penguatan atau pelemahan dari jiwa penguasaan diri (soul’s self-mastery). Elveton memberi dua kutipan, masing-masing dari Discourses dan Beyond God and Evil untuk membuktikan kesamaan antara Nietzsche dan Epictetus itu[9]:
If indeed one had to be deceived into learning that among things external and independent of our free choice none concerns us, I, for my part, should consent to a deception which would result in my living thereafter serenely and without turmoil […]. (Discourses, hlm. 35).
The falseness of a judgment is for us not necessarily an objection to a judgment […]. The question is to what extent it is life-promoting, lifepreserving […]. (Beyond God and Evil, hlm. 4).
Selain adanya kesamaan ide di dalam karya Nietzsche dan Epictetus, Elveton juga menyatakan kesamaan keduanya dalam gaya penulisan. Gaya tulisan mereka seakan bergerak secara cepat, sedikit aforistik, dari sebuah pemikiran ke pemikiran yang lain, mengeksplorasi konsekuensi-konsekuensi dari beberapa kriteria tentang “penguasaan-diri”. Secara lebih substantif, keduanya mengajarkan tentang martabat jiwa individual yang melibatkan sikap keras pada diri sendiri, disiplin diri, kejujuran diri, dan tidak takut pada situasi eksistensi manusia.
Epictetus dan Nietzsche punya tujuan yang sama yakni pencapaian keindependensian yang radikal dan “penguasaan diri” secara fatalis. Elveton pun mengatakan bahwa dokrin amor fati yang terkenal dari Nietzsche sudah dapat dikenali dalam Epictetus. Demikain, Elveton mengutip Epictetus, “But […] things about us being as they are and as their nature is, we may, for our own part, keep our wills in harmony with what happens”. Kalimat ini tentu saja mengeksrpesikan apa yang dimaksudkan Nietzsche dengan amor fati. Amor fati merupakan term yang ditemukan dalam karyanya bertajuk The Gay Science. Term ini merujuk pada pandangan Nietzsche bahwa seseorang harus ‘berkata ya’ pada kehidupan, tidak menegasikan eksistensinya namun mengaffirmasi eksistensinya itu.[10]

Elveton juga mengutip sebuah pernyataan Nietzsche di mana di sana ditunjukan bagaimana Nietzsche langsung merujuk pada Stoik dalam soal disiplin diri dalam kebajikan tentang kejujuran[11]:
Honesty, supposing that this is our virtue from which we cannot get away, we free spirits—well, let us work on it with all our malice and love and not weary of “perfecting” ourselves in our virtue, the only one left us. […] And if our honesty should nevertheless grow weary one day and sigh and stretch its limbs and find us too hard, and would like to have things better, easier, tenderer, like an agreeable vice—let us remain hard, we last Stoics! (Beyond God and Evil, hlm. 227)
Mengkritik dan Meradikalkan Ide Stoikisme[12]
Nietzsche dengan keras mengkritik distingsi yang dibuat Stoikisme tentang “apa yang tergantung pada diri kita sendiri” dan “apa yang tidak tergantung pada dirimu sendiri”. Distingsi ini merupakan sebuah doktrin moral yang juga merupakan salah satu hal penting dalam pemikiran stoikisme, terkhusus di bidang etika. “Apa yang tergantung pada diri kita sendiri” ini pun merupakan sebuah kecenderungan yang mana akan selalu harus sesuai dengan kehendak Alam (nature).[13]
Lebih jauh, Epictetus memandang alam (nature) sebagai kosmos rasional. Sedangkan “diri” dipandang sebagai kehendak rasional yang mampu memahami kosmos dan menguasai dirinya dalam menangguhkan segala dorongan untuk menganggu ketertiban alam. Pandangan metafisika Stoik yang demikian, yang merupakan pengulangan atas formula metafisika Platon yang diulangi oleh Epictetus, ini secara langsung diserang Nietzsche.
Elveton mencoba melihat ide Nietzsche “kehendak berkuasa” (the will to power) sebagai sebuah rumusan metafisika.[14] Dalam “kehendak berkuasa” terlihat langkah awal Nietzsche untuk meninggalkan dan sekaligus mengkritik dokrin Stoik “hidup berdasarkan alam” (live according to nature). Nietzsche secara langsung mempertanyakan dokrin Stoik tersebut sebagaimana dikutip Elveton[15]:
According to nature” you want to live? O you noble Stoics, what deceptive words these are! Imagine a being like nature, wasteful beyond measure, indifferent beyond measure, without purposes and consideration […]—how could you live according to this indifference? […] In truth, the matter is altogether different: while you pretend rapturously to read the canon of your law in nature, you want something opposite […]. Your pride wants to impose your morality, your ideal, on nature. (Beyond God and Evil, hlm. 9)
Nietzsche juga mengkritik konsep “diri” dalam Stoikisme. Diri dalam pemikiran Nietzsche adalah manifestasi partikular dari “kehendak” dan alam adalah will to power—jadi diri adalah manifestasi partikular dari alam—ketika kita melihat konsep metafisikanya, will to power, sebagai sebuah ontologi. Namun konsep will dari Nietzsche mengambil dimensi non-stoik dengan menghilangkan oposisi alam dari hubungan ini.
Menurut Elveton, oposisi fundamental antara “apa yang ada di bawah kehendak diri” dan “apa yang bukan” dari Stoik mereduksi “diri” ke dalam hanya satu dimensi dan kepada suatu pemaknaan atas diri yang tidak sempurna. Sikap “saya”, keadaan batin “saya” adalah refleksi atas kekuatan individual “diri-saya” tersebut. Tindakan saya atas dunia bukanlah saya sesungguhnya melainkan hanya bagian dari diri saya. Apa yang saya (diri) lakukan, sepenuhnya bukanlah saya tetapi saya adalah sikap rasional saya terhadap apa yang saya lakukan dan sikap rasional saya terhadap apa yang telah terjadi dan apa yang terjadi pada saya. Jadi, “diri” (self) dalam Stoik bukanlah diri secara “keseluruhan” melainkan diri yang “dipikirkan” secara ‘rasional’; demikian pemaparan Elveton atas pembacaan Nietzsche terhadap ide “diri” dari Stoik.
Mungkin bisa kita pahami apa yang dikatakan Elveton ini demikian. Berikut, kita akan coba berusaha memahaminya melalui sebuah fragmen. Terkenal sebuah cerita tentang seorang Stoik yang hendak dipatahkan kakinya oleh majikannya. Ia tidak berteriak kesakitan atau melawan tetapi dia hanya berkata melalui ‘rasional’-nya bahwa jangan memelintir kaki saya, nanti kaki itu akan patah. Tetapi majikannya yang mendengar itu tidak mengindahkan apa yang dikatakannya dan tetap memelintir kakinya. Akirnya, kaki si stoik itu pun patah dan dia berkata pada majikannya, “itu kan hasilnya. Saya kan sudah bilang kalau diplintir nanti akan patah kaki saya?”
Di sini diri Sang Stoik bukanlah ia yang merasa sakit, merasa ketakutan karena kakinya akan patah, tetapi Stoik adalah dia yang secara rasional sadar bahwa tindakan pematahan kakinya itu berada di luar kemampuan rasionalnya dan dia tak punya kuasa atas kakinya dan tindakan pematahan atas kakinya itu.
Selanjutnya, menurut Elveton, meskipun Nietzsche tidak menempatkan secara spesifik pandangan Stoik tentang kehendak (will), hal ini dapat kita lihat pada fase awal periodesasi reaktif spiritual gerakan “yang lemah” melawan “yang kuat” dalam tahap kedua genealogi Nietzsche, yakni pada periode moral. Stoik menunjukan upaya menjauhi peristiwa-peristiwa “duniawi” dengan menciptakan kebijaksanaan aristokratik yang lebih “bersifat ke dalam diri” (inward). “Inward” ini dalam pandangan Nietzsche, secara historis, memegang peranan penting dalam tahap moral dari genealoginya. Perkara ini diungkapkan Nietzsche dalam Beyond God and Evil dan juga On the Genealogy of Morals. Dakam On genealogy of Moral Nietzsche menulis demikian, “All instincts that do not discharge themselves outwardly turn inward—this is what I call the internalization of man: thus it was that man first developed what was later called his ‘soul”.
Genealogi Nietzsche pun, pada tempat awalnya, dipengaruhi oleh konsep “kehendak” yang murni Stoik, yang mana berafiliasi dengan faktor genealogis, “dosa”, dan itu menghasilkan “rasa bersalah” (guilty) atau “kesadaran yang salah” (bad conscience). Demikian Nietzsche[16]:
who had to turn himself into an adventure, a torture chamber, an uncertain and dangerous wilderness—this fool, this yearning and desperate prisoner became the inventor of the “bad conscience.” But thus began the gravest and uncanniest illness, from which humanity has not yet recovered, man’s suffering of man, of himself—the result of a forcible sundering from his animal past, as it were a leap and plunge into new surroundings and conditions of existence […]. Let us add at once that, on the other hand, the existence on earth of an animal soul turned against itself, taking sides against itself, was something so new, profound, unheard of, enigmatic, contradictory, and pregnant with a future that the aspect of the earth was essentially altered. (On the Genealogy of Morals II, hlm.16)
Menurut Elveton, Nietzsche mentransformasikan konsep “inwardness” dari Stoik dengan sebuah penekanan dan cakupan kedalaman yang lebih luas dan itu membawa sebuah konsep “diri” yang baru dan sebuah tugas yang baru untuk “diri” tersebut.
Namun Elveton juga mengakui adanya kompleksitas tertentu dalam hubunugan antara Nietzsche dan Stoik. Problem utama Nietzsche dalam On the Genealogy of Morals adalah pencaharian atas makna ascetic yang ideal. Nietzsche mengajukan pertanyaan, bagaimana mungkin bagi kehendak, yang secara essensial adalah kekuatan peneguhan hidup, dipaksa untuk dibelokkan kembali kepada dirinya sendiri dengan cara yang mengancam kehidupan? Nietzsche menjawab bahwa kehendak lebih suka menghendaki negasinya sendiri dari pada tidak sama sekali.
Elveton menyimpulkan bahwa, Nietzsche mengacu pada faktor baru yang muncul dalam tahap awal genealogi yakni sebuah proyek eksistensi yang “melampaui moralitas”. Konsekuensi penting lain dari proyek Nietzsche ini adalah menghapuskan oposisi antara “apa yang ada di bawah kendali saya” dan “apa yang tidak” dan memasukan sebuah konsepsi baru tentang “kehendak” (will) yang tak terbatas. Pada titik ini, kita melihat bagaimana Nietzsche menolak Stoikisme.
Intensionalitas terhadap sesuatu merupakan landasan dari sebuah tindakan. Intensionalitas ini menurut Nietzsche membutuhkan periode yang panjang untuk terlaksana. Hal yang demikian ini ada dalam “spirit eropa” yang oleh Nietzsche dikatakan sebagai, “…trained to strength, ruthless curiosity, and subtle mobility”. Nietzsche kemudian mencoba menunjukan sebuah sisi terkecil dari diri yakni diri yang tanpa intensionalitas. Demikian Nietzsche[17]:
But today—shouldn’t we have reached the necessity of once more resolving on a reversal and fundamental shift in values, owing to another self-examination of man, another growth in profundity? […] After all, today at least we immoralists have the suspicion that the decisive value of an action lies precisely in what is unintentional in it, while everything about it that is intentional, everything about it that can be seen, known, ‘conscious,’ still belongs to its surface and skin—which, like every skin, betrays something but conceals even more. In short, we believe that the intention is merely a sign and symptom that still requires interpretation—moreover, a sign that means too much and therefore, taken by itself alone, almost nothing. (Beyond God and Evil, hlm. 32)
Di sini kita melihat bahwa bagi Nietzsche sesuatu yang dilakukan dengan intensionalitas tertentu masih patut dicurigai karena dia berpotensi menyimpan hal-hal tertentu, maka, sesuatu tindakan yang sungguh murni adalah tanpa intensionalitas.
Elveton menguraikan bahwa di sini konsep diri-transparan dalam Stoikisme digantikan dengan kecurigaan-diri oleh Nietzsche dan lantas diradikalkan menjadi interpretasi-diri dan eksperimen-diri. Bagi Nietzsche, tidak ada “pelaku” (dalam pengeritan motif tertentu) di balik sebuah tindaka tanpa intensionalitas.
Intensionalitas ‘diajarkan’ pada diri manusia dalam rentang periode tertentu sehingga hidup dikatakan layak untuk dihidupi harus menunggu periode tersebut. Dengan hidup tanpa intensionalitas yang mana di dalamnya tidak tersembunyi sebuah “motif” atau “pelaku” tertentu atas tindakan, maka manusia harus dikembalikan ke alam. Mengembalikan hidup ke alam berarti menjadikan “kehendak” (will) manusia sebagai “kehendak untuk berkuasa” (the will to power); karena seperti yang sudah kita katakan sebelumnya bahwa nature di sini adalah will to power.
Dengan mengemebalikan manusia ke alam ini berarti Nietzsche menolak konsep jiwa-atomisme tradisional dan dia juga menolak segala konsep tentang “diri” ketika menunjukan tak adanya “pelaku” di balik segala “tindakan”. Di lain pihak, Nietzsche juga berusaha untuk mengembangkan ideal ascetik-nya dengan mengupayakan sebuah roh tindakan yang “lebih dalam, lebih ke kedalaman batin (inwardness)” yang dicapai dengan sebuah penderitaan asketis. Yang memungkin Nietzsche membicarakan inwardness yang seperti ini adalah tahap kebatinan Kristen.
Dalam ide tentang penderitaan (suffering), Elveton mengatakan bahwa kita bisa melihat perbedaan antara Nietzsche dan Stoicisme. Untuk itu, ia mengutip Berdyaev yang menunjukan karakteristik stoikisme dalam menanggapi penderitaan sebagai sebuah sikap yang putus asa. Sikap moral yang tinggi dalam Stoikisme yang ditandai dengan apatheia[18] menurut Berdyaev menyimpan ciri moralitas putus asa dan dekaden. Demikian Berdyaev seturut kutipan Elveton[19]:
Stoicism is the doctrine of self-salvation and of the attainment of peace or “apathy.” Stoic morality testifies to a very high level reached by man’s moral consciousness, but in the last resort it is a decadent and pessimistic morality of despair, which sees no meaning in life; it is inspired by the fear of suffering. One must lose sensitiveness to suffering and become indifferent—that is the only way out.
Sebaliknya, ketika Berdyaev merujuk ke pada Nietzsche, ia melihat adanya sebuah tendensi Nietzsche untuk melihat penderitaan dalam rangka penebusan menuju ke kehidupan, walau pun memang penderitaan tersebut bisa juga membawa manusia pada kematian.
Penutup: “Will To Power”
Demikianlah dengan merujuk hampir sepenuhnya pada artikel R. O. Elveton R. O. Elveton, “Nietzsche’s Stoicism: The Depths are Inside” kita melihat adanya keterpautan antara Nietzsche dan Stoicisme. Pada satu sisi, Nietzsche mengagumi apa yang menjadi pencapaian-pencapaian filsafat stoikisme dan di sisi lain ia pun mengkritik serta meradikalkan apa yang tersedia dalam filsafat stoiksime demi mengembangkan filsafatnya sendiri.
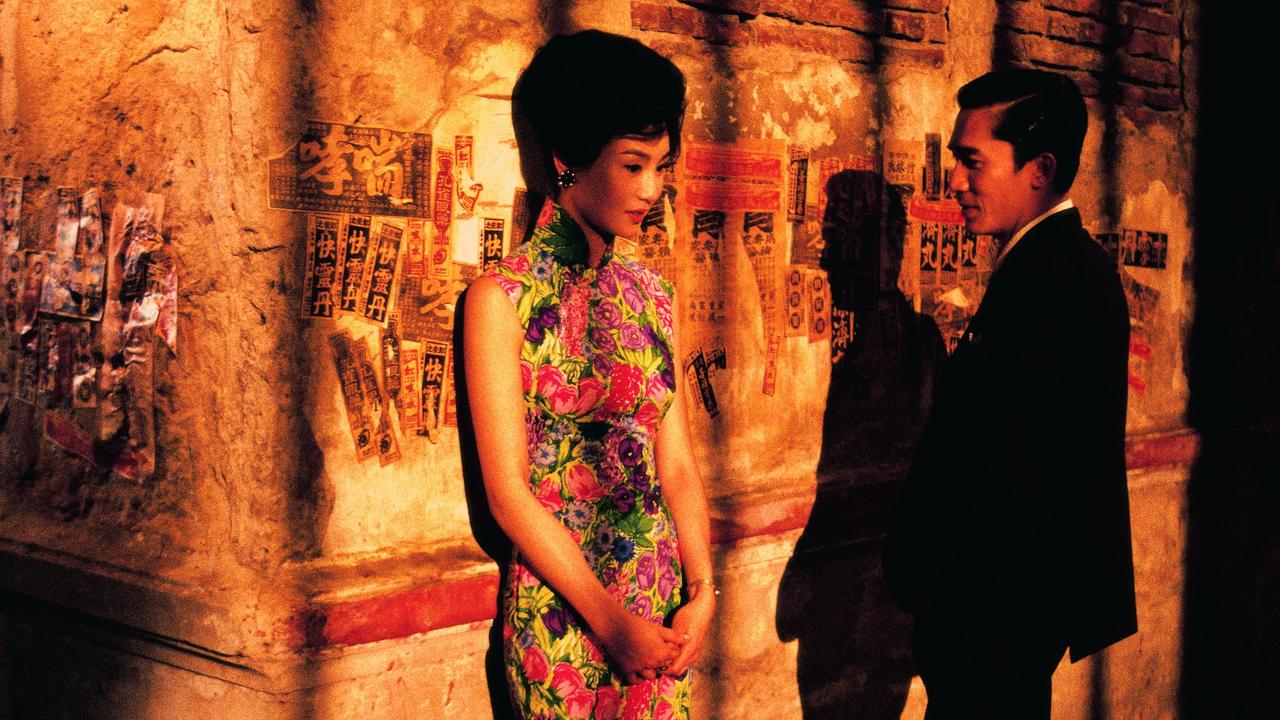
Selain kagum pada Epictetus dan Senecca yang oleh Nietzsche dianggagp sebagai figur moral terhebat, kita melihat bahwa Nietzsche membaca dengan tekun dan serius karya Epictetus. Dan oleh Elveton ditunjukan beberapa hal yang mana ada kesamaan dari ide Nietzsche dan Epictetus. Tentu dengan gampang kita menyimpulkan bahwa Nietzsche-lah yang dipengaruhi oleh Epictetus.
Namun, Nietzsche pun mengkritik beberapa pandangan dan berbeda jalan dalam beberapa hal dengan para pemikir stoikisme termasuk juga Epictetus tersebut. Kita melihat hal yang paling mendasar adalah bagaimana konsep hidup berdasarkan alam dari Stoikisme menjadi pendasaran bagi Nietzsche untuk mengembangkan will to power-nya. Namun konsekuensi dari pengembangan dari hidup berdasarkan alam menjadi will to power ini membawa Nietzsche pada pembedaan yang tajam dengan Stoikisme terkhusus dalam hal diri, dan juga intensionalitas.
Akir kata, mencerna apa yang menyamakan dan apa yang membedakan Nietzsche dan Stoikisme bukanlah perkara gampang. Apalagi keduanya adalah dua tradisi besar dengan kompleksitas pemikiran yang tak bisa dianggap remeh pula. Tulisan ini hanya merupakan review atas upaya pembacaan hubungan antara Nietzsche dan Stoikisme yang dilakukan R. O. Elveton sehingga sangat mungkin tulisan ini melewati dan tidak bisa mencerna apa saja yang diajukan Elveton, mengingat untuk memahaminya diandaikan pemahaman yang sangat memadai pula tentang stoikisme dan Nietzsche.
Daftar Bacaan:
Elveton, R. O., “Nietzsche’s Stoicism: The Depths are Inside”, dalam Paul Bishop (ed.), Nietzsche and Antiquity: His Reaction and Response to the Classical Tradition,(Toronto: Husion House), 2004.
Sedgwick, Peter R., Nietzsche: The Key Concepts, (New York: Routledge), 2009.
Sellars, John, Stoicism, (Durham: Acumen), 2010.
Spinks, Lee, Friedrich Nietzsche, (New York: Routledge), 2003.
Wibowo, A. Setyo, “Rangkuman dan Ajaran Stoicisme”, catatan untuk Kuliah I “Seminar Stoicisme” di STF Driyarkara, 27 Januari 2012.
[1] John Sellars, Stoicism, (Durham: Acumen), 2010, hlm. ix.
[2] Lee Spinks, Friedrich Nietzsche, (New York: Routledge), 2003, hlm. 2.
[3] Beberapa tulisan Nietzsche tentang filsafat dan budaya Yunani yang saya maksud antara lain, “The Greek State”, “The Greek Woman”, “Homer’s Contest”, dan “Philosophy During the Tragic Age of Greeks”.
[4] R. O. Elveton, “Nietzsche’s Stoicism: The Depths are Inside”, dalam Paul Bishop (ed.), Nietzsche and Antiquity: His Reaction and Response to the Classical Tradition,(Toronto: Husion House), 2004, hlm. 192-203.
[5] John Sellars, Stoicism…, hlm. 151-152.
[6] Bagian ini merujuk hampir sepenuhnya pada R. O. Elveton, “Nietzsche’s Stoicism: The Depths are Inside”. Jika ada rujukan lain akan disampaikan pada catatan kaki.
[7] Lee Spinks, Friedrich Nietzsche…, hlm. 151.
[8] Term genealogi dalam Nietzsche harus diingat merujuk pada metode untuk menganalisas model-model yang dominan dan yang berbeda-beda dalam wacanan tentang etika (moralitas). Ia adalah juga sebuah ‘penelitian’ tentang konsep etika (moralitas) dalam sejarah. Lih. Peter R. Sedgwick, Nietzsche: The Key Concepts, (New York: Routledge), 2009, hlm. 54.
[9] R. O. Elveton, “Nietzsche’s Stoicism: The Depths are Inside”…, hlm. 193.
[10] Peter R. Sedgwick, Nietzsche: The Key Concepts…, hlm. 3.
[11] R. O. Elveton, “Nietzsche’s Stoicism: The Depths are Inside”…, hlm. 194.
[12] Bagian ini, seperti bagian sebelumnya, hampir sepenuhnya merujuk ke artikel R. O. Elveton, “Nietzsche’s Stoicism: The Depths are Inside”. Jika ada rujukan lain akan dijelaskan pada bagian catatan kaki.
[13] Lihat, A. Setyo Wibowo, “Rangkuman dan Ajaran Stoicisme”, catatan untuk Kuliah I “Seminar Stoicisme” di STF Driyarkara, 27 Januari 2012, hlm. 3.
[14] Hal ini bisa jadi berbeda dengan pembacaan yang umum atau yang lain. Bdk. Dengan catatan kaki no. 7.
[15] R. O. Elveton, “Nietzsche’s Stoicism: The Depths are Inside”…, hlm. 195.
[16] R. O. Elveton, “Nietzsche’s Stoicism: The Depths are Inside”…, hlm. 196.
[17] R. O. Elveton, “Nietzsche’s Stoicism: The Depths are Inside”…, hlm. 198.
[18] Apatheia adalah ketenangan jiwa. Orang bijak yang “apatheia” artinya “ia tidak pernah ditarik-tarik” ke mana pun. Keteguhannya tidak bisa digoyahkan oleh impuls-impuls berlebihan. Lih. A. Setyo Wibowo, “Rangkuman dan Ajaran Stoikisme”…, hlm. 6.
[19] R. O. Elveton, “Nietzsche’s Stoicism: The Depths are Inside”…, hlm. 199.
*Catatan: Tulisan ini merupakan tugas dalam rangka UAS pada kelas Stoikisme bersama Dr. A. Setyo Wibowo di STF Driyarkara pada semester genap 2011-2012.





Sedap tulisan Om Berto ini.
Makasih. Wuehehehehehe