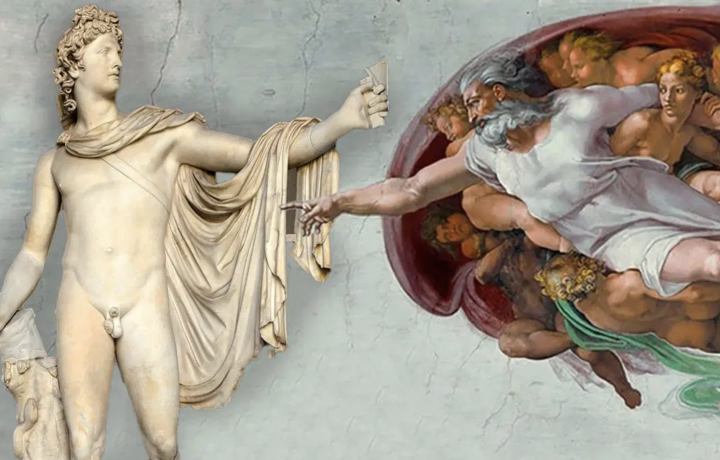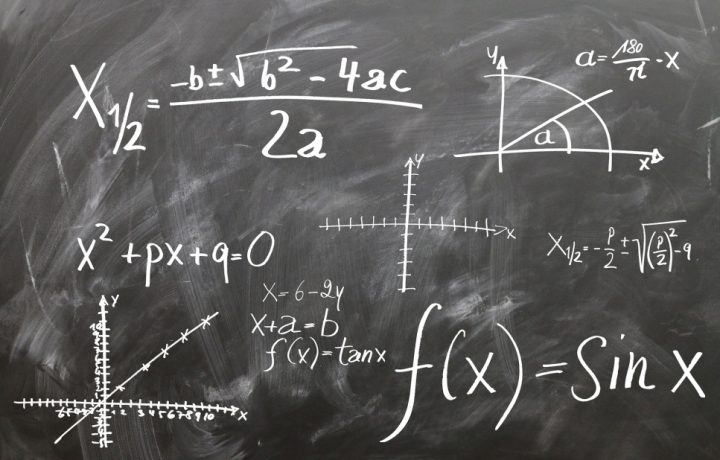KITA harus berterima kasih pada Plato lantaran dari Akademianya-lah sekolah-sekolah modern kita saat ini dimungkinkan untuk ada. Memang, jika bukan Plato tetapi orang lain yang membangun Akademia—sebut saja jika bukan Plato tetapi Hukama yang membangun Akademia—sekolah-sekolah kita saat ini pun akan tetap ada. Plato kebetulan saja lahir di zaman dan tempat yang masyarakatnya membutuhkan sebuah sekolah dengan metode yang jelas dan tertentu. Pendidikan disyaratkan oleh keadaan bukan oleh individu tertentu. Kalimat terakhir ini tentu bukan hal baru untuk pembaca sekalian.
Pendidikan modern ini lantas berkembang di Eropa. Perlahan-lahan bagaikan merembesnya air di sebuah kain. Di masa Skolastik, atau lebih dikenal dengan masa kegelapan, hanya untuk kaum bangsawan dan padri-padri Katolik. Lantas, Aufklärung mengubahnya menjadi milik kaum burjuis. Pendidikan sebagai HAM pun muncul di sini. Perkembangan selanjutnya, tentu bisa kita baca di banyak sumber. Anggar Septiadi pernah pula mereview sebuah buku tentang pendidikan melalui perspektif Marxisme.
Di Tanah Air, kita tahu, pendidikan mulai marak berkembang semenjak adanya Politik Etis. Pemerintah Belanda atas desakan dari kaum sosialis Belanda saat itu lantas membuka kesempatan pendidikan bagi masyarakat jajahan. Pendidikan modern pun muncul di Nusantara. Sekolah-sekolah yang dibangun pemerintah kolonial ini lantas membentuk sebuah kelas masyarakat baru; sebuah kelas yang di Jawa disebut kelas priyayi. Merekalah masyarakat yang berpikir à la Belanda dan lantas terkadang gaya hidupnya menjadi lebih Belanda dari pada Belanda sendiri. Padahal, mereka sesungguhnya disiapkan untuk menjadi pegawai-pegawai Belanda, disiapkan menjadi Ambtenaar, disiapkan menjadi kaum pengabdi. Ketika membaca cerpen Pramoedya bertajuk Jongos + Babu: Sejarah Keluarga yang Sangat Panjang (2002), kepala saya langsung tertautkan pada Kaum Ambtenaar ini.
Seluruh cerpen Pramoedya itu tentu saja menarik. Namun, saya hendak mengutip sebuah bagian untuk pembaca: ‘Keduanya termasuk pada aliran kanan—tak revolusioner, yakni babu-jongos yang suka mencuri sendok, garpu, pisau kemudian melarikan diri. Tidak! Keduanya memestikan diri patuh pada kewajiban. Siapa tahu, barangkali abadilah penghambaannya tiga turunan lagi. Jadi mereka telah membuat batas-batas untuk daerah hidupnya. Sama halnya dengan Renville membuat batas status quo hidupnya Republik.’
Pendidikan kita sedari awal memang aparatus ideologi negara. Ia menciptakan kaum pekerja yang tunduk pada sistem. ‘Hidup memang harus begini,’ begitu kira-kira ungkapan kepasrahan mereka kerap kita dengar sehari-hari. Sehingga, kita janganlah, dan jangan pernah sama sekali, merasa heran jika ada demo buruh menuntut kenaikan upah dimaki-maki para pekerja kerah putih lantaran demo ini mengganggu perjalan mereka ke kantor. Ingat. Mereka, mengutip Pramoedya, ‘…memestikan diri patuh pada kewajiban. Siapa tahu, barangkali abadilah penghambaannya tiga turunan lagi.’ Itu memang satu hal. Barangkali juga memang ada hal lainnya. Apa pun itu. Namun pendidikan memang tidak selamanya berwajah buruk. Pendidikan lantaran Politik Etis ini juga turut membentuk munculnya kaum pergerakan kemerdekaan. Namun, kita tak akan masuk ke dalam perkara itu di sini.

Barangkali pendidikan di masa politik etis ini jugalah yang menyumbang pandangan bahwa dengan pendidikan, kehidupan seseorang, atau sebuah keluarga, bisa diangkat derajatnya. Lebih jauh, pendidikan memberi garansi untuk kehidupan yang lebih baik—secara ekonomi tentu saja. Pendidikan tidak dilihat sebagai cara agar manusia bisa mengetahui sesuatu dengan lebih baik, mengetahui realitas hidupnya dengan lebih baik. Dengan privatisasi ranah pendidikan, tujuan sebenarnya dari pendidikan ini semakin saja terlupakan. Orang tua yang menyekolahkan anaknya tentu melihat apa hasi dari investasinya atas sang anak. Tentu alasan semacam ‘biar si anak menjadi lebih manusia dengan pendidikan’ atau ‘demi masa depan sang anak sendiri’ menyimpan pandangan sebenarnya mereka, biar si anak bisa mencari uang yang lebih banyak melalui kerja-kerja yang lebih ‘modern.’ Namanya investasi, Anda tentu akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan berapa yang anda investasikan; kecuali kalau Anda sial. Dalam kasus pendidikan, kesialan itu, misalnya, lantaran anak anda butuh waktu jauh lebih lama dari pada waktu normal.
Lantaran pendidikan dipandang sebagai perkara investasi, lebih jauh bisnis jasa, janganlah pernah heran dan jangan pernah bersungut-sungut jika di daerah Anda fasilitas pendidikan tidaklah bagus. Jika daerah Anda pendapatan perkapitanya masih begitu-begitu saja, janganlah pernah berharap fasilitas pendidikan di tempat Anda sama baiknya dengan daerah yang pendapatan perkapitanya lebih baik. Bagaimana pun caranya Anda berusaha, Anda hanya mungkin mendapatkan pendidikan yang itu-itu juga. Yah, memang ada kadang-kadang mereka yang ‘beruntung’ masuk dalam pantauan scout Kapitalisme sebagaimana tokoh Ikal dalam Laskar Pelangi. Tetapi tentu dalam Laskar Pelangi ini pun ketidakadilan sudah bisa kita lihat; kenapa Ikal dan bukan Lintang yang berhak atas pendidikan yang lebih tinggi?
Pendidikan, sebuah nama keramat yang bertujuan untuk memartabatkan, memanusiakan manusia ini menyimpan ketidakadilan. Entah dalam kualitas yang ditunjang oleh fasilitas dan kesempatan, entah dalam kuantitas yang juga ditunjang oleh fasilitas dan kesempatan. Dan jika pendidikan tak memiliki ketidakadilan, dunia kita ini pun tentu gonjang-ganjing. Bukankah kapitalisme butuh ketidakadilan untuk terus berjalan dalam puing-puing kehancuran manusia-manusia yang tak beruntung? Lagi pula, hidup ini butuh manusia-manusia yang bekerja di ranah-ranah kasar demi menunjang adanya parfum-parfum, sepatu-sepatu bagus, tas-tas mentereng, dan sederet barang lain yang menjelma seorang karyawan atau karyawati yang berjalan santai di atas trotoar Jalan Jenderal Sudirman. Mungkin ketika Anda menggerutu pada macet jalanan lantaran sebuah demonstrasi, di saat itu juga barangkali Anda harus membuang jauh-jauh rasa jijik dan umpatan ‘betapa tidak manusiawi’-nya perbudakan-perbudakan masa lalu; entah oleh kolonial Eropa atau pun oleh kerajaan-kerajaan masa lalu pada tawanan perang mereka.***
N.b. Judul di atas, Sekolah Minggu, tidak merujuk pada sebuah kegiatan khusus di gereja-gereja.
*Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Rubrik Oase, IndoProgress, pada 2 November 2013.