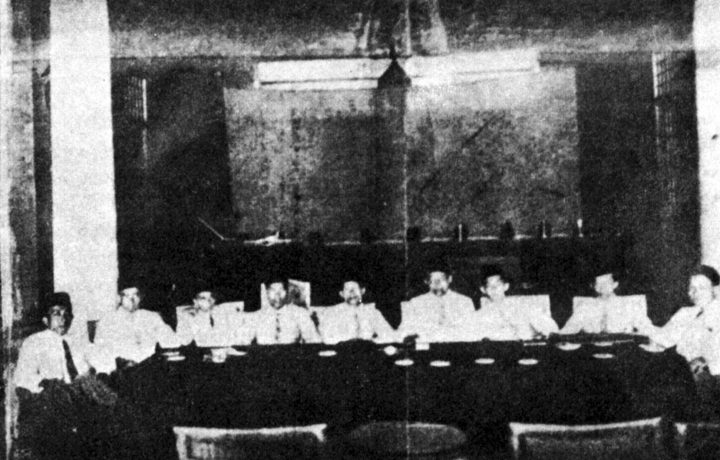“We are at the end of production.”
(Jean Baudrillard, Revenge of the Crystal, hal. 99)
Kini, lagu tak hanya bisa kita dengar lewat produksi aslinya (misal kaset dan CD) tetapi bisa kita dengar pula lewat bentuk produksi lainnya, misalnya Ring Back Tone, penanda jam, sound track sebuah sinetron termutakhir, atau pun sound latar untuk iklan produk mie instan di televisi mau pun radio. Bisa jadi suatu ketika akan ditemukan pula pada iklan sebuah parpol.
Kemajuan teknologi produksi mekanis itu memungkinkan sebuah lagu bisa didengarkan dengan gampang pada setiap media tersebut. Donald Sassoon dalam bukunya tentang budaya Eropa menggambarkan bagaimana musik saat ini berbeda sekali dengan musik di abad 18. Kala itu musik hanya didengarkan di Gereja dan beberapa kegiatan tertentu, saat ini musik bisa didengarkan di mana-mana dengan cara yang sangat ‘privat’ sekali pun.
Produk musik pop bukan lagi hanya mendikte lantas mengikuti selera pasar, lebih dari itu, musik yang didiktekan lantas mengikuti selera pasar tersebut direproduksi kembali ke dalam berbagai bentuk produksi lainnya, tentu saja dengan ‘membelokan’ ‘maksud awal’ musik tersebut. Pada titik ini kita bukan lagi membincangkan termin Roland Barthes (1977) ‘musik untuk didengarkan dan musik yang dimainkan’, melainkan ‘musik yang diperdengarkan dengan tujuan tertentu’ yakni tujuan dari media yang menungganginya.

Fetisisme Penikmat Musik
Theodor W. Adorno jauh-jauh hari telah mengumpat tentang musik pop, yang mana “dieksploitasi hingga kelelahan komersial, yang memuncak pada ‘kristalisasi standar’ (Adorno dlm Storey, 1996)”, lantas menghadirkan fetisisme pada pendengarnya. Maka, ketika musik yang asing (untuk menghindari kata: yang berbobot) muncul, kadang terdengar jelek di telinga kita, membosankan, dan sungguh membuang-buang waktu bila mendengarkannya. Nah, ‘yang fetis’ inilah yang kini didaur ulang, dijiplak, dipindah-wadahkan ke dalam berbagai bentuk produksi lain.
Baiklah kita buat sebuah analogi untuk masalah ini. Sebut saja sebuah lagu pop mutakhir Indonesia (selanjutnya disebut Lagu A) yang dengan—memparafrasekan Efek Rumah Kaca—nada minornya dan mendendangkan perselingkuhan serta raungan patah hati, lantas menjadi begitu mengena di kepala para pemilik telinga melayu. Lagu A ini lantas menjadi ‘musik yang didengar’ di mana saja, entah itu di bus, MP3 Player, dan menjadi ‘musik yang dimainkan’ di setiap acara musik dengan sponsor perusahan-perusahan besar nasional mau pun transnasional atau pun oleh pengamen di tengah KRL.

Beberapa lama kemudian, kita pun akan mendengarkan Lagu A ini pada sound track sebuah sinetron baru di salah satu stasiun televisi nasional. Beberapa lama kemudian, masih di televisi dan terkadang juga radio, beberapa part dari lagu A ini akan kita dengar sebagai sound latar sebuah iklan produk, sebut saja, mie instan. Sebelum itu, tentu saja lagu A ini akan kita dengar, mungkin hanya bagian reffrain-nya yang mendayu-dayu akan muncul sebagai RBT sebuah provider kita. Mari kita melupakan kemungkinan bahwa hal-hal tersebut menyelamatkan sang pemusik dari kerugian akibat pembajakan, yang sering mereka keluhkan itu, melainkan melihat bagaimana musik pop yang fetis (menciptakan kesadaran palsu) ini direproduksi kembali ke dalam bentuk-bentuk produksi lain yang menciptakan fetis-fetis yang baru pula; sebuah bentuk kesadaran palsu yang tercipta dari kesadaran palsu pula.
Musik Pop Disunting Sana-sini
Kejadian seperti itu sering terjadi dalam media massa, khususnya televisi. Baiklah, kita andaikan saja tema yang diangkat dalam lagu A benar-benar adalah buah dari refleksi sang musikus atas hidupnya dan dengan menuangkannya dalam lagu, ia telah membagikan pengalaman itu dengan penikmat musiknya. Musik pop sebagai produk kapitalis tentu mendikte selera pasar dan memilah repertoir musik yang bisa dikonsumsi pasar. Namun, ia tak bisa mengontrol bagaimana sebuah lagu itu dipahami, diinterpretasikan. Maka di sini, lagu A kita andaikan saja bisa memberikan makna menarik dan sedikit emansipatoris bagi kehidupan beberapa pendengarnya.
Namun, bagaimana ketika lagu A tersebut digunakan sebagai sound track, terkadang pula menemani adegan-adegan tertentu, sebuah sinetron? Kini yang hadir tentu saja adalah makna, pemahaman, dan interpretasi dari para pekerja sinetron atas lagu tersebut. Dan bukan sebuah kesalahan bila di sini kita menggaris-bawahi bahwa para pekerja sinetron itu, tentu saja tidak semuanya, kerap tidak bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan mereka. Makna seperti apakah yang akan dimunculkan dari lagu A yang cengeng ini ketika dijukposisiskan dengan sebuah cerita sinetron yang sonder ampun pula cengengnya? Mungkin anda sendiri wajib mengecek hal ini, karena saya cukup yakin hasilnya tidak akan menyenangkan saya. Satu hal yang bisa saya janjikan pada anda bahwa sinetron tersebut minimal akan meraup pemirsa, karena membonceng lagu A yang terlanjur punya banyak penikmat.
Berikutnya, bayangkanlah lagu A yang sudah dinikahi sinetron ini dipersunting pula oleh salah satu Production House pengkreasi iklan sebuah produk mie instan. Di sini, lagu A kita bisa saja diperkosa habis-habisan. Sering terjadi, ketika lagu (yang adalah nada dan lirik itu) masuk dalam produk iklan semacam ini, beberapa kalimat liriknya akan dirubah sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai iklan tersebut; tak lain dan tak bukan menggaet konsumen sebanyak-banyaknya. Anehnya, para—sebut saja—seniman musik pop kita dengan begitu entengnya membiarkan lagu ciptaannya diperkosa sedemikian rupa, bahkan terkadang tanpa malunya ikut nongol pula wajahnya pada iklan untuk televisi atau suaranya pada iklan untuk radio.

Penulis menduga, ketiadaan penghargaan terhadap karya sendiri semacam ini dikarenakan pertama, memang proses penciptaan lagunya yang sungguh sangat gampang dan sungguh terlampau sederhana. Kedua, te-reifikasi-nya para seniman musik pop kita; mereka menjadi semata alat produksi kapitalis tanpa pernah berpikir tentang kemanusiaannya dan pengolahan hidupnya yang terejawantah dalam musik karya mereka. Parahnya lagi, sebagian besar pendengar mereka (untuk tidak menyebut “fans berat”) mengamini saja pemerkosaan atas lagu kesayangan mereka, tanpa pernah menyayangkannya. Sekali lagi, hal ini penulis duga sebagai bukti ketidakberartian lagu A tersebut, dengan demikin ketidak-berartiannya musik pop tersebut. Atau memang saking terreifikasinya sang seniman musik pop dan para pendengar serta pemujanya.
Sound track sebuah sinetron dan sound latar sebuah iklan televisi dan radio adalah contoh, setidak-tidaknya untuk penulis, bahwa lagu Pop dari pemusik yang tak sadar benar akan dirinya dan menjadi konsumsi para pendengar yang ‘bertipe penurut yang “ritmis” dan tipe “emosional” (Adorno dlm Storey, 1996) tanpa pernah punya keinginan melawan pendiktean pasar akan menjadi sungguh tak berarti, semacam sampah. Namun demikian penulis percaya bahwa masih ada dan akan ada dari musik industri, lagu-lagu yang bisa menjadi katarsis untuk para pendengarnya, tentu bila para pendengarnya sendiri punya sistem pembacaan yang bisa melampaui pendiktean dan pilihan dari pasar.
Catatan: Tulisan ini awalnya dipublikasikan di KRESS, Vol. 1 No.1, Maret 2009—Musik & Industri; hal. 12-14).