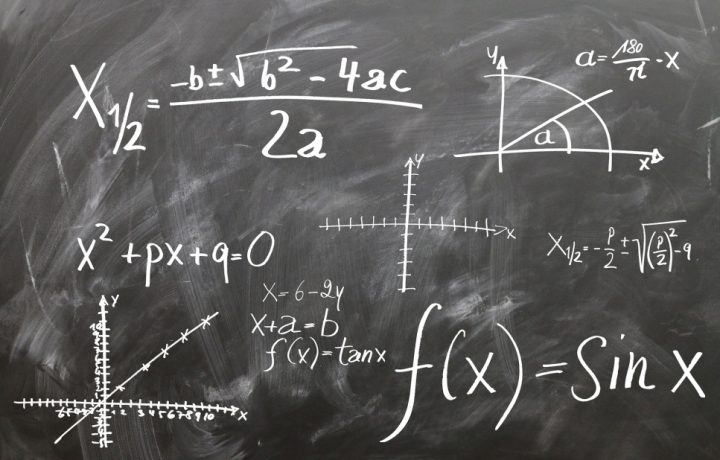Jika kita hendak melihat bentuk seni apa, sebelum membedakan antara seni ini dan itu, yang paling dekat dengan kehidupan kita, jawabannya barangkali coretan di dinding. Corat-coret di dinding, bagi kita yang hidup di tengah masyarakat dengan keteraturan tata kota yang jauh dari sempurna adalah pemandangan sehari-hari. Bahkan siapa pun, pada salah satu periode hidupnya pernah melakukan itu. Pada masanya, coretan di dinding adalah ungkapan protes yang tak terwakilkan oleh media apa pun. Bagi kita yang kenangan erah 1990-an masih lekat tentu tidak lupa pada lagu Iwan Fals yang liriknya kira-kira begini: coretan dinding membuat resah/resah hati pencoret mungkin ingin tampil/tapi lebih resah pembaca coretannya/ sebab coretan dinding/adalah pemberontakan kucing hitam/yang terpojok di tiap tempat sampah/di tiap kota…. Barangkali lirik lagu Iwan Fals yang entah mengapa tak hilang dari memori kepala saya inilah yang membuat asosiasi saya pada coretan dinding pertama-tama adalah sebuah bentuk pemberontakan. Pemberontakan atas apa; itu tergantung pada konteks masing-masing coretan dinding.

Kultur coretan dinding ini rupanya punya penggemar dan pengikut yang begitu banyak, sangat masif. Sejak Street Dealin oleh Gardu House sebanyak dua kali berturut-turut diadakan di Gudang Sarinah Ekosistem, saya menyaksikan sendiri kemasifan itu. Bukan berarti sebelumnya saya tak tahu perihal kemasifan kultur ini; tetapi melihat dengan mata kepala sendiri berkumpulnya para pegiat grafiti dan seni jalanan di satu tempat dalam waktu beberapa hari tentu memberi kesan yang berbeda tinimbang hanya melihatnya dari jejak-jejak karya corat-coret mereka di sudut-sudut kota. Oh ya. Sebelum lebih jauh, saya menggunakan istilah coretan dinding di sini untuk semua fenomena karya, baik yang tertata apik mau pun tidak, di tembok-tembok kota atau kampung.
***
Apa sebetulnya motivasi dari para seniman corat-coret ini, tentu saja sangatlah beragam. Bisa saja ada yang hanya mengikuti arus, ada yang punya tujuan-tujuan kampanye ke publik, atau juga sekadar kurangnya tempat berekspresi. Tentu masih banyak motif lainnya yang bukan di sini tempat untuk mendaftarkan semuanya. Namun, perihal kemasifan ini yang menarik perhatian saya. Jika memang corat-coret di dinding bisa kita temukan hampir di segala tempat, baik di kota mau pun desa, maka bentuk seni inilah yang paling demokratis; dalam pengertian dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Di dalam konteks ini, maka seni corat-coret pun tak bisa lepas dari pesannya yang bisa apa saja. Di sinilah kehadiran para seniman corat-coret ‘panutan’ para pencinta dunia corat-coret menjadi berarti. Dari mereka kita akan melihat, karena keseriusan mereka dengan medium ini, pesan-pesan mereka yang tertentu dan konsisten dari hari ke hari. Karena mereka adalah panutan, maka seni corat coret tidak sekadar corat-coret ini perlahan berterima. Di sini, peran mereka adalah agen.

Dengan adanya festival semacam Street Dealin, para seniman corat coret ‘panutan’ ini berkesempatan dikorak-korek oleh kawula budaya corat-coret lainnya. Di dua kesempatan Street Dealin di Gudang Sarinah Ekosistem, transfer pengalaman dan pengetahuan ini, dengan cara santai tentu saja, terjadi perlahan-lahan. Barangkali memang budaya seni corat-coret berada di aras itu; santai, penuh budaya kongkow, dan tak perlu hal-hal yang ribet. Dengan begitu, perkembangannya yang alamiah, meski pun perkembangan teknologi dan ekonomi serta budaya tidak membuatnya segampang itu organik, bisa terjadi. Kealamiahannya inilah, pada hemat saya, membuatnya bisa ada di mana-mana.
***
Kembali lagi pada semangat seni corat-coret yang saya ambil dari kutipan lagu Iwan Fals di atas. Jika kita membaca penelitian-penelitian perihak seni corat-coret, terakhir yang saya baca adalah tesis dari Pascasarjana Universitas Sanatha Dharma karya Syamsul Barry bertajuk Seni Jalanan Yogyakarta, memang perbincangan seputar bentuk seni yang ini tidak lepas dari usaha pemberontakan tersebut. Selalu saja ada corat-coret di dalam demonstrasi misalnya. Dari karya Syamsul Barry itu juga dikatakan bahwa di era revolusi fisik, Persagi dan juga PTPI (Pusat Tenaga Pelukis Indonesia) sudah membuat baliho dan spanduk protes seperti itu di jalanan. Sedangkan, masih menurut Syamsul Barry, grafiti di jalanan mulai marak di Indonesia pada era 1980-an. Tentu saja, berarti sudah ada bibit-bibitnya sebelum itu.

Penelitian Barry mengatakan bahwa kemunculan grafiti ini bersamaan juga dengan kemunculan budaya breakdance dan gank di kalangan anak muda. Ia, Barry, melihatnya sebagai pengaruh dari kemunculan budaya serupa di Eropa pada era 1970-an. Budaya punk punya sumbangsih besar pula untuk itu. Dengan penuh terima kasih pada penelitian Barry, fenomena kemunculan corat-coret di dinding di desa-desa yang terkadang bertuliskan sekadar “merdeka atau mati” atau “Bung Karno Sang Fajar” misalnya—corat-coret demikian ini terakhir bulan lalu saya lihat di wilayah Cisarua, Puncak—belum terjelaskan. Apakah corat-coret yang demikian adalah anak lain dari budaya grafiti era 1980-an itu ataukah ada hal lain yang melatarinya?
Pertanyaan-pertanyaan yang demikian saya kira memang perlu terus ditanyakan agar ada kesadaran pada kita untuk juga mengarsipkan, atau mencatat, perkembangan seni corat-coret ini. Problemnya, seni corat-coret adalah, di satu sisi, seni yang melawan kemapanan. Kemapapan dicirikan juga oleh ketercatatannya secara baik. Maka, kendala besar dalam upaya pencatatan seni corat-coret adalah upaya itu berjalan berlawan arus dengan apa yang hendak dicatatnya. Itulah tantangan utamanya. Bukan berarti tidak bisa dilakukan tentu saja. Timor Leste misalnya pernah menerbitkan buku perihal corat-coret di masa perjuangan untuk merdekanya dari Indonesia. Entah keterbatasan pembacaan saya—dan jika itu benar maka itu sangat membahagiakan—buku serupa itu, di dalam konteks Indonesia, belum pernah saya temukan.***

Catatan: tulisan ini ditulis pada awal 2018 sebagai catatan atas Street Dealinnya Gardu House edisi 2017. Saya tak ingat betul apakah tulisan ini sekadar saya tulis saja atau ketika itu memang direncanakan untuk dipublikasikan.