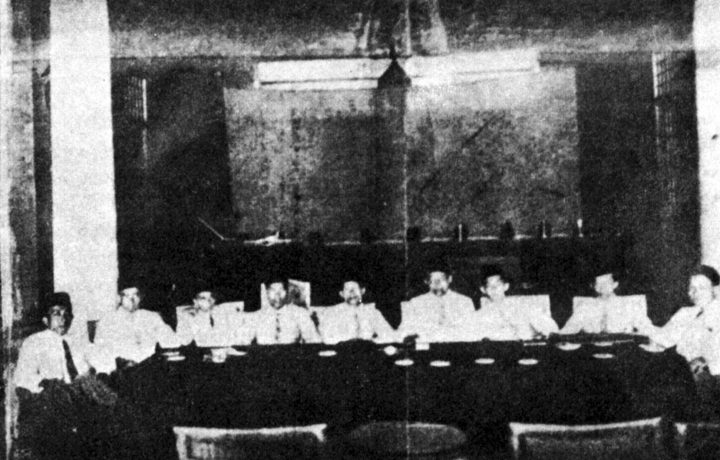KALI ini kita akan sedikit puitis, karena saya hendak berbicara tentang waktu. Dan waktu, kerap membawa kita pada gambaran-gambaran keindahan tertentu, katakanlah, kerap romantis. Sebut saja sebuah kata benda waktu yang sungguh dipautkan dengan imajinasi-imajinasi keindahan; senja. Keindahan yang saya maksud bukan sesuatu yang selalu baik adanya. Sebagai contoh, pada drama klasik Yunani yang indah selalu juga disertai tragedi.
Senja secara denotatif adalah kata benda yang merujuk pada keadaan ‘setengah gelap sesudah matahari terbenam.’ Secara konotatif, janganlah ditanya. Senja dalam Senja di Jakarta-nya Mochtar Lubis menjadi kiasan akan kebobrokan aparat pemerintah dan politikus di Indonesia pada era 1950-an. Sedangkan Senja dalam Negeri Senja-nya Seno Gumira Ajidharma bisa kita baca sebagai kiasan negeri penuh sensor, terror, horror. Singkatnya otoritarianisme a la Orde Baru.
Selain dua contoh di atas, kita bisa membuat daftar panjang untuk makna konotatif senja. Namun apa yang tercipta di dalam imajinasi tetap dimungkinkan oleh senja secara denotatif. Dan senja secara denotatif hanyalah ekspresi dari sebuah keadaan alam tertentu. Ketika perputaran bumi pada porosnya membawa wilayah Indonesia yang berada di bujur dan lintang tertentu itu berada pada posisi hendak membelakangi matahari, saat itulah senja tercipta. Keadaan alam yang demikian menciptakan beragam gambaran dan sensasi. Matahari yang ngumpet di balik bukit, gemawan yang menjelma jingga, semburat merah di langit, secuil kelam mengintip dari timur, dan masih banyak lagi. Lantas terciptalah makna, refleksi, kesan dari senja yang beragam. Singkatnya, bagaimana pun juga isi kepala kita tentang senja—dengan demikian juga waktu—dikondisikan dengan satu dan lain cara oleh keadaan alam. Selain keadaan alam, secara praktis, waktu pun ditentukan oleh modus produksi yang ada.
Tidak heran, waktu yang kita hidupi saat ini ditentukan oleh kapitalisme. Waktu yang kita kenal sekarang tidak bisa tidak adalah produk modernitas. Konon khabarnya, penentuan standar waktu dengan berpatokan pada salah satu kota di Inggris dilakukan dalam rangka penyamaan jadwal kereta di seantero Eropa. Dengan standarisasi itu, jadwal kereta pun menjadi lebih teratur. Demikian juga komunikasi dan transportasi seantero Eropa. Tentu di balik semua itu ada modus ekonomi yang melatarinya. Industrialisasi pun memanfaatkan waktu dan lantas menjejalkan keteraturan waktunya pada kita. Secara otomatis tubuh kita terjaga di pukul 4:00 – 7:00. Secara otomatis tubuh kita butuh makan pada pukul 11:00 – 13:00. Secara otomatis, mata kita lelah pada pukul 22:00 – 24:00. Semuanya menjadi serba otomatis, terkesan wajar dan biasa-biasa saja. Dan kapitalisme bekerja juga melalui waktu lebih kerja yang tidak diperhitungkan dalam upah.
Di nusantara, tentu saja waktu, sebagaimana yang kita kenal sekarang, datang bersama kolonialisme. Jika mengikuti waktu tradisional yang bergantung pada alam maka penjarahan yang dilakukan kompeni tidak berjalan maksimal. Pengaturan waktu a la modern pun diperkenalkan. Tentu tidak tanpa perlawanan. Sisa-sisa perlawanan atasnya masih bisa kita endusi dalam frase ‘waktu karet’ alias ngaret. Demikian pula penanggalan yang kita kenal sekarang. Untuk kerja, liburan, hari-hari raya, kita berpegang pada penanggalan Romawi, sedangkan penanggalan tradisional tinggal sebagai ramalan-ramalan nasib hidup. Tentu saya tidak bermaksud bernostalgia dan mengajak kita untuk kembali pada penanggalan tradisional itu.
Kembali pada senja, ia adalah bagian dari hari dan hari adalah bagian dari bulan dst. Kita lantas sampai pada sistem penanggalan; sebuah representasi waktu yang kita pegang. Pada kalender itulah sedikit banyak hidup kita ditentukan. Secara otomatis kita mengingat sebuah peristiwa yang terjadi jauh di masa lalu. Kita mengenang kesaktian Pancasila, mengenang kemerdekaan, mengenang hari ibu, dsb. Kalender kita tentu tidak merekam dan menuntut kita mengingat semua hal dan peristiwa. Tetapi melalui kalender, secara tak sadar ingatan kita akan masa lalu diseleksi. Pada kalender seleksi atas ingatan ini terjadi terus menerus dan berulang, begitu juga pemahaman akan masa lalu. Kalender barangkali sebuah alat cuci otak yang ampuh. Pun pula alat mengenang yang ampuh. Hari perempuan, hari buruh adalah contohnya.
Dan sebentar lagi, kalender kita akan berputar ulang pada titik awal. Kita sebentar lagi akan kembali mengulang pada tahun 2014 apa-apa yang kita kenang dan kita ingat di tahun 2013. Kita tengah berada di senja-nya 2013. Kita dengan demikian akan memasuki lagi alat cuci otak yang sama dan atau alat mengenang yang sama. Dalam rutinitas yang akan datang, kita lagi-lagi terus berusaha melawan lupa atau kebalikannya terus melupakan. Tetapi sungguh benar juga bahwa melawan lupa pun harus berlanjut ke taraf berikutnya. Ketika mengingat sudah sampai pada taraf yang maksimal, kita harus melakukan sesuatu atas ingatan tersebut. Namun sebelum itu, pertanyaan yang patut dijawab adalah sudah sesosial apakah laku melawan lupa? Barangkali kutipan dari Walter Benjamin ini bisa menjadi jawabannya, ‘kalender berbentuk lingkaran dan untuk mengubah masyarakat, kita harus mengubah kalender. Hal ini untuk mengubah masa lalu yang hidup dalam lingkaran tersebut pada kesekarangan kita.’
Dengan demikian, selamat merayakan senja 2013. Kita akan memasuki 2014 dengan rutinitas tahunan Pemilu dan setengah abad minus satu tragedi 65.***
*Catatan: Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Rubrik Oase IndoProgress, 29 Desember 2013.